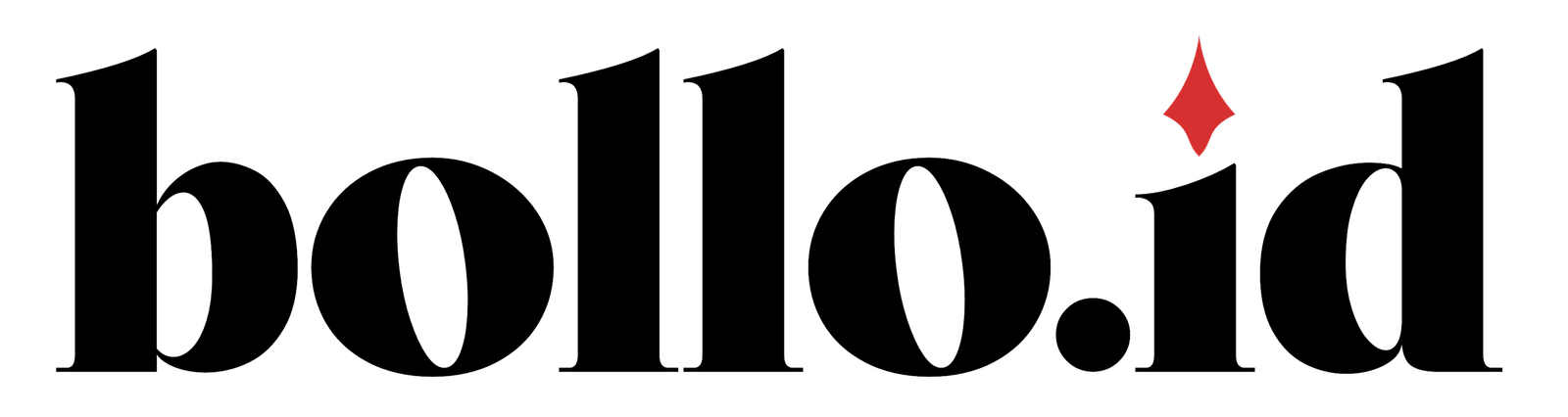Daeng Ngenang menggebu-gebu, ketika bercerita soal nasib lahan taninya yang telah berubah menjadi lahan ladang tebu di bawah kuasa Hak Guna Usaha milik PT. Perusahaan Nusantara XIV, salah satu badan usaha milik negara.
Mimik kesal. Tatapan tajam, berkaca-kaca. Dulu, lahan bisa digarap demi memenuhi keperluan sehari-hari. Berbagai tanaman hidup subur di atas lahan milik Daeng Ngenang: Ubi, jagung, padi, pisang, hingga beragam sayur. Tanaman itu tidak hanya cukup untuk kebutuhan pangan keluarga, tetapi memenuhi dimensi kebutuhan lain seperti pendidikan hingga kesehatan.
“Kalau dulu tidak diambil lahan ta, mungkin bisa sekolah seperti kalian,” kata Daeng Ngenang.
Daeng Ngenang bermukim di Lassang Barat, sebuah desa di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, berjarak 28 kilometer dari Makassar, Ibu Kota Sulawesi Selatan. Lassang Barat merupakan salah satu desa dari sebelas desa di Kecamatan Polongbangkeng Utara yang menjadi tempat perputaran ekonomi nasional perusahaan raksasa PTPN XIV.
Daeng Ngenang, seorang perempuan paruh baya, yang sejak dua puluh tahun menghabiskan waktunya ‘berkawan’ dengan sapi setelah lahan tani miliknya dikuasai PTPN XIV melalui Hak Guna Usaha (HGU). Sejak fajar, Daeng Ngenang bersama sapinya akan berada di tepi lahan itu. Saban hari, hingga petang.
“Saya sudah capek jadi penggembala,” kata Daeng Ngenang pada saya. “Makanya saya masih terus berjuang untuk kembalikan lahanku.”
Baca:
- Sisi Kelam Hutan Pinus: Folk bagi Orang Kota, Bencana bagi Orang Desa
- Pemilu masih Ableisme: Apa yang Harus Dilakukan Penyelenggara?
- Mereka yang Dibenci tapi Dibutuhkan
Ia menjadi penggembala sapi antara tahun 2002 dan 2003, pascamenikah dengan Daeng Nakku, seorang laki-laki kelahiran Parangluara. Tidak ada pilihan selain tinggal di desa dan menjadi seorang penggembala. Sementara suaminya bekerja sebagai tukang batu atau buruh bangunan di Makassar.
Tidak hanya Daeng Ngenang yang berubah profesi sebagai penggembala, hampir seluruh perempuan di Kecamatan Polongbangkeng Utara yang tidak memiliki privilese pendidikan juga menjadi penggembala sapi, sementara para laki-laki akan ke Makassar menjadi buruh bangunan atau kerja serabutan.
Ya. Perubahan profesi ini berlangsung lantaran perempuan yang harus tinggal di rumah sementara laki-laki keluar mencari penghidupan lain. Kalau dulu, menjadi penggembala bukanlah pekerjaan prioritas, karena sapi-sapi bisa bebas dilepas di atas lahan milik sendiri sembari bertani.
Perempuan dan laki-laki juga sama-sama melakukan aktivitas pertanian. Namun kini, menjadi penggembala adalah profesi yang lumrah di desa ini, karena sapi-sapi harus dijaga agar tidak merusak perkebunan tebu milik perusahaan. Bahkan sebenarnya tidak diizinkan. Sapi mereka tidak dibiarkan merumput di tepi ladang tebu PTPN XIV.
Dari perubahan kebiasaan tersebutlah maka muncul istilah ‘Janda seminggu’ di daerah ini. Istilah yang menggambarkan kebiasaan perempuan ditinggalkan selama seminggu lamanya oleh suami mereka. Alasannya sederhana, demi keselamatan.
“Kalau sudah kerja baru balik ke sini kan jauh, rawan juga di perjalanan,” kata Daeng Ngenang. “Mending tinggal di sana. Hari Sabtu atau Minggu baru pulang ke rumah.”
Sejak 1983 saat pertama kali PTPN XIV masuk memang upaya perlawanan sudah dilakukan, termasuk keterlibatan perempuan di dalamnya. Sebut saja ketika aksi pertama pada tahun 2008 yang dilakukan di depan pabrik gula PTPN XIV. Kala itu, aksi mereka berujung bentrok dengan aparat keamanan. Para perempuan yang ikut bahkan mengalami luka. Jangan tanya soal trauma.
Tapi itu tidak berlaku bagi perempuan-perempuan di Desa Parangluara dan Lassang Barat. Daeng Ngenang bahkan menjadi saksi bagaimana brutalnya polisi mengejar warga yang menuntut hak mereka sampai ke rumah-rumah warga.
Di sisi lain, ada Daeng Ati, sosok perempuan hebat yang juga masih berdiri tegak di barisan masyarakat sipil berhadapan dengan pemerintah dan perusahaan. Meski posisinya mungkin berada di antara garis pemisah, tetapi isi kepala dan sikapnya, jelas bersama warga yang terkena dampak dari ekspansi ladang PTPN XIV.
Perempuan berumur 50 tahun lebih ini sudah hampir 10 tahun menjadi bagian dari birokrasi pemerintah Desa Lassang, sebagai Sekretaris BPD Desa Lassang Barat. Bekerja sebagai sekretaris BPD memang posisi yang sangat dilematik bagi Daeng Ati, tetapi juga untuk beberapa hal posisi ini cukup menguntungkan kelompok oposisi di desanya.
Daeng Ati merupakan gambaran nyata bagaimana beban ganda sebagai seorang perempuan itu bekerja. Di mana selain bekerja sebagai aparat desa, ia juga adalah seorang guru mengaji untuk anak-anak di masjid Desa Lassang Barat. Daeng Ati juga seorang ibu rumah tangga, bahkan nyaris 3 tahun ia telah menjadi kepala keluarga lantaran suaminya sakit dan tidak bisa lagi bekerja. Daeng Ati mau tak mau juga merawat suami sekaligus anak-anaknya.
Lalu dalam konteks hubungan Daeng Ati dengan konflik agraria, Daeng Ati juga menjadi salah satu perempuan petani yang kehilangan tanah warisan orangtuanya lantaran diubah menjadi ladang tebu oleh pemerintah lewat PTPN XIV.
Meskipun disibukkan dengan segudang pekerjaan domestik dan publik, ia tetap vokal dan cukup sering terlibat dalam upaya-upaya menuntut kembalinya lahan dari perusahaan. Keluar kota menceritakan kisah perjuangannya, berjaring dengan perempuan-perempuan lintas daerah juga ia lakukan sebagai bagian dari upaya tetap waras di negara yang sudah lama kehilangan akal sehatnya.
Sementara itu ada juga Mama Paning, perempuan yang umurnya mungkin saja hampir sama dengan umur bangsa ini. Mama Paning duduk di pondok yang berdiri sejak dua tahun lalu, dikepung hamparan tebu milik perusahaan PTPN XIV—yang ditanam di atas lahan miliknya.
Kalau di beberapa tempat gambaran soal konflik agraria kental dengan isu maskulin, Mama Paning adalah salah satu representasi dari bagaimana isu feminin itu bekerja.

Muak dengan janji perusahaan yang katanya akan mengembalikan tanah milik warga sehabis Hak Guna Usaha berakhir, Mama Paning satu-satunya warga sekaligus perempuan yang melakukan perlawanan dengan caranya sendiri.
Dia akan meracun tanaman tebu milik perusahaan yang tumbuh di atas lahannya sedikit demi sedikit, petak demi petak, hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan. Hingga kini hampir 4 tahun aksi reklaimingnya itu ia lakukan. Dan ia telah menguasai kembali lahannya seluas kurang lebih 50 are. Isinya ada ubi jalar, kacang panjang, ubi kayu, pisang, dan jika musim hujan akan ada padi juga.
“Setiap subuh, pergi ka ke kebunku, bawa racun, kuracuni mi satu baris itu tebu. Seminggu kemudian, ku cabut akarnya, dan mulai mengolah tanahnya lagi supaya bisa ditanami ubi, jagung, dan lain-lain,” ceritanya pada saya.
Intimidasi dari pihak keamanan perkebunan tebu kerap menyasar Mama Paning. Bahkan surat panggilan polisi dengan dalil penyerobotan lahan yang dilakukan oleh Mama Paning datang bagaikan surat cinta. Namun Mama Paning bilang, selama untuk kebenaran dan itu adalah haknya, ia akan maju paling depan.
“Kalau ditanya, kenapa ko berani racuni atau ambil itu lahan?” Mama Paning akan balik bertanya. “Tanya juga kenapa itu perusahaan juga berani ambil tanahku”
Saya bertanya kepada Mama Paning, bagaimana jika dia berhadapan dengan aparat.
“Saya dan Polisi itu sama, cuman baju kita yang berbeda,” jawabnya.
Aksi reklaiming yang dilakukan Mama Paning merupakan akumulasi kemarahan dari kesemena-menaan negara dan pemodal dalam merebut ruang penghidupan masyarakat. Dan sampai saat ini, Mama Paning masih terus berkebun sambil sesekali ikut berkumpul, berdiskusi dengan organisasi tani mereka.

Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Kilas Balik Penguasaan Lahan
Polongbangkeng Utara adalah salah satu kecamatan di Takalar yang lahir dan dikuasai oleh Raja Kepolongbangkeng bernama Gallarrang. Dari tradisi tuturan, Gallarang ini berasal dari Palleko, salah seorang Karaeng bernama Salemo Daeng Lira. Di mana Polongbangkeng ini dinamai Lassang sebelum akhirnya bernama Kecamatan Polongbangkeng.
Konon katanya setiap kali Raja Gallarang berkunjung ke wilayahnya, ia selalu mengklaim setiap daerah yang disinggahinya sebagai tanah miliknya. Mulanya raja itu singgah di daerah Panjojo, tetapi kemudian diberitakan oleh pengawalnya kalau di tempat itu ada ketinggian yang bagus untuk ditempati beristirahat. Itu lalu disebut dengan Anging-Mammiri artinya cari angin sepoi-sepoi atau mattoangin.
Pada kekuasaan Raja Gallassang pertama (I), ia memerintahkan untuk setiap masyarakat agar mengukur tanahnya masing-masing dan akan dibuatkan semacam bukti kepemilikan. Namun ketika itu, untuk bisa dibuatkan bukti, masyarakat diminta membayar dengan jumlah yang besar sehingga tidak semua masyarakat bisa mengakses dan mengklaim tanahnya melalui kebijakan raja tersebut.
“Jadi yang punya uang saja,” kata Daeng Ati, Sekretaris Desa Lassang Barat.
Pengukuran tanah kala itu, hanya berdasarkan dengan nama-nama yang sanggup membayar saja dan selebihnya tanah-tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan adalah milik Raja Gallarrang.
“Selebihnya itu Gallarang yang ambil,” kata Daeng Ati. “Itulah yang terjadi.”
Setelah Raja Gallarrang I Karaeng Salemo Dg Lira meninggal, kekuasaan digantikan oleh Gallarang Parale Daeng Beta, seorang warga setempat. Tetapi entah apa yang terjadi di kampung, Gallarang Parale Daeng Beta kemudian mengasingkan diri ke Borongloe (Gowa), dan kemudian berkuasa di sana.
Di Lassang pun terjadi kekosongan jabatan, sehingga posisi tersebut digantikan oleh Gallarrang I Karaeng Salemo Daeng Lira yakni Karaeng Syamsuddin Daeng Tunru. Di bawah kekuasaannyalah PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) datang.
Baca:
Sebelum masuk, PTPN XIV di Polongbangkeng, ada perusahaan bernama PT. Madu Baru, salah satu perusahaan tebu swasta yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Perusahaan ini masuk pada sekitar tahun 1972, dan baru beroperasi pada tahun 1978.
PT. Madu Baru merupakan milik Sultan Hamengkubuwono XI, yang dibawa masuk oleh Martono salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Maksud dari tujuan Martono membawa perusahaan tebu ini untuk memajukan perekonomian masyarakat Polongbangkeng, tetapi Martono tidak melihat konflik sosial yang terjadi Polongbangkeng. Hal ini menjadi permasalahan sangat kompleks, dan maraknya pengklaiman lahan yang dilakukan oleh elite lokal.
Pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini bupati sangat kontradiktif di kalangan masyarakat. Sebabnya, lahan yang diambil oleh pihak pemerintah dan perusahaan swasta itu justru melibatkan aparat keamanan TNI dan kepolisian—waktu ABRI—untuk mengosongkan lahan masyarakat Polongbangkeng.
Pengosongan lahan itu diwarnai protes dan membuat banyak korban berjatuhan dan luka-luka. Kekerasan aparat keamanan sudah di luar kendali, sehingga mengharuskan masyarakat menandatangani kesepakatan pembebasan lahan. Dugaan pelanggaran HAM pada 1980-an tersebut sampai saat ini tidak pernah diadili, bahkan di tutupi oleh pemerintah.
Pada tahun 1978 terbitlah Surat Keputusan dari Bupati terkait izin Perkebunan Tebu kepada pihak PTPN XIV, tanpa didasari penyampaian informasi atau kesepakatan semua pihak khususnya masyarakat yang pada dasarnya adalah pemilik lahan. Selama rentan waktu 1978 hingga 1979 pemerintah kemudian melakukan pengukuran tanah yang kelak dipakai untuk perkebunan.
Pada saat itu tidak ada yang berani melawan atau membangkang ketika Raja meminta tanah masyarakat agar dijadikan perkebunan. Warga dipaksa untuk mengontrakkan lahan mereka agar ditanami tebu oleh PTPN XIV.
Proses pembebasan lahan kemudian dilakukan pada 1981 oleh Karaeng Tunru yang pada saat itu sebagai perwakilan pemerintah desa.
“Kalau tidak mau menyerahkan tanahnya, tidak boleh lagi tinggal di Polongbangkeng,” tutur Daeng Ati. “Bahkan kalau ada yang berani bicara, dibantai oleh orang-orangnya.”
Proses pengambilan lahan milik masyarakat pun dilakukan. Lahan produktif yang selama ini ditanami padi, ubi, jagung, dan beragam jenis pohon pun diratakan dengan tanah.
“Tanaman yang bermacam-macam, tempat produksi batu-bata dan keindahan panorama hamparan yang dihiasi irigasi dengan pemandangan yang indah digusur dan diratakan dengan tanah,” Daeng Ati bercerita.
Lalu pada tahun 1981 hingga 1982 perusahaan kemudian melakukan penanaman tebu. Lantaran tidak ada pilihan, warga lokal pun menjadi buruh perkebunan. Menanam,
memupuk, merawat, menyemprot, bahkan sampai proses panen dan memastikan tebu telah terangkat ke mobil truk untuk dibawa ke pabrik.
Mereka bekerja mulai pukul 08.00 hingga 16.00 dengan besaran upah hanya Rp15 ribu per hari. Upah itu akan dibayarkan setiap 20 hari kerja.
“Ada yang jatuh sakit dan tidak kuat lagi akhirnya meninggal membawa sakit penindasan yang dialaminya dengan keputusasaan,” cerita Daeng Ati.
“Bahkan ada yang gila dan sebagian memilih merantau demi kelangsungan hidupnya, ada yang putus sekolah dan ada juga yang ikut keluarga merantau sampai ke Malaysia.”
Pada tahun 1983 pemerintah desa berkeliling ke rumah-rumah warga untuk melakukan pendataan bukti kepemilikan tanah dengan alasan akan dilakukan pembaharuan. Namun bukannya diperbaharui, pemerintah desa diduga malah membakar surat-surat bukti kepemilikan warga seperti rinci dan lain-lain.
Ketika itu juga sebagian masyarakat ada yang hanya dibayar dengan menghitung jumlah pohon yang ada di atas tanahnya. 200 pohon dihargai sebesar Rp218 ribu, kemudian pajaknya dipotong, menjadi Rp198 ribu. Meskipun lahannya telah dikuasai sepihak oleh PTPN XIV.
Beberapa diberikan ganti rugi sebesar Rp1.250 per pohon. Ada juga yang berdasarkan luasan lahan, di mana lahan sebesar 30 are dihargai sebesar Rp300 ribu.
Pihak perusahaan menjanjikan akan mengembalikan seluruh tanah warga setelah 25 tahun dan selanjutnya untuk menunjang produksi, perusahaan mulai membangun pabrik gula pada tahun yang sama yakni 1983.
Waktu terus berjalan, masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa di bawah kekuasaan pemerintah desa yang juga dari keturunan raja. Menunggu adalah pilihan terbaik. Apalagi pihak perusahaan sudah menjanjikan akan mengembalikan lahan warga setelah 25 tahun atau ketika Hak Guna Usaha berakhir.
Di tengah proses produksi yang terus dilakukan perusahaan, berhembus kabar kalau HGU PTPN XIV baru terbit pada tahun 1998. Hampir 16 tahun lamanya PTPN XV diduga melakukan aktivitas perkebunan tanpa HGU. Yang artinya selama kurun waktu tersebut pihak perusahaan juga meraup keuntungan besar karena tidak membayar kepada Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP No. 40 tahun 1996 Tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah.
Dan tahun 2023 dan 2024 ini, merupakan tahun di mana HGU telah berakhir, seyogianya perusahaan beritikad baik untuk mengembalikan tanah masyarakat seperti janji mereka 25 tahun lalu.
“Tanah bukan hanya tentang harta, tetapi tanah adalah kehidupan kami,” teriak Daeng Ati, di atas mobil komando saat mengikuti aksi penolakan perpanjangan HGU PTPN XIV Takalar, pada 5 Maret 2024 lalu.
“Kalau tahun ini kami tidak berjuang merebut kembali tanah kami, kami akan menunggu 25 bahkan 30 tahun lagi untuk sampai pada hari ini. Untuk itu, kami perempuan akan berjuang.”