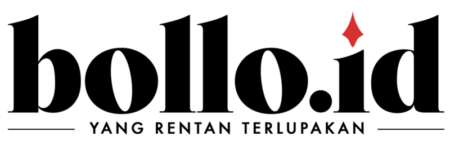Selama puluhan tahun masyarakat adat Kajang memperjuangkan tanahnya yang dicaplok PT Lonsum. Penjaga Hutan Hujan Terbaik Dunia itu telah melayangkan gugatan di pengadilan, reklaiming, demonstrasi, sampai audiensi yang tak terhitung jumlahnya. Balasannya: kekerasan dan trauma.
***
“Rumahku dibakar,” kata Tia.
Kejadiannya di suatu malam di tahun 1987. Tia yang saat itu hamil anak pertama, baru saja pulang dari pesta kawinan, lalu mendapati rumahnya sudah rata dengan tanah.
Tak ada peringatan sama sekali. Pakaian dan barang-barang berharga hingga padi yang ada di dalam rumahnya habis disambar api.
Pembakaran dilakukan terang-terangan. Warga yang ada di rumah malam itu, dipaksa keluar – sebelum rumahnya dibakar.
Mereka yang melawan dianiaya: dipukuli sampai dicabut kukunya.
Saking banyaknya rumah dibakar, Tia tak pernah tahu berapa jumlah pastinya.
“Banyak rumah dibakar. Banyak sekali.”
Kebun juga disasar. Jagung, pisang, dan sayuran lain dibabat, dilindas mobil person, lalu dibakar. Desa Tukumba – sekarang Bonto Mangiring, Kecamatan Bulukumpa – malam itu, dipenuhi titik api.
“Habis semua di situ. Rumah, tanaman,” ujar Tia.
Tidak ada yang tahu persis siapa yang membakar. Tapi orang-orang yang ada di kampung, termasuk Tia, menduga pelaku pembakaran berasal dari orang suruhan PT Lonsum.
Tia, adalah warga Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Perempuan adat yang hingga kini memperjuangkan tanahnya. Pembakaran rumahnya adalah satu titik mula konflik agraria masyarakat adat Kajang melawan PT Lonsum.
Lonsum adalah akronim dari Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia. Perusahaan yang didirikan tahun 1906, oleh grup perusahaan perkebunan raksasa asal Inggris, Harrisons and Crossfield.
Singkatnya, Lonsum menancapkan jangkar bisnisnya di Bulukumba pada tahun 1919. Melalui Penanaman Modal Asing (PMA) untuk perkebunan dengan nama NV Celebes Landbouw Maatschappij. Kala itu, mereka menguasai lahan seluas 7.092,58 hektare dengan status hak erfpacht.
Pada 17 April 1961, setelah muncul Undang-Undang (UU) Pokok Agraria Tahun 1960, statusnya berubah jadi Hak Guna Usaha (HGU). Luas lahan yang dikuasai perusahaan itu juga berubah jadi 6.592,82 hektare.
Sekarang saham Lonsum dikuasai PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood). Perusahaan milik Anthony Salim, salah satu orang terkaya di Indonesia. Satu dari bohir yang dijuluki sembilan naga.
Lonsum kini menguasai lahan 5.784,46 hektare berdasarkan Surat Keputusan (SK) HGU tahun 1997. Luasnya setara 8.101 lapangan sepak bola dengan ukuran standar FIFA.
Konsesi ini terbentang di lima kecamatan: Kecamatan Bulukumpa, Kajang, Ujungloe, Herlang, dan Rilau Ale. Dibanguni kantor, perumahan karyawan, fasilitas olahraga, dan ditanami pohon karet.
Pohon-pohon itu terhampar, berjejer bak tentara yang berbaris. Rapinya jajaran pohon yang hijau, memukaunya fasilitas olahraga seperti lapangan tenis, kerap digunakan sebagai latar berfoto.

Di balik itu, tidak banyak yang tahu, kebun monokultur tersebut dulunya tumbuh pisang, jagung, mangga, dan tanaman lainnya milik masyarakat.
Tidak banyak yang tahu, dulunya pohon-pohon itu adalah hamparan lahan tempat masyarakat melepas ternak. Dan tidak banyak yang tahu, pepohonan hijau itu dulunya adalah alat produksi masyarakat adat yang digarap sebagai tumpuan hidup mereka.
Selain itu, tidak banyak juga yang tahu, bahwa di lahan perumahan milik karyawan itu, dulunya pernah berdiri rumah-rumah warga.
Sampai semuanya menjadi saat ini. Tidak banyak yang tahu, prosesnya menumpahkan darah, air mata, dan menyisakan trauma kolektif.
Investigasi Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut Lonsum sejak awal menginjakkan kakinya di Bulukumba disertai kekerasan. Didukung penuh pemerintah bersama aparat militer dan kepolisian (ABRI).

Selain menggusur dan membakar, cara Lonsum melakukan ekspansi dengan memberi iming-iming kesejahteraan. Baba, warga Desa Tammatto, Kecamatan Ujung Loe, adalah korbannya.
Mulanya pihak perusahaan yang datang ke kampung Baba mengatakan hidup warga tak akan mengalami peningkatan, jika hidupnya hanya mengandalkan hasil panen dari kebun dan sawah.
“Kalau padi kamu tanam, jagung, ubi jalar atau ubi kayu, kamu tidak bisa sekolahkan anakmu,” kata Baba mengenang bujuk rayu pihak Lonsum kepadanya.
Kejadian itu berlangsung di tahun 1977. Saat itu, Baba masih berusia 17 tahun.
Untuk meyakinkan warga, kata Baba, Lonsum berjanji memasukan warga jadi karyawan di perusahaan secara turun-temurun. Serta menyekolahkan anak-anak di kampung itu. Syaratnya, warga mesti menyerahkan lahan garapan mereka kepada PT Lonsum untuk dikelola jadi kebun karet.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Janji-janji itu kemudian disambut warga. Mereka setuju.
Baba misalnya, jadi karyawan PT Lonsum pada tahun 1979, dua tahun pasca perusahaan memperluas wilayahnya di Desa Tammatto, Kecamatan Ujung Loe. Di perusahaan, Baba diupah Rp 400 per hari.
“Yang masuk diambil (lahan) waktu itu, saya sama keluarga di atasnya 5 ha,” kata Baba.
Karirnya berakhir setelah Lonsum kembali melakukan ekspansi di lahan milik warga. Melalui mata kepalanya sendiri, dia melihat orang suruhan Lonsum menggunakan mobil person menyerobot lahan dan merusak tanaman jagung milik warga.
“Saya bekerja di perusahaan 11 tahun,” kata Baba yang tahun ini berusia 65 tahun.
Padahal masa panen tanaman itu tinggal sebentar lagi. Tanaman tersebut, sebenarnya bukan miliknya, bukan juga punya keluarganya. Tapi bagi Baba, tanaman itu punya nilai sendiri.
Sebagai orang yang hidup dari hasil tanah sejak kecil, dia tahu betul bagaimana susahnya merawat tanaman.
“Sakit sekali di situ hatiku. Mau ka marah, tapi sendiri ki,” kata Baba.
Perilaku pihak perusahaan itu membuat Baba tak tahan. Hari itu juga dia berjanji menanggalkan seragam PT Lonsum-nya. Dia tak lagi sudi menjadi bagian dari perusahaan yang merampas tanah warga.
“Besoknya saya langsung pergi (keluar dari perusahaan),” ujar Baba.
“Tidak ada alasan.”
Baba bukan satu-satunya korban PT Lonsum. Ada juga Kamaruddin, warga Desa Tammatto.
Luas lahan milik keluarga Kamaruddin yang diambil klaim PT Lonsum di kampung itu, seluas 20 hektare.
Lonsum mengambil alih lahan itu saat Kamaruddin masih berusia enam tahun, lalu menjadikan orang tuanya karyawan perusahaan.
“Mandor dulu orang tuaku. Mandor di perusahaan,” Kamaruddin tertawa.
Jika diuraikan, konflik PT Lonsum dengan masyarakat ini terbagi menjadi empat klaster.

Pada akhir September 2025 lalu, Bollo.Id mendatangi salah satu tanda alam dimaksud. Letaknya di Desa Tammatto, pekuburan yang berada di tengah-tengah perkebunan karet milik PT Lonsum.
Masyarakat setempat menyebut kuburan itu sebagai pekuburan tua. Beberapa pusara di sana tidak bernama dan tak jelas kapan empunya disemayamkan.
Salah satu kuburan, yang terbilang baru, di nisannya tertulis Suhardi, meninggal tanggal 28 bulan September 1982. Itu masa-masa ekspansi PT Lonsum di Tammatto.
“Setelah ada Lonsum, masyarakat dilarang lagi gunakan ini kubur,” kata Baba “Jadi warga cari tempat lain untuk pekuburan.”

Kuburan itu dianggap sebagai bukti bahwa warga sudah menguasai lahan tersebut sebelum Lonsum datang.
Jika merujuk empat klaster konflik di atas, tidak semua konflik lahan PT. Lonsum memang melawan masyarakat adat. Hal ini dibenarkan Tendri Itti, masyarakat adat Kajang, yang juga Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel.
Lalu kenapa konflik ini selalu dihubungkan dengan masyarakat adat Kajang?
Itti menghela napas. “Jadi begini,” kata dia memulai penjelasannya. “Wilayah adat Ammatoa Kajang itu terbagi dua.”
Rambang Seppang seluas 552 hektare, dan Rambang Luara 22.445 hektare. Berdasarkan Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015, total luasnya mencapai 22.997 hektare.
Rambang Seppang, yang ada di dalam kawasan Ammatoa, tempat yang tidak boleh dimasuki modernitas. Disebut juga dengan Ilalang Embayya atau wilayah adat inti.
Wilayah ini mencakup sejumlah desa di Kecamatan Kajang: Desa Tanah Toa, Pattiroang, Bonto Baji, dan Malelleng. Hutan suci seluas 313 hektare, yang belakangan disebut Hutan Adat Kajang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6746, berada di wilayah ini.

Sementara Rambang Luara terhampar di empat kecamatan di Bulukumba: Kecamatan Kajang, Bulukumpa, Ujung Loe, dan Herlang. Meski bukan wilayah adat inti, Itti mengatakan mereka yang tinggal di Rambang Luara juga ada masyarakat adat.
“Semuanya masyarakat adat. Yang tinggal di luar (bahkan bukan di Kajang) pun masyarakat adat, selama mereka masih menjalankan ritual dan tradisi,” terang Itti.
Definisi masyarakat adat, menurut Itti, tak disempitkan pada letak domisili. Jika dikontekskan pada empat klaster konflik PT Lonsum dengan warga, memang ada yang di luar wilayah adat dan bukan masyarakat adat. Yakni masyarakat Bulukumpa Toa dengan luas sekitar 254 hektare.
Tapi bagi Itti, semua orang berkedudukan sama memperjuangkan haknya. Entah dia masyarakat adat atau bukan.
***
Terusir dan Menderita
Perampasan lahan milik warga oleh PT Lonsum telah menyisakan luka mendalam. Tanah-tanah yang dulunya dikelola warga jadi sawah dan ladang sebagai tumpuan hidup keluarga, telah berubah jadi kebun karet.
Kondisi ini membuat masyarakat adat harus memilih diantara dua pilihan. Apakah mereka tetap bertahan di kampung itu atau pergi mencari kehidupan yang baru.
Gani misalnya, seorang warga yang menjadi korban perampasan lahan di Kecamatan Kajang, Bulukumba sempat meninggalkan kampung halamannya.
Saat itu, Gani merantau ke Kabupaten Bone, Sulsel. Di sana dia bekerja sebagai tukang becak untuk dapat melanjutkan hidup. Semua ini dilakukan Gani karena tanah garapannya yang ada di kampung dirampas perusahaan.
“Saya juga pernah di Bone tiga tahun, jadi tukang becak,” kata Gani.
Selain Gani, warga yang tinggal di lingkungan kawasan adat inti, sebuah kawasan yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisi adat Kajang karena tak boleh mengalami modernisasi juga banyak yang memilih meninggalkan kampung mereka.
Penyebabnya karena ruang hidup di dalam kawasan adat inti semakin hari semakin sempit.
“Keluar (karena) bertambah manusia, sedangkan tanah tidak bertambah,” kata Ramlah.
Tanah masyarakat adat yang dulunya dikelola untuk menanam berbagai macam tanaman seperti jagung dan umbi-umbian, sebagian besar telah diambil alih PT Lonsum.
Di lahan milik warga itu, pihak perusahaan menanam pohon-pohon karet yang tak ada kontribusinya bagi masyarakat adat Kajang.
“Kenapa masyarakat adat banyak yang keluar bekerja?”
“Karena di wilayahnya sendiri sudah tidak ada lagi penghidupannya. Jadi banyak yang perempuan maupun laki-laki yang kerja di luar,” Ramlah menegaskan.
Ramlah sendiri tak mempersoalkan banyaknya warga yang memilih pergi meninggalkan kampung karena dipaksa dengan kondisi, terlebih lagi ruang hidup yang ada di dalam kawasan adat Kajang inti semakin sempit.
Dia mencontohkan di dalam kawasan adat Kajang inti, sudah banyak rumah-rumah warga yang berdiri dan hanya menyisakan dua tempat pemukiman dengan hutan adat.
Padahal, saat Ramlah masih kecil, rumah-rumah warga yang berdiri di dalam kawasan adat Kajang inti itu masih dapat dihitung jari.
“Kalau mau tinggal di dalam semua, efeknya akan tidak ada lagi tanah-tanah atau hutan yang selama ini kita jaga,” terang dia.
“Jadi untuk masyarakat adat yang memang bermigrasi keluar itu, menurut kami tidak ada masalah,” Ramlah menambahkan.
Terbatasnya ruang hidup akibat perampasan lahan PT Lonsum ini juga telah memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan perempuan adat selama puluhan tahun.
Mereka yang selama ini menggantungkan hidup pada lahan garapan, banyak yang pergi ke berbagai daerah seperti ke Makassar, Sulawesi Tenggara, Kalimantan hingga merantau ke Malaysia, bekerja di perkebunan sawit.
“Banyak anak juga putus sekolah,” ungkap Itti.
Dampak lain yang dihadapi warga akibat perampasan lahan tersebut, kata Itti, ialah perempuan adat sekarang sudah kesulitan mendapatkan kayu bakar untuk memasak.
“Orang memasak tidak pakai kayu mi semua. Karena di mana mau ambil? Tidak ada mi,” jelas Itti.
Itti sendiri juga merupakan korban dari perampasan lahan oleh PT Lonsum. Menurutnya, jauh sebelum pihak perusahaan menanam pohon karet di wilayah adat Kajang, orang tuanya dulu sempat punya lahan yang luas untuk digarap jadi sawah dan kebun pada tahun 1960-an.
Itti menyebut tanah garapan orang tuanya itu dengan istilah Tanah Ongko Ammatoa Kajang, tempat masyarakat Ammatoa mencari makan.
“Sebelum penjajahan mereka sudah ada di situ,” jelas Itti.
Selain itu, dampak dari perampasan lahan oleh PT Lonsum perlahan mengikis aturan yang berlaku di dalam kawasan adat Kajang.
Itti mencontohkan peristiwa kakaknya yang harus dipenjara lima bulan hanya karena memberi makan sapi menggunakan ranting pohon yang ada di dalam kawasan adat. Kejadiannya sekitar tahun 1987-an.
“Dulu banyak ranting pohon bisa diambil. Kapan kita masuk, ditegur. Sekarang longgar mi.”
Sama seperti yang terjadi di Desa Tammatto, Ujung Loe, tempat tinggal Baba dan dua orang temannya, Amiruddin dan Kamaruddin.
Di kampung itu, warga yang sudah tak memiliki tanah juga pergi meninggalkan kampung.
“Apa mau dikerja?”
“Itu saja buruh-buruh di Makassar banyak dari Kajang,” Baba melanjutkan.
Dan kehidupan warga di kampung itu pun berubah.
“Tidak ada mi kebun, termasuk ternak. Sapi juga sempit mi (tempat makannya).”
Sementara Tia, sempat luntang-lantung kehilangan tempat tinggal setelah rumahnya dibakar. Sampai harus numpang di rumah keluarga.
Perampasan tanah itu, juga tidak hanya menghilangkan tempat tinggalnya. Tapi juga ruang hidupnya. Padahal tanah tersebut diwariskan dari nenek suaminya.
“Sekarang tidak ada mi kodong,” katanya lirih.
Sebagai petani, dia tidak punya tanah lagi untuk digarap. Bekas lahannya yang dirampas, sekarang jadi perumahan karyawan Lonsum.
Dia bersama suaminya sempat ke Makassar bertaruh nasib. Menjadi buruh bangunan, dan pekerjaan serabutan lainnya.
Sampai semua anaknya menikah. Dia kembali ke kampung. Sekarang keluarganya hidup dari berjualan dengan membuka warung kecil.
“Sisa ini,” kata Tia menengadah. Menunjukkan warung kecilnya.
Dia melanjutkan.
“Puluhan tahun kami di sini menderita.”
Mereka yang tanahnya dirampas, seakan hanya punya dua pilihan. Bertahan dengan penderitaan, atau bertaruh nasib di perantauan. Tapi Itti, Tia, Ramlah, Baba, Amiruddin, Kamaruddin, dan warga lain yang berjuang, mereka membuat jalannya sendiri.
Mereka menyalakan harapan. Tidak berpangku tangan. Mereka memilih melawan.
***
Melawan Perusahaan Raksasa
“Cuing, cuing.”
“Lewat-lewat itu peluru.”
“Ada kena. Sampai ada yang meninggal,” kata Gani kepada Bollo.Id akhir September 2025.
Warga Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba itu sedang menceritakan tragedi tahun 2003. Peristiwa berdarah dari salah satu letusan konflik antara PT Lonsum dengan masyarakat.

Saat itu, 21 Juli 2003, warga mencoba mengklaim kembali lahannya dari PT Lonsum. Pihak perusahaan melawan balik, mereka bersama aparat kepolisian berusaha membubarkan massa.
Laporan KontraS menyebut, ada 11 pegawai Lonsum dilengkapi pistol melepaskan tembakan saat situasi memanas. Lusinan polisi yang dipimpin juga melakukan hal serupa.
Dalam kejadian itu, lima orang dikabarkan terluka terkena tembak, dua lainnya tewas. Satu yang tewas di antaranya karena lukanya membusuk setelah empat hari bersembunyi di hutan. Menghindari perburuan polisi.
Selepas penembakan membabi buta itu, polisi memburu masyarakat yang diduga terlibat dalam kerusuhan. Mereka menyisir kampung-kampung hingga masuk ke Rambang Seppang atau kawasan inti adat Kajang.
Seorang masyarakat adat Kajang, Mail, yang saat itu masih duduk di Sekolah Dasar (SD) ingat betul, bagaimana polisi datang ke Rambang Seppang dengan senjata lengkap. Polisi itu menggunakan celana panjang, pakaian yang sangat asing digunakan di dalam kawasan inti.
Siang itu, Mail tengah bermain di ambang Rambang Seppang. Gapura pembatas antara Rambang Seppang dan Rambang Luara. Tiba-tiba, sekelompok polisi datang.
Saat melihat para pria dengan celana panjang itu, Mail langsung berlari, mengabarkan kepada orang-orang dewasa yang diburu bahwa polisi datang.
“Rie (ada) polisi! !Rie (ada) polisi!”
Orang-orang dewasa pun lari kocar kacir masuk ke hutan.
Perburuan itu berlangsung beberapa pekan sejak hari kerusuhan.
Di hutan, mereka yang sembunyi memakan apa yang bisa mereka makan. Kadang pula, warga lain membawakan makanan, jika tidak ada bantuan atau persediaan makanan telah habis. Dan ketika situasi dianggap telah aman, mereka akan masuk kembali ke kampung.
Ramlah, anak pemimpin spiritual masyarakat adat Kajang, Ammatoa yang kami temui menceritakan peristiwa itu. Kala itu, dia masih usia Sekolah Menengah Atas (SMA). Saat sore dan malam hari, dia melihat banyak orang yang diburu polisi datang ke rumahnya. Memohon perlindungan ke Ammatoa.
”Mereka menangis. Bertanya ke Ammatoa, ‘bagaimana nasib saya?”
“Karena takut ditangkap polisi kasian,” kenang Ramlah.
Catatan KontraS, sebanyak 36 orang ditangkap waktu itu, polisi juga mengumumkan 26 Daftar Pencarian Orang (DPO). Beberapa orang ditangkap tanpa dokumen resmi. Penangkapan itu juga disertai kekerasan, terutama saat warga ditahan di kantor polisi.
Belakangan, saat peristiwa berdarah dan perburuan itu tersebar di berbagai media. Lonsum dan kepolisian mendapat kecaman dari pegiat hak asasi manusia dan sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga turun tangan pada awal Agustus. Mereka mendapati potensi pelanggaran HAM berat dalam Tragedi 2003 berdarah itu
Di tengah berbagai sorotan, tensi ketegangan di Bulukumba mereda.
“Baru semua itu keluar yang pergi sembunyi,” ujar Ramlah.

Meski demikian, rasa takut terus membayangi masyarakat adat sampai bulan-bulan selanjutnya. Perburuan juga terus berlanjut terhadap orang-orang yang ditetapkan sebagai buronan alias DPO. Di kawasan inti Kajang, kalau ada pria yang datang mengenakan celana panjang, masyarakat tetap paranoid.
”Masih lari sembunyi.”
Di Ujung Loe, warga yang merasa tanahnya dirampas PT Lonsum juga melawan. Mereka yang dulunya tak berani kepada perusahaan karena berjuang sendirian, kini telah bersatu.
Amarah warga yang telah lama terpendam, mulai meledak di tahun 2009.
Saat itu, mereka yang berusaha merebut kembali lahannya dari cengkraman PT Lonsum bentrok, dan dihalau polisi.
“Waktu itu terjadi beberapa penembakan-penembakan terhadap masyarakat,” kata Amiruddin.
Dari situ, warga kemudian mengatur strategi untuk melawan perusahaan. Mereka mulai mengumpulkan bukti-bukti macam kepemilikan lahan milik warga yang diklaim PT Lonsum.
Setelah bukti-bukti kepemilikan lahan terkumpul, warga kemudian mendesak pemerintah daerah di DPRD Bulukumba untuk meninjau lokasi. “Jadi ada dua itu. Verifikasi data dan verifikasi lahan,” jelas Amiruddin.
Tahun 2012, menurut Amiruddin, ada beberapa pengakuan yang diterbitkan oleh pemerintah bahwa tanah yang dikuasai PT Lonsum merupakan milik masyarakat.
“Ada legalisasi secara sah dari kepala desa. Sembilan kepala desa dan satu kelurahan,” kata dia.
“Kemudian Perda tahun 2015 yang berisi tentang wilayah, Rambang Luara dan Rambang Seppang. Itu semua yang menguatkan kami sehingga memang kami harus berjuang seperti ini,” sambung Amiruddin.
Perlawanan itu terus berlanjut, hingga pada suatu ketika di tahun 2018, warga berhasil menduduki lahan mereka kembali yang diklaim perusahaan.
Di tempat itu, warga berkumpul mendirikan tenda dan mulai menanam berbagai macam tanaman jangka pendek di lahan yang berhasil mereka reklaiming.
Tapi, ketika warga telah panen dan ingin melanjutkan dengan menanam tanaman jangka panjang, pihak perusahaan mengirim karyawannya untuk berhadapan dengan warga yang ada di lokasi.
Para karyawan yang dikerahkan tersebut merupakan keluarga warga sendiri yang bekerja di PT Lonsum.
“Tetap mi kita mengalah karena saudara kita toh, bahkan anak-anak kita sendiri,” jelas Kamaruddin.
Ditahun itu, Kamaruddin bersama dengan Bupati, Kapolres, Dandim, Ketua DPRD, dan pihak pertanahan berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Di kantor Kemendagri, mereka menuntut agar tanah-tanah warga yang diklaim PT Lonsum di Kabupaten Bulukumba, Sulsel segera dikembalikan.
“Keputusan akhir itu hari, nanti habis HGU-nya. Ini sudah habis, jadi kita menuntut lagi bagaimana ini?”
***
Trauma dan Tak Pernah Kembali
Meski perampasan lahan oleh PT Lonsum itu telah berusia puluhan tahun, tetapi peristiwa itu masih melekat pada memori ingatan warga yang menjadi korban.
Beberapa diantara mereka yang menjadi korban dalam kejadian itu bahkan trauma dan tak pernah kembali ke kampung setelah tanah garapan mereka diambil alih PT Lonsum.
“Semua tanaman itu dibabat habis. Baru orang-orang (kampung) itu diusir, dan ada yang belum kembali sampai sekarang,” kata Kamaruddin.
Sementara, mereka yang masih bertahan di kampung itu juga ada menutup diri karena trauma dan merasa terus diawasi.
Tia misalnya, salah satu korban dari PT Lonsum yang kami temui di Bulukumba sangat khawatir identitasnya diketahui banyak orang.
Untuk menemui Tia, kami naik sepeda motor dari kota Bulukumba, membelah hamparan perkebunan karet di Ujung Loe, lalu sampai di Kajang. Kecamatan di sebelah timur daerah berjuluk Butta Panrita Lopi itu.
Di sana, kami menyaksikan betapa peristiwa masa lampau masih menjadi trauma kolektif warga.
Kami mencari Tia. Berbekal secuil informasi bahwa dia seorang perempuan. Serta rumahnya yang konon berada di dekat pasar di sebuah dusun bernama Kajuara, Desa Bonto Biraeng.
Sesampai di pasar dimaksud, kami menghampiri orang yang ada di sekitar situ. Memperkenalkan diri, lalu bertanya dengan pertanyaan sama.
”Di mana rumahnya Ibu Tia?”
Pertanyaan sama, kepada sejumlah orang berbeda. Tapi jawabannya senada.
Muka kebingungan, dan sepotong kalimat “Tidak tahu.”
Kami nyaris menyerah. Sampai bertemu dengan dua orang perempuan dewasa dan satu pria yang sedang kongko di depan warung kecil.
”Di mana rumahnya Ibu Tia?”
Tidak ada yang menjawab. Mereka terlebih dulu saling lempar pandang. Sampai seorang yang lebih muda diantara mereka balik bertanya.
“Apa urusan ta cari Ibu Tia?”
Kami menjelaskan.
Lalu diminta duduk di sebuah balai-balai kayu.
Belakangan, setelah kami mengobrol panjang. Tia mengaku memang tak mudah mencari rumahnya. Sejak dia aktif memperjuangkan tanahnya, dia sudah berkali-kali dicari polisi.
Warga sekitar yang paham keamanan Tia, jadinya tak sembarang memberi tahu alamat rumahnya.
“Trauma orang di sini toh. Tidak ada mau anu (sebut) namaku. Takut-takut mi orang, takut mi kasih tau dimana rumahku,” kata Tia.
Trauma itu membuat gerakan warga terpecah. Ada warga yang tak ingin lagi menggunakan cara demonstrasi untuk memperjuangkan hak. Bahkan muncul dikotomi antara perjuangan masyarakat adat yang mempertahankan tanah ulayatnya, dengan warga di luar kawasan adat yang juga berkonflik dengan PT Lonsum.
Selama puluhan tahun berkonflik dengan PT Lonsum, mereka telah melakukan berbagai cara merebut kembali tanahnya. Menggugat ke pengadilan, reklaiming, demonstrasi, pendudukan, sampai audiensi yang tak terhitung lagi jumlahnya.
“Banyak cara ditempuh, tapi selalu kekerasan yang didapat,” kata Tia.
Selain kekerasan, sudah banyak upaya membenturkan warga, berbagai. Mereka dibenturkan dengan keluarga sendiri, sampai di masyarakat luas, bahkan muncul tendensi negatif.
Mereka yang berjuang dianggap selalu cari masalah dengan pihak Lonsum. Padahal perusahaan sudah membuka lapangan kerja di Bulukumba.
“Banyak orang yang mengatakan, kenapa kamu mengganggu Lonsum? Saya jawab, bukan saya yang mengganggu Lonsum, Lonsum yang ganggu saya,” kata Baba santai.
***
HGU Berakhir
Perjuangan itu kini mendapat secercah harapan. HGU PT Lonsum telah berakhir sejak 2023. Sekarang, perusahaan perkebunan raksasa itu tengah mengajukan pembaruan.
Menurut UU Pokok Agraria, maksimal pengajuan pembaruan dua tahun setelah HGU berakhir. Ada berbagai syarat untuk pembaruan. Di antaranya mengeluarkan sejumlah luas lahan untuk fasilitas umum.
Lonsum mengklaim sudah mengeluarkan 600 hektare konsesi HGU. Sehingga saat ini tersisa 5.100 hektare yang dikuasai.
“601 hektare untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. Termasuk lahan garapan warga selas 271 hektare. Lahan yang kami kelola telah sesuai peruntukan dan izin yang berlaku,” kata Humas PT Lonsum, Rusli Karim saat dikonfirmasi.
Di titik ini, pihak perusahaan dan masyarakat berselisih paham. Klaim itu dinilai masyarakat perlu diverifikasi.
Bagi masyarakat yang berjuang, apapun klaim Lonsum, sekarang pihak perusahaan tidak punya lagi hak atas tanah sejak HGU habis per 2023. Tersisa hak atas tanaman dan bangunan.
Jika HGU tak berhasil diperbarui di 2026, maka Lonsum tidak punya hak apapun lagi. Perusahaan yang dikuasai pemilik merek Indomie itu harus hengkang dari Bulukumba.
“3 bulan ke depan (2026) Stop! Pulang!” tegas Amiruddin.

Tapi mereka paham, dengan kekuasaan yang dimiliki Lonsum, HGU sangat mungkin diperbarui. Kalau itu terjadi, masyarakat meminta lahannya yang sudah dicaplok dengan tidak adil selama puluhan tahun dikembalikan.
Pada dasarnya, mereka mengaku tak pernah menolak kehadiran Lonsum. Masyarakat hanya memperjuangkan hak mereka.
Mereka merasa lahan HGU itu adalah haknya. Sementara perusahaan hanya pendatang. Kalau HGU berlanjut dan hak tak diberikan, maka selama itu, dia bilang konflik akan terus berlanjut.
“Konflik ini artinya mempertahankan lahan, mempertahankan tanah, mempertahankan hidup,” kata Amiruddin. Baginya, memperjuangkan tanah adalah soal hidup dan mati. “Itulah prinsip.”
Mereka tak bisa menggaransikan tidak ada konflik yang meletus ketika hak masyarakat terus diabaikan.
Sekuat apapun lawannya, yang penting bagi mereka adalah berjuang. Tak peduli bagaimana akhirnya.
“Namanya berjuang hanya ada dua kan. Kalah atau menang.”
Kami menemui pemimpin spiritual masyarakat adat Kajang, Ammatoa di rumahnya. Sebuah rumah panggung sederhana yang berada di tengah hutan Rambang Seppang lias kawasan adat inti.
Untuk sampai di sana, kami masuk melalui gapura antara batas Rambang Seppang dan Rambang Luara di Desa Tanah Toa. Lalu berjalan kaki menyusuri hutan dengan jalan berbatu sejauh kurang lebih satu kilometer.

Aturannya, Ammatoa tidak boleh meninggalkan Rambang Seppang agar tidak terpengaruh dengan modernitas. Walau tak pernah meninggalkan wilayah adat inti kecuali untuk persoalan mendesak seperti upacara adat, dia merestui upaya perlawanan melawan PT Lonsum.
“Kita dukung masyarakat adat,” katanya menggunakan bahasa Konjo. Kami mencatat perkataannya di buku. Di kawasan ini merekam audio atau visual dilarang.
Bagi dia, lahan yang dicaplok Lonsum, baik yang masuk dalam tanah ulayat atau milik masyarakat yang punya SHM, adalah ruang untuk hidup.
Kehidupan manusia, kata dia berasal dari tanah dan laut. Jika itu dirampas, maka artinya merampas kehidupan masyarakat. Di dalam konteks Lonsum, dia ingat betul, konsesi yang perusahaan kuasai melalui secarik kertas bernama HGU adalah lahan yang dirampas, diambil paksa.
“Harusnya itu tanah dikembalikan,” ujarnya.
Sementara itu, Lonsum menegaskan HGU yang mereka kuasai tidak ada yang tumpang tindih dengan tanah ulayat masyarakat adat Kajang. Sebagaimana Perda Nomor 9 Tahun 2015.
”Itu sudah disosialisasikan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, serta memberikan penjelasan tertulis bahwa tidak ada tanah masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang di area HGU Lonsum,” ujar Rusli.
Di sisi lain, Ammatoa mengaku sudah dijanji tanah ulayat masyarakat adat yang dikuasai Lonsum akan dikembalikan. Janji itu berkali-kali. Walau hingga kini hanya sekadar janji.
“Banyak salah paham. Dia kira untuk saya itu tanah, ini untuk kehidupan kita semua.”
“Sekarang sudah 2025 belum ada,” sambungnya.
Semenjak Lonsum menginjakkan kakinya di Bulukumba, dia menganggap masyarakat adat tak pernah diberi manfaat. Pemerintah menurutnya kenyang dari pajak, sementara masyarakat adat tidak kebagian.
Dia menegaskan Kajang bagian dari Indonesia. Masyarakat adat pun warga negara.
“Kalau dibagikan ke masyarakat manfaatnya, sebenarnya tidak ada masalah,” ucapnya.
Ammatoa menggambarkan kondisi masyarakat adat Kajang hari ini dengan satu kata.
“Anremo.”
Jika dialih bahasakan dari bahasa Konjo, artinya sudah tidak ada lagi kehidupan. Itulah kenapa, kata dia, sudah sedikit lagi masyarakat adat yang bermukim di Kajang. Terkhusus di Rambang Seppang.
Karenanya dia paham dan mendukung perjuangan masyarakat. Meski selalu merestui perlawanan merebut kembali tanah dari Lonsum, dia selalu mewanti-wanti agar masyarakat adat yang berjuang mengontrol diri.
“Kalau saya yang demo, masyarakat adat yang demo, kacau Bulukumba.” Dia mengulang-ulang kalimat itu. Lalu berpesan, “Saling bantu ki. Saling tolong ki.”
Editor: Sahrul Ramadan