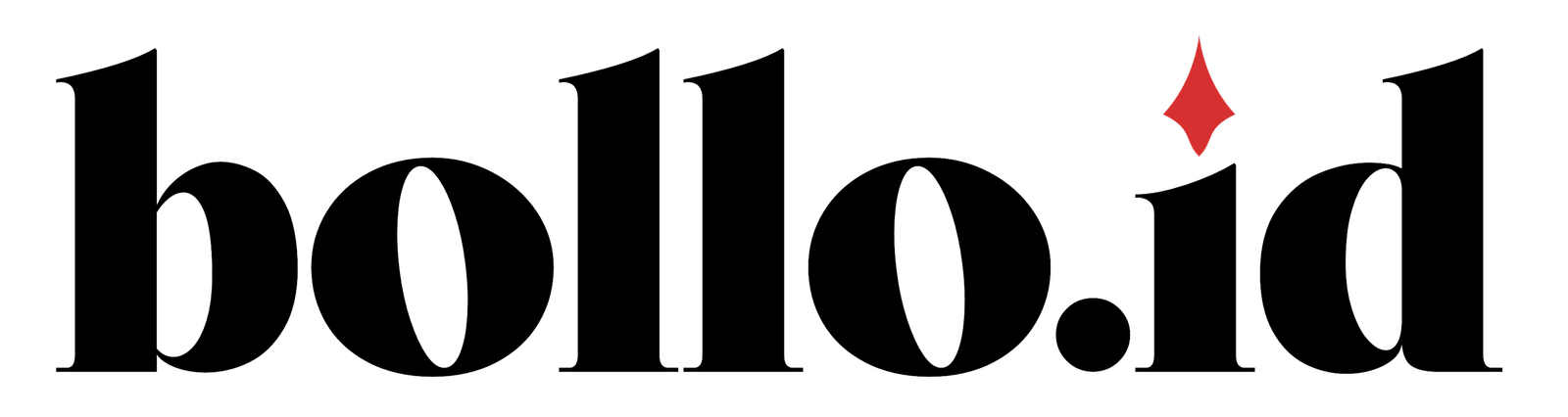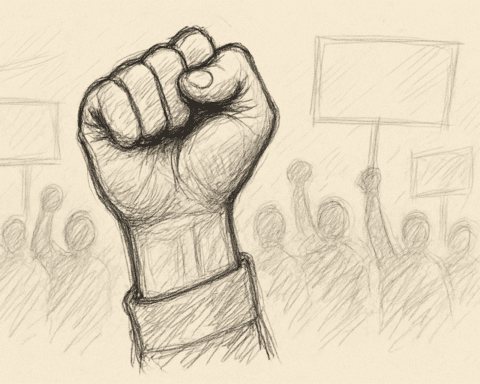Missusilawati bersama suaminya sedang di halaman parkir Klinik TB MDR, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Jakarta Timur. Missusilawati baru saja naik di motor, duduk di balik suaminya.
“Kamu nyusahin orang aja!” sang suami membentak Missusilawati. “Dasar penyakitan!”
Dada Missusilawati mendidih. Dia langsung melompat dari motor.
Umpatan sang suami terlontar saat perempuan asal Dumai itu, baru saja usai menjalani rangkaian panjang terapi antibiotik rutin, pada 2018 lalu. Sang suami merasa pengobatan sang istri menguras banyak waktunya. Dan di hari itu juga, kulit Missusilawati gatal dan kemerahan, efek samping yang timbul dari obat penyakitnya: tuberkulosis.
Durasi antrean pemeriksaan yang lama dan efek samping obat itulah yang menyulut kekesalan sang suami.
Setelah Missusilawati lompat, sang suami bergegas memarkir motor dan mengejar Missusilawati. Menarik tangannya. Tetapi, Missusilawati menepis cengkraman itu.
Dan bahwa setelah peristiwa itu juga, suami Missusilawati tidak lagi pulang ke kontrakan sederhana mereka di bilangan Cakung. Hubungan mereka pun merenggang.
Missusilawati adalah pasien dengan vonis tuberkulosis yang kebal terhadap antibiotik atau MDR (multidrug-resistant), sejak Agustus 2018.
TB–Tuberkulosis–adalah penyakit klasik yang diperkirakan oleh para ahli sudah ada sejak 17.000 tahun silam. Sekalipun sudah terdapat pengobatannya, TB masih mengancam negara-negara berkembang.
Laporan global TB WHO 2018 menunjukkan, bahwa Indonesia duduk pada peringkat ketiga dalam jumlah estimasi TB, sebanyak 842 ribu kasus. Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dalam penyampaiannya di Makassar, 2 Maret 2019 silam, mengatakan bahwa TB berada di peringkat keempat penyebab kematian di Indonesia.
Catatan tersebut menjadikan TB masuk dalam tiga beban penyakit (triple burden diseases) di Indonesia. Salah satunya lewat TB jenis MDR, seperti yang mendera Missusilawati.
Tuberkulosis MDR adalah kelanjutan dari penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Terapi antibiotik, adalah solusi akan penyakit tuberkulosis, tetapi ketika terapi terputus, penyakit itu dapat berkembang hingga kebal terhadap antibiotik.
Menjalani terapi tuberkulosis memang butuh ketabahan. Ketika kian mengganas sebagaimana Missusilawati, durasi perawatannya akan jauh lebih lama. Umumnya pengobatan antibiotik dari tuberkulosis ini berlangsung rutin selama rentang 18-24 bulan.
Karenanya, pasien TB butuh pendampingan, utamanya dukungan dari keluarga atau orang-orang terdekat. Namun, apa daya bagi Missi–sapaan Missusilawati–nasibnya tidak demikian.
Semenjak dia divonis TB MDR, sikap suaminya berubah dingin. Missi yang gemar mengobrol, acap kali dicuekin dengan suaminya yang telah memberinya seorang anak.
“Dia lebih senang main media sosial,” peluh Missi. “Terus kalau ditanya ada apa, dia cuma bilang, ‘Apa yang harus diomongin?’”
Lambat laun, sang suami yang semula mendukung pengobatan istri, berubah menjadi keluhan dan makian. “Kamu itu penyakitan. Penyakit kamu itu menular,” Missi menuturkan ulang makian suaminya.
“Tiap kali dia sebut itu, sakit rasanya.”
Perempuan itu bukannya tak berusaha meneguhkan hati sang suami. Berulang kali, Missi meyakinkan bahwa selama dia mengenakan masker dan menjalani pengobatan rutin, penyakitnya tidak akan menulari siapa pun dan dia akan sembuh. Namun apa daya, lain kehendak, lain kenyataan pula yang terjadi.
Kejadian 28 Februari itu, adalah puncak kemarahannya kepada sang suami. Dia kecewa. Hatinya remuk.
Seminggu setelah pertengkaran itu, Missusilawati bersama ibu dan kakaknya, menggelar mediasi bersama sang suami yang berprofesi sebagai driver ojek online. Dia ingin hubungan mereka kembali baik. Tapi usaha itu pun berakhir sia-sia.
“Saya sampai sujud minta maaf,” kenang Missi. “Tapi suami minta cerai.”
Cerita ini meluncur dari mulut Missusilawati, saat kami bertemu di RSUP Persahabatan, 2018 silam. Kini, dia hidup bersama kakaknya. Turut pula dia membawa anak semata wayangnya. Missi akan menangis, setiap kali mengenang perilaku suaminya itu.
Sikap yang diterima Missi termasuk dalam perilaku stigma dan diskriminasi. Kenyataanya, perilaku ini masih sering menyasar para penderita TB.
KNCV Tuberculosis Foundation, lembaga internasional yang fokus isu TB, menekankan bagaimana bahaya stigma dan diskriminasi ini membelenggu pasien TB. Ia dapat menghambat perawatan pasien, dan pada kasus yang fatal, dapat mendorong keinginan pasien untuk ‘putus obat’.
Seperti Elfrida Lubis, seorang pasien berusia 20-an yang turut menjadi penghuni shelter KNVC. Perempuan asal Medan ini merantau ke Jakarta pada Oktober 2018 dan bekerja sebagai staf penjualan di salah satu perusahaan swasta, di bilangan Pasar Minggu.
Sekitar Januari 2019, Elfrida mengalami batuk, demam, keringat di malam hari lebih dua minggu. Berat badannya menurun sekitar 6 Kg. Gejala tersebut mengarahkannya pada pemeriksaan dahak.
Walhasil, dia yang sebelumnya pernah terjangkit TB pada 2016 itu, kembali terkena tuberkulosis. Kali ini, dengan status MDR. Dalam perjalanannya, Elfrida sempat memutuskan untuk berhenti berobat. Salah satu alasannya karena tanggungan pekerjaan.
Perusahaan tempat Elfrida bekerja, menyuruh untuk berobat hingga sembuh. Namun, pengobatannya tidak ditanggung oleh perusahaan, dan gajinya pun tidak berlanjut. Padahal pemerintah pernah mengimbau agar karyawan yang menjalani terapi TB dapat tetap mendapatkan cuti dan gaji penuh.
Selain putus kerja, Elfrida juga diusir dari kos-kosannya, di Jatipadang, Jakarta Selatan karena penyakitnya. “Ibu kos bilang, ‘Bisa kamu cari kos yang lain saja?’, apalagi saya dituduh dapat menularkan TB ke anak-anaknya dan anak-anak kos.”
Suatu waktu, sempat terbersit dipikirannya untuk pulang kampung, tetapi rasa malu yang jauh lebih besar mencegah niatannya.
Terusir dan putus kerja membuat Elfrida harus berlabuh di shelter. Rumah singgah tersebut berada di tepat belakang RSUP Persahabatan, rumah sakit khusus untuk pelayanan pasien TB.
Organisasi ini adalah lembaga pendanaan internasional yang berfokus pada pengurangan HIV, Malaria, dan Tuberkulosis. Untuk pengelolaannya, rumah singgah ini dikelola oleh lembaga pendamping untuk pasien TB Pejuang Tangguh (PETA). Sepanjang 2018-2020 organisasi ini telah merawat 6900 pasien, termasuk Elfrida.
Setiap bulannya para pasien, mendapat bantuan sebesar Rp750 ribu. “Bantuan ini penting, utamanya untuk pasien yang keluarganya tidak mampu. Hampir semua pasien TB tidak bisa bekerja selama pengobatan,” tutur Darmansyah, pengelola shelter RSUP Persahabatan.
Terlepas dari setitik harapan itu, rasa sakit yang lain menghantui Elfrida: kesepian. Dia merasa diajuhi oleh kawan-kawannya begitu mengetahui ada TB yang ‘bersarang’ di dadanya.
“Dulunya biasa masak bareng, waktu tahu, pada nggak mau masak bareng. Kalau bicara sama saya juga takut dekat-dekat,” lanjutnya.
Meski teman-teman Elfrida kerap mengirim dukungan lewat pesan singkat di WhatsApp, dia tetap merasa dijauhi. Selama mereka tahu, tidak seorangpun yang datang mengunjunginya. “Saya sampai bilang di grup (WhatsApp), datanglah tengok aku, jangan sampai meninggal baru datang.”
Siksaan stigma dan diskriminasi itu, juga hampir membuat seorang Bambang Ismaya, bunuh diri.
Bambang divonis TB MDR pada tahun 2014. Pada tahun 2016, jelang kesembuhannya, keluarganya terus bertanya; mengapa dia tidak bekerja. Lelaki yang sebelum sakit berjualan makanan ini, memang selama menderita TB MDR, tidak dapat bekerja sepenuhnya. Tuduhan malas pun disematkan oleh keluarganya.
“Gimana mau kerja kalau habis minum obat, kuping berdengung, panas, dan lemas. Capek minum obat, Mas,” kata Bambang.
“Karena minder ditanyain terus tentang kerja, beberapa kali saya kayak mau bunuh diri.”
Efek yang dirasakan lelaki asal Bogor itu, adalah efek samping dari pengobatan TB. Antibiotik suntik seperti Streptomisin, dapat menggangu pendengaran pasien. Obat lainnya, Sikloserin, juga punya efek samping. Dua jam sehabis meminum Siskloserin, Bambang merasakan ada suatu panggilan yang datang dari arah tiang rumahnya.
Stigma dan diskriminasi yang dialami oleh Bambang dan Elfrida, acap kali jadi belenggu bagi pasien-pasien dengan kasus TB, di tengah usaha pemerintah untuk mengeliminasi penyakit ini di Indonesia pada tahun 2030 kelak–sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs).
“Bagaimana mau eliminasi?” kata Darmansyah. “Yang sakit aja belum ada bisa dijamin pekerjaannya.”
Selama masih ada teman-teman di sini, saya bisa semangat...
Suatu siang, pada 2018, di kursi tunggu Klinik TB MDR RSUP Persahabatan, Elfrida menurunkan maskernya. Di tangannya ada sejumlah pil berwarna putih dan kuning.
Pil putih itu adalah Pyrazinamid dan yang kuning Sikloserin. Dua jenis pil itu adalah antibiotik untuk pasien TB MDR. Di samping kursi Elfrida, ada beragam jenis buah-buahan lengkap bersama bumbu rujak dan air botol.
Hari itu seperti hari biasanya, dia bersama kawannya mengantre jatah obat terapi antibiotik. Dari sisi berlawanan, Darmansyah mengawasi dan sesekali mengingatkan para pasien untuk datang kembali dan meminum obat sebelum pulang.
Tetapi meminum obat tidak semudah itu. Setidaknya bagi Elfrida.
Elfrida terlihat ragu ketika hendak memasukkan pil-pil itu ke dalam mulutnya. Akhirnya, dia malah mengambil sebuah jambu dan mencocol ke bumbu rujak lalu memakannya. Sehabis itulah, Elfrida baru menenggak pil-pil di tangannya. Wajahnya pun berubah masam.
“Kalau pertama-tama mungkin tidak ada masalah, tapi kalau sudah sering akan mual dan muntah. Dengar nama obatnya saja. Apalagi kalau diminum. Tiap hari lagi,” seloroh Elfrida.
Pernyataan Elfrida tidak mengada-ada. Salah seorang pasien yang tengah meramu kombinasi obat-obatan ini menyilakan saya untuk membaui obatnya. Saya tak bisa membayangkan bagaimana rasa obat ini ketika menyentuh lidah dan sampai pada pangkal lidah mereka–bagian di mana pengecapan rasa pahit berada.
“Makanya usahakan sehat mas ya,” pasien itu berkelakar kepada saya.
Sejam setelah menenggak obat, Elfrida terlihat kuyu. Dia menundukkan kepala dan buru-buru menarik selembar kantong plastik bening dari sampingnya. Dia muntah dan memenuhi kantong itu.
Memang, setiap kali Elfrida memimun obat dia bakal muntah. Pyrazinamid dan Sikloserin memang punya efek samping menyebalkan: mual dan muntah.
Missusilawati dan rekannya yang berada di sekitar kemudian meriung di hadapan Elfrida. Seorang memijit lehernya dari belakang, seseorang lagi mendekatkan minyak beraroma terapi ke hidung Elfrida.
Menyaksikan pemandangan ini menyadarkan saya, bahwa saling mendukung dan menyemangati inilah yang membuat para pasien terus berobat. “Kalau bukan sesama penderita TB dan keluarga, siapa lagi yang akan menyemangati pasien lain?” tutur Darmansyah yang juga mantan pasien TB MDR. Dia tahu betul rasanya.
Dan bagaimana dengan Missusilawati?
“Saya sudah ini…. sudah masuk masa iddah (masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya), sama aja sudah diceraikan. Selama masih ada teman-teman di sini (sesama penderita TB), saya bisa semangat.”
Dhihram Tenrisau menulis tulisan ini pada 2018 dan tayang di Beritagar.id. Bollo.id kembali memuatnya dengan beberapa penyesuaian atas izin penulis.
Baca ceritaan lainnya: Masyarakat Takalar Tuntut Lahannya Dikembalikan PTPN XIV
Keterangan foto sampul: Ilustrasi oleh storyset/Freepik