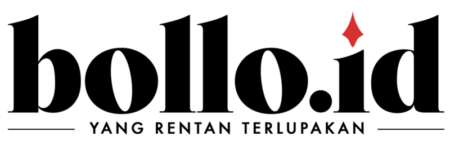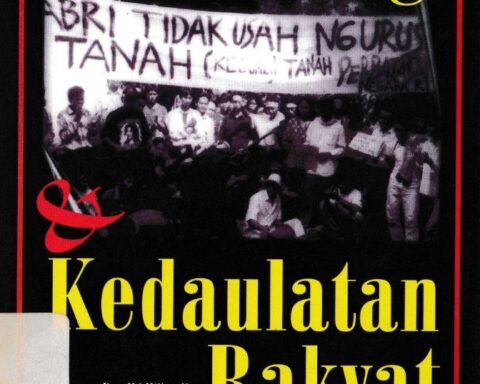Bollo.id — Sebulan lalu, suatu penugasan membawa saya ke Kolombo, Sri Lanka—negara pulau di Asia Selatan yang dikelilingi Samudra Hindia. Tempat yang mungkin kalah tenar dari Bali atau Lombok di telinga para pelancong.
Beberapa kawan sempat bertanya-tanya, untuk apa saya pergi ke sana? Pertanyaan yang belum bisa sepenuhnya saya jawab. Satu hal yang pasti, tulisan ini bukan tentang berita besar atau panduan wisata.
Ini tentang percakapan dengan orang-orang asing yang terasa akrab; tentang hidup. Bukankah setiap perjalanan selalu menyimpan satu hal yang sama: cerita?
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Saya meninggalkan rumah di Maros pukul empat pagi. Setelah menyantap sepiring nasi dan telur dadar buatan istri, serta mengecup kening kedua anak saya yang masih terlelap, saya berangkat menuju Bandara Sultan Hasanuddin.
Penerbangan saya ke Jakarta dijadwalkan pukul 05.55 WITA, lalu akan lanjut terbang menuju Kolombo pada pukul 14.25 WIB. Ini adalah perjalanan panjang, bukan hanya soal ribuan kilometer yang membentang, tapi juga karena satu hal yang belum pernah benar-benar berdamai dalam diri saya: ketakutan terbang.
Kecemasan ini selalu hadir setiap kali pesawat akan mengudara. Ia menjelma menjadi dialog panjang dengan Tuhan, lalu berganti menjadi percakapan dengan isi kepala sendiri—hanya untuk memastikan bahwa segalanya akan baik-baik saja.
Rupanya saya tidak sendirian. Di kursi sebelah, seorang ibu paruh baya tampak sama cemasnya. Mulutnya bergerak pelan, melafalkan doa-doa yang nyaris tanpa suara, matanya terpejam rapat.
Dua orang asing yang duduk berdampingan, diam-diam bernegosiasi dengan Tuhan lewat kecemasan yang sama selama dua jam perjalanan di atas langit. Pikiran saya melayang pada kalimat yang pernah saya baca di halaman Dunia Sophie (Jostein Gaarder):
“Hidup itu sendiri adalah misteri yang besar. Kita lahir ke dunia ini. Tumbuh. Dan akhirnya mati. Tapi dari mana kita datang? Dan ke mana kita pergi?”
Pukul 09.00 WIB, pilot mengabarkan jarak pandang di Bandara Soekarno-Hatta tidak lebih dari tiga kilometer. Dari balik jendela pesawat, Jakarta tampak terselubung kabut asap. Lima belas menit kemudian, di tengah gerimis yang mulai turun, roda pesawat akhirnya menapak di landasan.
*
Pernah menonton The Terminal (2004)? Film yang dibintangi Tom Hanks itu bercerita tentang Viktor Navorski yang terjebak di bandara karena negaranya dilanda krisis.
Ia tak bisa pulang, tak bisa pula melanjutkan perjalanan, dan akhirnya menjadikan bandara sebagai rumah. Bagi saya, bandara adalah ruang tunggu raksasa, tempat para pelancong singgah untuk satu hal: menunggu.
“Saya menunggu…,” kata Viktor dalam film itu.
Kalimat itu memutar sebuah lagu lawas di kepala saya, “Menunggu… ternyata… meletihkan…,” yang dinyanyikan Ribas, penyanyi asal Makassar yang lagunya kerap diputar radio di awal tahun 2000-an.
Sembari menunggu, saya mencari tahu hubungan antara Indonesia dan Sri Lanka. Ternyata, ikatan keduanya sudah terjalin jauh sebelum kedua negara ini merdeka.
Para biksu dari Sri Lanka pernah mengarungi Samudra Hindia menuju Nusantara untuk memutari stupa-stupa Borobudur. Sebaliknya, para biksu dari Nusantara berlayar ke Anuradhapura untuk menyentuh pohon Sri Maha Bodhi, saksi bisu saat Siddharta Gautama mencapai pencerahan.
Hubungan yang bermula dari perjalanan spiritual. Ikatan emosional itu semakin erat ketika Sir John Kotelawala dari Sri Lanka duduk sejajar dengan Soekarno, Nehru, Nasser, dan Zhou Enlai dalam Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.
Mereka berlima sepakat pada satu hal yang tak bisa ditawar: menolak penjajahan. Pantas saja, izin visa bagi warga Indonesia (dan sebaliknya) sangat mudah. Saya hanya butuh sepuluh menit untuk mendapat balasan visa disetujui setelah mendaftar secara daring.
Pukul 14.10 WIB, tiba waktunya melanjutkan perjalanan ke Kolombo. Ketakutan yang sama kembali datang. Saya duduk di kursi 11C, dekat lorong, untuk memudahkan pelarian kecil saya ke toilet saat rasa cemas memuncak di udara.
Di samping saya, sepasang suami-istri telah duduk. Pasangan ini berasal dari Solo. Saya mengetahuinya setelah kami mulai berbincang sekitar dua puluh menit setelah lepas landas. Keduanya saya perkirakan berusia di atas 50 tahun dan tampak begitu mesra. Sang istri bersandar manja di bahu suaminya, tangannya merangkul lengan kanan pria itu.
“Oh, Anda dari Maros?” kata si bapak saat saya menyebutkan asal saya. “Saya pernah ke Maros, tapi hanya numpang lewat. Waktu itu mau ke Tana Toraja naik sleeper bus. Busnya bagus-bagus. Saya bahkan ditungguin sama busnya karena telat 15 menit keluar dari bandara,” selorohnya.
Perbincangan kami mengalir hingga ke tema perjalanan. Si bapak bercerita bahwa setiap tahun, mereka berdua selalu menyisihkan waktu untuk ritual kecil: “me time” bersama. Tradisi sederhana namun penuh makna untuk lari sejenak dari rutinitas, hanya untuk menikmati kebersamaan.
“Kadang kami naik motor, kadang jalan kaki, kadang naik mobil, atau ya… seperti ini, naik pesawat ke tempat yang jauh,” katanya.
Ia lalu menatap saya dan menambahkan, “Mas, enjoy your time. Enjoy with what… and who… you love. You never know when you will be separated.”
Perjalanan dan percakapan ini terasa ganjil, tetapi sekaligus hangat. Kami tidak pernah saling memperkenalkan nama. Tidak ada basa-basi, tidak ada pertukaran nomor ponsel, apalagi janji untuk bertemu lagi.
Tanpa ucapan perpisahan formal, kami hanya berjabat tangan, lalu berpisah di Bandara Internasional Bandaranaike, Kolombo.

**
Sebelum tiba, saya sempat bertaruh dengan diri sendiri: hewan apa yang pertama kali akan saya lihat di Kolombo, kucing atau ayam? Ternyata saya salah. Burung gagaklah yang pertama kali saya temui.
Spesies Gagak Rumah (Corvus splendens) memang pemandangan umum di sini. Mereka telah menghuni kota ini selama berabad-abad, sejak Kolombo menjadi pusat pelabuhan utama yang dikuasai Portugis, Belanda, dan Inggris pada abad ke-16.
Aktivitas pelabuhan, pasar ikan, dan kawasan dagang yang menghasilkan banyak limbah organik menjadi magnet alami bagi koloni mereka. Saya tiba di hotel larut malam. Keesokan paginya, dari balik jendela kamar, terlihat hamparan tanah reklamasi yang menjulur ke laut.

Megaproyek dermaga sedang dibangun, bagian dari Belt and Road Initiative milik pemerintah Tiongkok yang kelak akan bernama Colombo Port City. Tak heran jika saya beberapa kali melihat rombongan orang Tiongkok berjalan-jalan di kota.
Kurang dari satu kilometer di sebelah kanan hotel, berdiri bangunan putih besar dan megah: Kedutaan Besar Amerika Serikat. Penjagaannya super ketat, lengkap dengan petugas yang menenteng senapan AK-47. Sebuah ironi yang menggelitik—Amerika dan Soviet dalam satu bingkai.
Tepat di depan hotel, terdapat stasiun kereta api bernama ‘Kollupitiya Rail Station’. Nama stasiun ditulis dalam tiga bahasa—Sinhala, Tamil, dan Inggris—di atas papan kayu bercat putih.
Dibangun di awal abad ke-20 saat Sri Lanka masih bernama Ceylon di bawah kolonialisme Inggris, rel ini adalah bagian dari jalur pantai yang menghubungkan pusat kota Kolombo dengan Galle dan Matara di pesisir selatan.
Di sudut jalan lain, satu bus tua terparkir. Warnanya biru pudar, catnya mulai retak, bentuknya kaku dan klasik. Bus Leyland buatan India, model yang sama sejak tahun 1968, yang telah mengangkut warga Kolombo dari dekade ke dekade.

Pemandangan ini sontak mengingatkan saya pada Metromini atau Kopaja di Jakarta. Keduanya sama-sama tua, sama-sama menjadi saksi zaman.
Saya mencoba merangkai semua pengalaman ini. Bus Leyland yang menua dan gagak-gagak yang berkerumun adalah jejak masa lalu yang menolak sirna. Proyek raksasa Colombo Port City adalah gambaran masa depan yang ambisius.
Sementara itu, senapan serbu AK-47 di depan kedutaan Amerika adalah simbol dua dunia yang bertolak belakang, namun nyatanya mampu hidup berdampingan di kota ini. Kolombo adalah perpaduan dari semua itu: masa lalu, masa depan, dan ketegangan yang hidup dalam harmoni.
Editor: Sahrul Ramadan