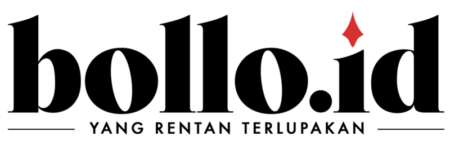Jadi itu tahun 2010. Saya bekerja sebagai wartawan muda di Harian Fajar Makassar. Beberapa bulan selanjutnya, ketika bulan peringatan Hari Pendidikan Nasional, Buyung Maksum yang jadi redaktur halaman Metro, menugaskan untuk membuat wawancara dengan Prof. Halide.
Suara Prof. Halide cukup penting karena sebagai ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan. Waktu itu, dia juga sedang menjabat Rektor Universitas Fajar.
Sebelum menemuinya, Buyung bilang, cari referensi dulu dan isi kepala agar bisa wawancara dengan baik. Maka berbekal pencarian di internet seadanya, saya siap melaksanakan penugasan.
Di lantai dua, gedung kampus, saya menjumpai Prof. Halide. Ruangannya besar, ada lemari dengan beberapa buku. Ini kali pertama saya bertatap muka dengannya. Basa basi perkenalkan diri. Tak disangka, pria tua beruban itu, tiba-tiba bilang: apa yang kau tahu tentang pendidikan di Sulsel?
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Saya terkejut. Tapi merasa percaya diri karena sudah membaca sedikit informasi. Dan menjawab penuh percaya diri. “Ehhh, kau pulang saja. Kau tidak tahu apa-apa soal Pendidikan. Soal sejarahnya. Soal apa saja,” katanya cetus.
Saya terguncang. Sebagai wartawan muda, saya pun tak mau kalah. Saya kembali mengatakan apa yang saya ketahui. “Sudah. Nanti saya telpon Alim, kenapa dia kirim wartawan bodoh kemari,” lanjutnya.
Alim adalah Nur Alim Djalil, wakil Pemimpin Redaksi masa itu.
Saya mulai jengah. Pria tua yang songong dan sombong menurutku. Tapi saya juga malu, jika kembali ke kantor Fajar, dan gagal wawancara. “Karena saya tidak tahu apa-apa Prof, jadi saya datang bertanya,” kata pasrah.
“Wartawan itu harus pintar. Mana bisa jadi wartawan kalau bodoh,” ucapnya.
“Tapi saya tidak mau pulang Prof,” kataku sedikit menentang.
“Ya sudah, saya banyak kerjaan. Kau disitu saja,” menyuruhku duduk.
Saya duduk di kursi sofa ruangannya. Dua orang mungkin staf kampus masuk. Mereka berbicara sekitar 15 menit, lalu keluar. Dan tiba-tiba pria tua, kembali memalingkan wajah pada saya. “Kau baca berapa buku satu bulan?,” katanya.
Karena ingin terlihat pintar juga, saya bilang; “Empat Prof.”
“Bodoh memang. Kau kemanakan waktumu yang lain. Bagaimana bisa kau pikir bisa jadi wartawan kalau tidak banyak membaca,” tegasnya lagi.
Saya melongo. Pria tua itu, kemudian bilang, usia muda, seharusnya digunakan untuk melahap semua pengetahuan. Pada usia, 30 hingga 60 tahun, katanya, dia membaca satu buku satu hari. Tentu itu tak terhitung koran dan majalah.
“Sekarang, saya sudah mau 80 tahun. Mata saya sudah mau kalah. Saya baca 100 lembar setiap hari,” lanjutnya.
Mendengar itu, akhirnya menciut. Saya sadar, sedang berhadapan dengan siapa. Seorang pria yang terhormat. Yang namanya juga ikut abadi di lembaga Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) – Korps Pecinta Alam (Korpala) Unhas, karena salah satu orang yang memberikan izin pendirian lembaga itu di tengah kecaman Orde Baru.
Pria tua itu kemudian berdiri, dan memegang tiga buah buku tebal. Sejarah Pendidikan Indonesia. Satu buku, setidaknya 400 halaman. “Ini kau baca dulu, terus besok kau datang lagi,” katanya.
“Besok Prof. Boleh empat hari?,” pintaku.
“Ini tinggal kau baca. Apa susahnya. Besok pagi kau datang,” katanya lagi.
“Tiga hari boleh prof?,” saya kembali menawar.
“Iya. Pulang mi.”
Saya keluar ruangan dengan lemas. Menuruni tangga dan menendang stater motor vespa saya. Di perjalanan menuju Graha Pena kantor Harian Fajar, hati saya remuk. Menemui Buyung dan menceritakan kisah ini. Celakanya, dia ikut tertawa. Dan saya meminta untuk tidak tugaskan banyak liputan selama tiga hari untuk menyelesaikan bacaan buku.
Di petak kosan di Manuruki saya mengurung diri. Tak keluar malam hanya membaca buku itu. Waktu perjanjian sudah tiba, saya menjumpai pria tua itu kembali. Dia kemudian mengajak saya berbicara, lalu berbicara banyak hal tentang Pendidikan di Sulawesi Selatan.
Tanya jawab kami berlangsung cair. Di akhir wawancara, dia bilang; “Nah kalau sudah ada pengetahuan sedikit, jadi enak bicara toh.”
****
Setelah perkenalan pertama itu, saya menjadi begitu dekat dengannya. Atau setidaknya, saya saja yang merasa. Saya menyimpan nomor hp-nya, dan dia juga menyimpan nomor saya di gawainya.
Prof Halide – kini saya menulis namanya tanpa tanda baca – adalah narasumber yang mumpuni untuk bidang yang ditekuninya. Sekali waktu, ketika menulis tentang perjalanan kopi di Sulawesi Selatan untuk Majalah Historia, pria tua itu sudah menjadi salah seorang komisaris di Bank Sulselbar. Tapi pada 1970-an, dia pernah menjadi kepala dagang di pelabuhan dan mengirimkan kopi untuk ekspor ke beberapa negara.
Saat menemuinya, usianya yang telah lebih 80 tahun, membuatnya melambat. Jika saya memotong jawaban dan memberikan pertanyaan berbeda, dia meminta untuk sabar mendengar. Tapi dia adalah pria tua yang menawan.
“Eko, kepala saya ini sudah kepala tua. Biar saya urut dulu, perjalananya. Supaya saya tidak lupa,” katanya.
Saya tersenyum. “Kau jangan senyum mengejek begitu e. Mata saya masih bisa membaca. Kalau tulisanmu salah, saya bisa telepon ko,” lanjutnya.
Wawancara mengenai kopi itu, terjadi saat bulan puasa. Dan celakanya, dia mencium aroma pakaianku yang berbau rokok dan tahu kalau saya tak puasa. Saat hendak pamit, dia keluarkan dompetnya dan memberikan uang satu lembar Rp100 ribu.
“Prof, ini apa. Tidak dong,” saya keluar ruangannya marah dan merasa kecewa.
Tapi, tak disangka, dia mengikuti hingga ke parkiran depan gedung. Lalu kembali memaksakan uang itu. “Kau ambil, kau pergi beli kopi atau makan di sebelah,” katanya, sambil menunjuk gerai KFC di samping kantornya.
Dengan nada marah seperti bapak, saya akhirnya menerima. Motor saya biarkan parkir di depan gedung bank itu, lalu berjalan. Ketika di depan gerai KFC, saya menoleh, dan dia berjalan memastikan keberadaanku.
Dia mengangkat tangannya dengan jempol. Saya juga melambai dengan jempol. Ah sial, kejadian itu serasa baru kemarin terjadi.
Setelah wawancara mengenai kopi itu selesai dan saya mulai menulis naskah. Beberapa penggalan harus dikonfirmasi ulang. Saya kemudian mengirimkannya pesan singkat melalui SMS untuk memastikan apakah bisa menelponnya.
Saat menunggu, dia menelpon. “Eko, kau sudah tidak punya uang kah? SMS ini, minta dibayarkan,” katanya.
Saya tertawa, karena lupa mengecek pulsa.
Bertahun kemudian, saya kembali menemuinya. Dia makin tua. Kelopak mata bagian bawahnya, kelihatan jatuh. “Prof, semakin tua. Bolehkah saya menulis biografi untuk prof,” kataku.
“Tidak. Ada beberapa orang yang sudah minta. Tapi saya menolak,” katanya menegaskan.
“Tapi diantara nama yang meminta itu Prof, saya yang terbaik. Percaya lah prof,” saya merayunya.
Dia menatap dengan diam. Lalu tertawa. “Kalau kau menulis buku saya, itu kau doakan saya cepat mati. Jadi nanti orang-orang akan cari buku itu, bukan cari saya.”
Giliran saya yang tertawa. Dia juga membuat Sekolah Dasar Anak Indonesia, menggunakan bekas kantor Rektor Unhas di sekitaran Masjid Al-Markaz. Dananya dari Badan Amil Zakat, dan pengajarnya adalah kawan-kawannya, atau muridnya yang sudah jadi dosen di berbagai perguruan tinggi di Makassar.
Dari gedung itu, saya merajuknya untuk buku biografi. Dia lalu berjalan dan bilang, mau ke kantor Dewan Provinsi karena diundang rapat. Ketika dia membuka pintu sedan Toyota-nya, saya pun masuk ke pintu sampingnya.
“Saya nda mau turun Prof, kalau tidak diizinkan menulis buku,” kataku.
“Kau ikut mi ke kantor DPRD,” ia mengajakku.
Di perjalan yang singkat sekitar 15 menit itu, saya menatapnya. Dan dia berbangga bilang, jika masih bisa menyetir dengan baik dengan usia tua. Memasuki halaman kantor Dewan Provinsi, dia memarkirkan kendaraan. “Jadi bagaimana Prof,” kataku.
“Saya sudah terlambat. Nanti kupikir. Ini kau ambil, naik pete-pete mi ke sana, ambil motormu,” menyodorkanku uang.
“Adaji uangku Prof,” saya menyanggah.
“Ambil mi. Kalau kau nda ambil, saya tidak akan pikir-pikir soal buku itu.”
Ketika uangnya saya ambil, dia tertawa. “Nda cukup naik taxi kesana ini Prof, ka Rp20 ribu,” ucapku.
“Kau tambahi uangmu mi,” ia menimpali.
Baca juga artikel lain orang-orang yang Layak Dikenang:
29 Maret 2025, dua hari sebelum lebaran Idulfitri, saya membaca kabar kematiannya. Sesak rasanya. Memejamkan mata sesaat dan menemui wajahmu, rambutmu yang memutih bersinar dalam gelap. Selamat jalan Prof Halide.
Berkali-kali saya bilang ke beberapa kawan, hanya kau lah yang memiliki gelar Prof dengan lekat dan menempel sudah serupa nama. Namamu yang hanya satu kata, sungguh membuat lidah kaku untuk berucap Pak Halide. Rasanya menjadi tak etis. Kau lah Prof Halide. Dan kau pun Profesor Halide yang menawan.