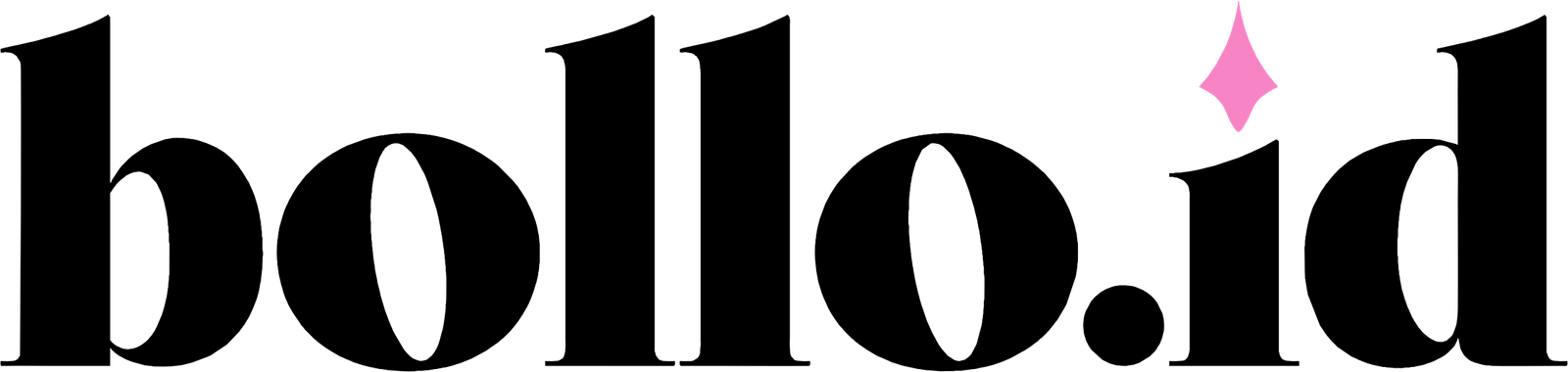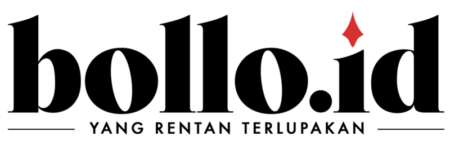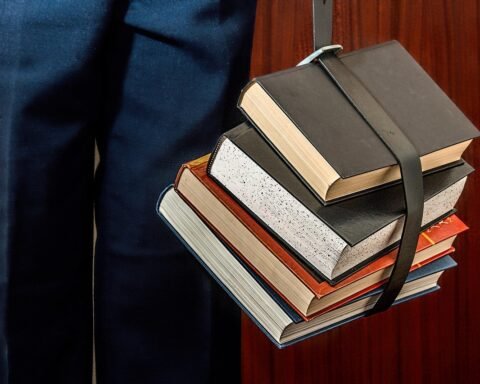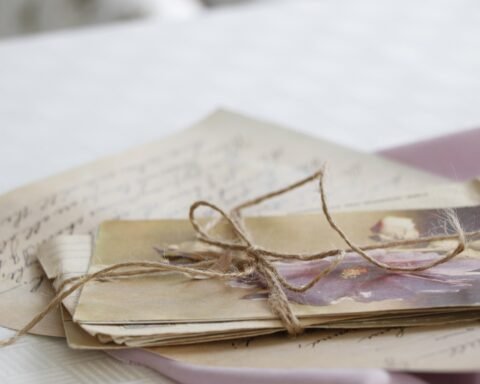Kota-kota besar di Indonesia kebingungan mengendalikan polusi udara yang ditimbulkan oleh lalu-lalang kendaraan. Selain itu, kemacetan lalu lintas pun hingga kini belum menemukan solusi efektif sebab volume kendaraan dengan beragam jenisnya terus bertambah. Pengendalian kepemilikan kendaraan telah diterapkan pemerintah dalam beberapa tahun melalui kebijakan Pajak Progresif—di mana pemilik kendaraan roda empat dengan jumlah di atas dua buah akan dikenakan tarif pajak khusus. Tetapi tampaknya, kebijakan ini tak jua mampu menekan jumlah kendaraan yang saban hari malang melintang di ruas-ruas jalan perkotaan, seperti Kota Makassar.
Perihal kendaraan bebas polusi udara alias ramah lingkungan, mengingatkan kita pada “Becak”. Moda transportasi roda tiga ini tergolong ramah lingkungan, sebab tak menggunakan bahan bakar minyak sebagaimana kendaraan modern lainnya. Mesin pembakarnya adalah sang pengayuh sendiri. Lebarnya, tak cukup semeter. Panjangnya, lebih semeter dengan tenda segi empat yang juga tak cukup semeter persegi.
Selain ramah lingkungan, becak juga tergolong moda transportasi “ramah Polantas”. Becak tak wajib memiliki surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB. Pengendaranya pun tak harus mengantongi Surat Izin Mengemudi (SIM). Dan ketika melanggar rambu-rambu lalu lintas, pengendaranya bebas tilang. Oleh karena itu, becak ramah Polantas. Tak pernah berurusan dengan Polantas.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Menumpangi becak, keselamatan pun relatif terjamin. Jarang ditemukan terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti tabrakan antar sesama becak. Dan juga efektif, sebab becak mampu menyusuri jalanan sekelas lorong (gang) di kota. Penumpang becak dapat diantar hingga depan rumahnya, kendatipun jalanannya harus menyusuri lorong-lorong sempit. Efektif pula, lantaran tarifnya tak semahal moda transportasi modern lainnya, seperti taksi.
Pengayuh becak umumnya berasal dari kelas masyarakat bawah dengan tingkat pendidikan yang terbatas. Lebih jauh, Erwiza Erman dalam buku Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa (Buku Obor–KITLV Jakarta, 2013) menulis artikel berjudul “Kehidupan dan Politik Penarik Becak di Jakarta (1930–1960).” Ia menyebut penarik becak adalah sebuah kategori sosial yang digolongkan sebagai masyarakat kelas bawah dengan berbagai stempel yang dikenakan pada mereka, yakni kemiskinan, ketidakteraturan, dan kotor serta pengganggu keindahan dan ketertiban kota. Berbagai stempel ini, menurut Erwiza, dikonstruksi umumnya oleh para agen pembangunan kota.
Sementara itu, Sartono Kartodirdjo lewat studinya tentang latar belakang sosial-ekonomi tukang becak tahun 1970-an di sekitar Yogyakarta menyebut, bahwa para penarik becak umumnya berasal dari kelas bawah seperti petani penggarap, dan berpendidikan rendah (Sartono Kartodirdjo, 1981). Sebab memang dalam faktanya, untuk menjadi penarik/pengemudi becak tak memerlukan keahlian tertentu.
Di Kota Makassar, kita jumpai pengayuh atau penarik atau tukang becak sering menanti penumpang di pinggir jalan utama. Adapun pemilik becak, biasanya dimiliki oleh kelas masyarakat mampu dengan sistem sewa harian oleh para pengayuh/penarik becak. Relasi patron-klien kental di sini.
Tetapi sejak tahun 2004 becak di Kota Makassar mulai tersingkir. Moda transportasi roda tiga ini tersingkir oleh kelahiran “adik tirinya” sendiri yang dikenal dengan nama “Bentor” (becak motor), sebuah kendaraan beroda tiga menyerupai becak, hasil modifikasi motor bekas dengan becak. Ada yang bilang, evolusi becak ke bentor ide awalnya berasal dari Kota Gorontalo. Namun menumpangi bentor tentu saja tarifnya tak semurah becak, sebab Bentor menggunakan bahan bakar minyak. Dan, tentu pula Bentor tak ramah lingkungan dan tak ramah Polantas.
Tetapi Bentor terlanjur tumbuh walau dengan menggunakan motor bekas. Kemudian sekitar tahun 2004 Bentor dengan motor baru mulai bertumbuh. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh semakin bertumbuhnya perusahaan pembiayaan kepemilikan kendaraan motor dengan diskon dan layanan kemudahan lainnya.
Sejumlah perusahaan pembiayaan berlomba memberi kemudahan pada publik untuk transaksi kredit motor. Di era inilah, pembiayaan kredit kendaraan tumbuh bak cendawan di musim hujan. Motor misalnya, dapat dimiliki hanya dengan menyetor Rp500 ribu uang panjar dengan syarat administrasi yang mudah pula. Cukup dengan fotokopi KTP, kartu keluarga, dan rekening pembayaran listrik. Maka semakin masiflah pertumbuhan bentor, dan kian hari becak semakin langka.
Walau begitu, becak tak mesti “dibuang” begitu saja. Becak tak harus dilupakan begitu saja, sebab ia adalah bagian dari masa lalu Kota Makassar. Dengan kata lain, becak merupakan salah satu bagian dari sejarah Kota Makassar yang megah ini. Lantas, bagaimana riwayat roda tiga ini?
Asal Muasal
Becak punya cerita, becak punya kisah sejarah yang panjang. Mulai sejarah ekonomi, sosial, politik, urbanisasi, hingga sejarah tentang kemiskinan di kota ini.
Barangkali karena terabaikannya komunitas becak dalam historiografi di Indonesia membuat naskah tentang asal muasal becak secara umum sangat terbatas. Erwiza Erman dalam artikelnya “Kehidupan dan Politik Penarik Becak di Jakarta (1930–1960)” (Buku Obor–KITLV Jakarta, 2013) menyebut sejumlah sumber sejarah yang terbatas itu bertema becak, di antaranya: Sartono Kartodirdjo memulai studi latar belakang sosial-ekonomi tukang becak pada tahun 1970-an (1981). Ada pula Prof. Dr. Sry Edi Ahimsa yang menganalisis etnografi tiga keluarga tukang becak di Yogyakarta (1977a, 1977b, dan 1978). Studi kontemporer tentang penarik/tukang becak lahir dari karya Heru Winarno (1997), Verdi Yusuf (1992), Kamala (1994), Azuma (2001), dan Paul Koetsier (1989).
Erwiza Erman, merujuk pada Warren (1986), menyebut becak pertama kali ditemukan di Jepang pada tahun 1869 dan kemudian menjadi transportasi modern di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Bentuk awalnya sangat sederhana, ditarik oleh orang di depan. Pelan-pelan, becak mengalami kemajuan teknologi, tak lagi ditarik oleh tenaga manusia, tetapi dijalankan dengan roda tiga oleh penariknya di bagian belakang. Pada abad ke-19 dan abad ke-20, kendaraan ini dijumpai di kota-kota besar seperti Yokohama, Peking, Shanghai, Rangoon, Hong Kong, Calcutta, Singapura, dan Jakarta. Ada pula yang menyebut, becak mulai populer di Asia Tenggara pada tahun 1940-an. Lea Jellinek dalam Seperti Roda Berputar menulis, becak didatangkan ke Batavia dari Singapura dan Hong Kong pada 1930-an.
Tak diketahui persis kapan becak mulai hadir di Indonesia dan dari mana ia didatangkan. Tetapi di Surabaya—menurut Erwiza Erman—becak telah hadir di sana yang dikenal dengan angkong sebelum tahun 1900, pemilik dan penariknya umumnya berasal dari suku Hokchia.
Ada pula yang menyebut, becak diperkenalkan dari Hong Kong atau Tiongkok pada tahun 1941 hingga meluas ke Pulau Jawa. Dan dari Surabaya lalu dibawa ke Makassar. Namun, pemberitaan Jawa Shinbun edisi 20 Januari 1943 menyebut, becak diperkenalkan dari Makassar ke Batavia (Jakarta) pada akhir tahun 1930-an.
Ini diperkuat dengan catatan perjalanan seorang wartawan Jepang ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Makassar. Dalam catatan berjudul Pen to Kamera terbitan 1937 itu disebutkan, becak ditemukan oleh orang Jepang yang bermukim di Makassar bernama Seiko-san. Ia memiliki toko sepeda. Karena penjualan seret, ia memutar otak agar tumpukan sepeda yang tak terjual bisa dikurangi. Dia membuat kendaraan roda tiga, dan terciptalah becak (daengbecakmks.blogspot.co.id).
Tukang Becak, Siapa Gerangan?
“Ah, kawan, biarlah aku ceritakan kau tentang Jakarta kita. Tahun 1942, waktu aku untuk pertama kalinya aku injak tanah ibu kota ini, Stasiun Gambir dikepung oleh delman. Kini delman ini telah hilang dari pemandangan kota—hanya tujuh belas tahun kemudian. Becak yang menggantikannya. Kuda-kuda diungsikan ke pinggiran kota. Dan kemudian, manusia-manusia menjadi kuda dan sopirnya sekali: begini tak ada ongkos pembeli rumput. Inilah Jakarta, demi uang manusia sedia jadi kuda.” (Pramoedya Ananta Toer, 1957; dikutip dari Erwiza Erman, 2013)
Kutipan sastrawan Pramoedya Ananta Toer di atas menunjukkan bagaimana peralihan delman ke becak di Jakarta. Pram pun cukup tegas dalam kutipan itu menyebut bagaimana transformasi moda transportasi delman ke becak menandai pergeseran dari tenaga kuda ke tenaga manusia. Dan tentu pula tegas Pram menyebutkan bagaimana tukang becak mengganti peran kuda dalam upaya mengais rezeki. Begitulah potret sejarah peralihan delman ke becak di Jakarta dalam pandangan Pram.
Lantas, bagaimana dengan becak di Kota Makassar? Berdasarkan sumber-sumber sejarah, tampaklah bahwa sejarah becak di Kota Makassar cukup panjang. Ia hadir di kota ini sebelum Proklamasi Kemerdekaan 1945 silam dan sampai kini masih bertahan di tengah sisa-sisa yang ada akibat gempuran kendaraan modern serba mesin.
Lalu siapa gerangan para tukang becak itu? Sejumlah sumber menyebut, para tukang becak di Kota Makassar umumnya berasal dari daerah seperti Kabupaten Maros, Gowa, Takalar, dan Jeneponto. Mereka umumnya berasal dari wilayah pedesaan di kabupaten-kabupaten itu. Alasan utama hijrah ke Kota Makassar adalah untuk mencari pekerjaan, sebab desa dirasa tak lagi dapat diandalkan sebagai sumber penghidupan: sarana pertanian bergantung pada curah hujan, infrastruktur desa yang buruk, sarana pendidikan terbatas, serbuan pangan impor di pasar, dan sebagainya.
Kondisi pedesaan yang terus krisis seperti itu memaksa sejumlah warganya menjadi kaum urban, mengadu nasib di Kota Makassar untuk mencari pekerjaan. M. Nawir, aktivis Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), menyebut sejarah tukang becak di kota ini adalah sejarah tentang kaum urban. Sebagian dari mereka meninggalkan tradisi bertani (urban permanen), sebagian lagi menjadi migran sirkuler (tidak permanen): bolak-balik desa-kota mengikuti siklus ekonomi agraris (M. Nawir, “Tukang Becak, Riwayat Petani Urban”; 2011).
Mereka datang ke Kota Makassar dengan modal terbatas dan kapasitas yang serba terbatas pula: tingkat pendidikan yang rendah dan keahlian yang nihil. Dengan kondisi serba terbatas ini, mereka tak mampu terserap dalam pasar kerja perkotaan. Maka bekerja di sektor informal menjadi satu-satunya solusi; entah menjadi buruh, PKL, sopir angkot (pete-pete), atau tukang becak.
Di Makassar, mereka berdomisili di rumah kerabat, atau menyewa kos-kosan, atau membangun gubuk di area tanah kosong. Bila telah mendapatkan tempat huni, biasanya kerabat yang lain di kampung halaman diajak pula hijrah ke Makassar untuk bekerja, terutama di sektor informal.
Mereka pun seringnya disentuh oleh program pembangunan Pemkot Makassar—walau tak seluruhnya tersentuh. Seperti program pembagian raskin atau program kesehatan gratis.
Becak vs Negara
Suburnya pertumbuhan kaum urban yang bekerja di sektor informal, khususnya sebagai tukang becak di Kota Makassar, dipersepsi sebagai beban pemerintahan kota. Bukan saja dalam aspek kependudukan, tetapi dalam pemanfaatan ruang kota juga dikhawatirkan tersasak dampak dari suburnya kaum urban ini. Barangkali karena itu, Pemkot Makassar pernah berupaya membatasi laju pertumbuhan becak. Pembatasan jumlah becak dan penarik becak di Kota Makassar pernah berlangsung pada tahun 1970-an silam. M. Nawir (ibid) mengutip catatan Dean Forbes dalam “Petty Commodity Production and Under-development: The Case of Pedlars and Trishaw Riders in Ujung Pandang, Indonesia” (1979: 156). Catatan ini menggambarkan bagaimana ekonomi sektor informal (becak, PKL, pedagang eceran) bersaing dengan ekonomi kapitalis, pemilik modal.
Diterangkan dalam catatan itu bahwa pada tahun 1976 jumlah becak yang beroperasi di Makassar sekitar 17.500 unit, pemiliknya sekitar 6.817 orang, menghidupi sekitar 68.000 jiwa keluarganya, atau 12,11 persen dari 561.501 jiwa jumlah penduduk Kota Makassar masa itu. Keadaan ini menjadi alasan pemerintah kota untuk melakukan pembatasan produksi becak. Becak hanya diproduksi untuk disuplai ke luar kota.
Kemudian, pemerintah kota mengajukan kebijakan transportasi yang disebut Layanan Khusus Angkutan Kota, yakni minibus. Sebanyak 176 unit minibus beroperasi di dua jalur utama dalam kota dengan tarif yang lebih murah daripada tarif becak, yakni Rp50 jauh-dekat. Sedangkan tarif becak pada masa itu Rp45 per kilometer. Dampaknya, terjadi penurunan jumlah becak pada tahun 1985, yakni sekitar 16.000 unit yang terdaftar.
Pembatasan operasi becak secara terang-terangan (legal) dilanjutkan Wali Kota Makassar Soewahyo sampai Amiruddin Maula (sumber: Paper/Alat Bengkel, Puskit Unhas, 2001). Pada masa pemerintahan Wali Kota Soewahyo (1988–1993), selain pembatasan produksi becak baru, wali kota juga mengeluarkan aturan tentang penggunaan helm, surat izin mengemudi becak, penggunaan lampu becak, serta pengaturan warna becak berdasarkan hari operasinya.
Pengaturan seperti itu menjadi alasan pemerintah kota melakukan penertiban dengan merazia becak-becak yang dianggap ilegal. Ribuan becak hasil razia dibuang ke laut di sekitar Markas Angkatan Laut Makassar, Ujung Tanah. Dan ini berarti ribuan pula tukang becak terbuang piringnya, lara hatinya, merana nasibnya.
Catatan M. Nawir menyebut, Wali Kota Makassar Malik B. Masry (1994–1999) menerbitkan Perda No. 3 Tahun 1995 tentang Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor di Kota Makassar. Dalam Pasal 6 ayat (4) disebutkan dua warna becak yang diizinkan beroperasi: kuning dan biru. Pengoperasian becak warna kuning pada Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Sedangkan becak warna biru beroperasi pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu.
Namun, pewarnaan dan penjadwalan operasi becak tidak efektif dan tidak konsisten. Pada masa pemerintahan Amiruddin Maula (1999–2003), perda tersebut hendak diberlakukan kembali. Tetapi komunitas tukang becak menolak. Maka, pada tanggal 26 Mei 2000, ribuan tukang becak berunjuk rasa di Balai Kota. Mereka menuntut penghapusan pembatasan warna, jadwal, dan jalur operasi becak. Sejak itu, kebijakan Pemerintah Kota Makassar terhadap sarana transportasi becak lebih longgar, tetapi Perda No. 3 Tahun 1995 tentang Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor di Kota Makassar tak pernah dicabut.
Di bawah kepemimpinan Ilham Arief Sirajuddin pada 2004 silam, becak tak sirna. Para tukang becak masih banyak ditemui beroperasi di ruas-ruas jalan perkotaan. Meski begitu, pada masa ini sebagian menyebut becak mulai tergerus secara pelan-pelan oleh kehadiran bentor.
Tetapi becak di masa itu, boleh dikata Pemkot Makassar cukup ramah pada mereka. Tak ada riak-riak dari tukang becak memprotes Pemkot dalam urusan kebijakan tentang becak. Dan Pemkot Makassar pun tak menerbitkan regulasi lokal terkait dengan pengaturan becak.
Pengaturan becak oleh pemerintah secara serius memang hanya dilakukan di masa pemerintahan Wali Kota Soewahyo hingga Amiruddin Maula. Namun sayangnya, yang diatur hanyalah pengendalian jumlah becak saja, bukan bagaimana mendongkrak pendapatan tukang becak dengan menetapkan tarif resmi penumpang becak.
Berbeda dengan kendaraan angkutan lainnya seperti pete-pete, bus, Damri, dan sebagainya—tarif kendaraan ini semua diatur oleh pemerintah. Sementara becak, tarif ditentukan berdasarkan kesepakatan penumpang dengan tukang becak bersangkutan. Maka tak heran bila negosiasi tarif sering kali kita saksikan atau pernah kita lakukan tatkala hendak mengendarai becak.
Becak dan Demokratisasi
Meskipun becak mulai tergerus oleh “adik tirinya” sendiri (bentor), tetapi moda transportasi bebas polusi dan polisi ini tetaplah menjadi “kendaraan rakyat”, ia tetaplah favorit rakyat. Ketika perayaan tujuh belas Agustus di Kota Makassar, seringkali ditemui perlombaan balapan becak di sejumlah sudut Kota Makassar. Pawai becak pun masih sering ditemui saat perayaan HUT kemerdekaan itu. Ini artinya, becak tetaplah lengket di hati rakyat. Semua ini boleh dilihat sebagai cara menegaskan eksistensi becak di tengah serbuan kendaraan bermesin modern.
Baca juga: Di Balik Buaian Transportasi Ramah Lingkungan
Dengan demikian, boleh dikata becak terus ada di tengah berbagai keadaan yang ada. Kita bisa memotret itu dalam sejumlah peristiwa lainnya. Bahkan di tengah isu demokratisasi yang terus berputar pun becak selalu turut serta.
Dalam gerak demokratisasi yang dimotori mahasiswa misalnya, pada April 1996 silam, becak memiliki peran penting. Demokrasi yang berbuah kerusuhan antara mahasiswa vs aparat keamanan (Polisi–TNI) yang dikenal dengan April Makassar Berdarah (AMARAH) 1996 itu, becak hadir dengan fungsinya. Pada 24 April 1996 itu, tiga mahasiswa UMI tewas dalam bentrokan antara pihak aparat keamanan. Saat itu, mahasiswa memprotes kebijakan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tentang kenaikan tarif angkutan umum.
Wali Kota Makassar pun menerbitkan keputusan penyesuaian terhadap kebijakan Menhub saat itu. Keputusan penyesuaian tarif tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 900, tertanggal 17 April 1996. Saat itu, hampir seluruh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berunjuk rasa menolak kenaikan tarif angkutan kota dari Rp300 menjadi Rp500.
Transportasi dalam Kota Makassar saat itu lumpuh. Transportasi publik, seperti pete-pete dan taksi mendadak libur. Masyarakat yang sebelumnya menumpangi angkutan pete-pete dan taksi terpaksa jalan kaki. Di tengah situasi seperti itu, becak satu-satunya moda transportasi yang bebas beroperasi.
Begitu pula saat kerusuhan berbau SARA (China vs Pribumi) yang pecah pada 15 September 1997 silam. Kerusuhan yang dipicu oleh terbunuhnya putri semata wayang dosen IAIN Alauddin Makassar, Noor Huda Noor, yang bernama Anni Mujahidah Rasuna (9), oleh Benny (etnis China) yang dikenal temperamen dan menderita kelainan jiwa. Benny juga diketahui putra seorang pedagang China yang menyuplai botol kecap dan saus.
Saat ia melintas di pertigaan Jl. Veteran Selatan–Jl. Kumala–Jl. Sultan Alauddin, Benny membacok bocah Anni Mujahidah Rasuna hingga tewas. Kabar pembacokan itu pun menyebar luas hingga ke Kabupaten Gowa—di mana Anni bersama kedua orang tuanya berdomisili. Maka pada malam harinya, kediaman Benny di Jl. Kumala diserbu ribuan warga yang sebagian dari Gowa. Malam itu, rekan-rekan Benny rupanya stand by pula (sekitar 500 orang). Tetapi apa daya, serbuan warga pribumi mengalahkan mereka. Benny sendiri dikabarkan tewas dalam peristiwa itu.
Keesokan harinya, massa pribumi protes seraya menjarah sejumlah toko/rumah milik warga Tionghoa. Mula-mula mereka bergerak ke Jl. Veteran, Jl. Penghibur, Jl. Nusantara, Jl. Timor, Jl. Sulawesi, Jl. Ahmad Yani, dan Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo sambil melakukan pengrusakan, pelemparan, dan pembakaran terhadap kendaraan dan rumah penduduk Cina. Sementara di depan kampus-kampus, mahasiswa orasi tiada henti. Kerusuhan ini berlangsung hampir satu pekan.
Dalam situasi seperti itu, moda transportasi Kota Makassar pun lumpuh. Dan di tengah kelumpuhan itulah, tukang becak hadir. Di sini, para tukang becak mengangkut warga yang hendak bepergian, tentu dengan tarif yang disepakati dengan penumpang.
Pada pekan awal Maret 1998 hingga 21 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa secara nasional dilancarkan untuk menuntut Presiden Soeharto mundur dari kursi kepresidenan. Di Kota Makassar, aksi demonstrasi mahasiswa berlangsung hampir setiap hari. Selain bakar ban mobil bekas, mahasiswa pun orasi di depan kampus masing-masing. Di samping itu, mahasiswa di kota ini pun pawai keliling kota dengan kendaraan roda sepuluh hingga roda dua.
Dengan kondisi begitu, lalu lintas di kota ini macet total bahkan lumpuh. Angkutan umum, seperti taksi dan pete-pete, jarang beroperasi, kecuali jalur-jalur tertentu dan jam tertentu, khususnya malam hari. Dengan begini, satu-satunya moda transportasi yang relatif bebas melintas mengangkut penumpang hanyalah becak. Bahkan, tidak sedikit tukang becak ikut bersama mahasiswa mengumandangkan “reformasi”.
Sampai pada akhirnya, pada Kamis, 21 Mei 1998, pukul 09.05 WIB, di Istana Merdeka, Jakarta, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. “Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998,” ujar Soeharto saat membacakan surat pengunduran dirinya.
Pada Pemilu 1999, tukang becak pun tak ketinggalan dalam momentum ini. Di Kota Makassar, mereka terlihat berkerumun dengan massa kampanye pemilu lainnya. Dengan menggunakan simbol-simbol parpol, mereka mengayuh becaknya menuju lokasi kampanye. Konon, mereka memperoleh puluhan ribu rupiah sekali terlibat dalam setiap kampanye. Begitupun yang terjadi dalam pemilu presiden secara langsung yang pertama kali dilakukan pada tahun 2004 lalu.
Ketika pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) dijalankan untuk pertama kalinya pada 2005 silam, dan di Kota Makassar dijalankan pada 2009, peran tukang becak cukup realistis. Mereka aktif turun kampanye bersama pasangan calon Wali Kota/Wakil Wali Kota di lokasi kampanye yang telah ditetapkan KPUD Makassar. Dengan simbol-simbol paslon seperti baju kaos atau bendera parpol pendukung yang dikibarkan di becak masing-masing, mereka begitu antusias meneriakkan yel-yel bersama massa pendukung lainnya. Dan konon, mereka pun dibekali puluhan ribu rupiah oleh tim paslon setiap pelaksanaan kampanye. Tetapi di era ini, “adik tiri” becak bernama bentor sudah mulai terlihat dalam kampanye para paslon.
Dengan itu semua, cukup terang bagaimana becak menunjukkan eksistensinya di tengah putaran demokratisasi yang bergerak di kota ini. Ia tak pernah menganggur di saat moda transportasi lainnya gugur di tengah maraknya demonstrasi. Dan yang paling penting kala itu, jasa mereka cukup berharga saat warga butuh kendaraan menuju tempat kerja.
Senjakala Becak di Abad “Android”
Meski jumlahnya terus menyusut, tak sama ketika tahun-tahun 1980-an/1990-an silam, becak di kota ini tetaplah ada. Kita temukan misalnya di pinggir Jl. Sultan Hasanuddin, di Jl. Ranggong, di Jl. Mannuruki, dan ruas jalan tertentu lainnya di kota ini. Cuma saja, penariknya rata-rata berumur 50-an tahun ke atas. Jarang lagi kita temukan penarik becak berusia remaja seperti era 1980-an/1990-an lampau. Selain karena penarik becak usia remaja hijrah ke bentor, sebagian juga di antara mereka hijrah kerja di berbagai sektor informal lainnya. Ada cerita yang dulu berkembang, entah benar atau tidak, bahwa regenerasi sopir pete-pete di kota ini direkrut dari para tukang becak usia muda.
Tetapi bukan berarti para tukang becak yang masih tersisa gagal membangun keluarganya. Dengan segala keterbatasannya, mereka menyadari pentingnya keluarga, terutama pendidikan anak-anak. Baihaqi Hendri Mangatta, dalam “Strategi Adaptasi Tukang Becak dalam Kehidupan Sosial Ekonomi” (Jurnal Holistik edisi Juli–Desember 2016) menuliskan, bahwa tukang becak kini menganggap pendidikan formal untuk anak di zaman sekarang sangat penting. Mereka kini berupaya sekeras mungkin untuk menyekolahkan anak mereka setinggi mungkin agar kelak memiliki kehidupan yang lebih baik dari dirinya.
Di Kota Makassar, ada sejumlah anak tukang becak berpendidikan tinggi. Misalnya, Dr. Anzar Makkuasa, S.H., M.H., seorang praktisi dan akademisi hukum di Kota Makassar. Akademisi dan lawyer ini cukup sukses walau latar belakang keluarganya adalah tukang becak.
Bukan hanya dalam pendidikan anak para tukang becak tak rela ketinggalan. Mereka pun kini tak ketinggalan dalam penggunaan teknologi komunikasi seperti handphone. Dikutip dari Baihaqi Hendri Mangatta (2016), tukang becak juga menggunakan teknologi seperti telepon genggam agar lebih memudahkan para penumpang untuk menghubungi mereka atau siapa pun yang membutuhkan bantuan mereka.
Tetapi harus diakui, keberadaan teknologi komunikasi smartphone berbasis Android semakin menggerus kehadiran becak di kota ini. Pada pekan awal Agustus 2015 lalu, perusahaan peranti lunak Gojek mengumumkan bahwa layanan mereka resmi tersedia di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mulai Jumat (8/8/2015). Makassar menjadi kota kelima operasional Gojek setelah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Bali.
Layanan antar-jemput menggunakan jasa ojek sepeda motor berbasis aplikasi Android Gojek ini terbukti mengalihkan warga dari sebagai penumpang becak atau bentor ke penumpang Gojek. Selain praktis (request Gojek dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja), juga terbilang murah dan jumlah tarif langsung dapat diketahui penumpang berdasarkan jarak tempuh tujuan. Di sini, tak ada lagi negosiasi tarif.
Apalagi, Gojek dapat diorder bahkan saat larut malam sekalipun, dan langsung menjemput sang penumpang di depan rumah, atau di mana pun sang penumpang hendak dijemput. Dan kini, Gojek pun tak sekadar melayani angkutan penumpang, tetapi juga melayani pesanan makanan/minuman, dan pengiriman barang-barang ringan dengan aman. Tarifnya pun cukup terjangkau. Pelanggannya, tak hanya masyarakat kelas bawah, ia menjangkau pula kelas masyarakat atas lintas profesi dan lintas usia.
Bila di tahun 2004 silam, becak tersingkir oleh serbuan bentor, maka hari ini, becak tersenggol oleh Gojek, bahkan bentor pun tergerus olehnya. Perpaduan moda transportasi dengan teknologi komunikasi berbasis Android itu pelan-pelan menyingkirkan becak dan bentor. Dan dari aspek keamanan, Gojek dianggap relatif aman dari serangan kaum begal dibanding becak dan bentor. Waktu tempuh yang digunakan Gojek pun jauh lebih cepat dibanding becak. Apalagi dengan kian macetnya lalu lintas kota ini, Gojek lebih lincah menerobosnya dibanding becak. Di sini, senjakala becak semakin menganga di depan mata. Ia terancam punah.
Barangkali ancaman kepunahan becak itulah hingga Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, mengabadikannya dengan membangun patung becak berukuran raksasa, atau sekitar tiga kali lipat dari ukuran becak normalnya, di anjungan Pantai Losari, Makassar, pada tanggal 21 Desember 2012 lalu. Patung becak raksasa ini diresmikan Wakil Presiden RI, Muhammad Jusuf Kalla.
Lantas, benarkah senjakala becak kini sedang berlangsung? Benarkah kepunahan becak tak lama lagi? Bila benar, di antara penyebab senjakala dan kepunahan itu—barangkali pemicu mencoloknya adalah kehadiran teknologi komunikasi yang semakin canggih (Android) yang dipadu dengan layanan antar-jemput penumpang roda dua (Gojek). Ia terancam punah bukan karena kebijakan spesifik pemerintah seperti di era 1980-an/1990-an silam, tetapi dipunahkan oleh kemajuan pesat teknologi komunikasi yang menerjang bak tsunami itu.
Editor: Kamsah Hasan