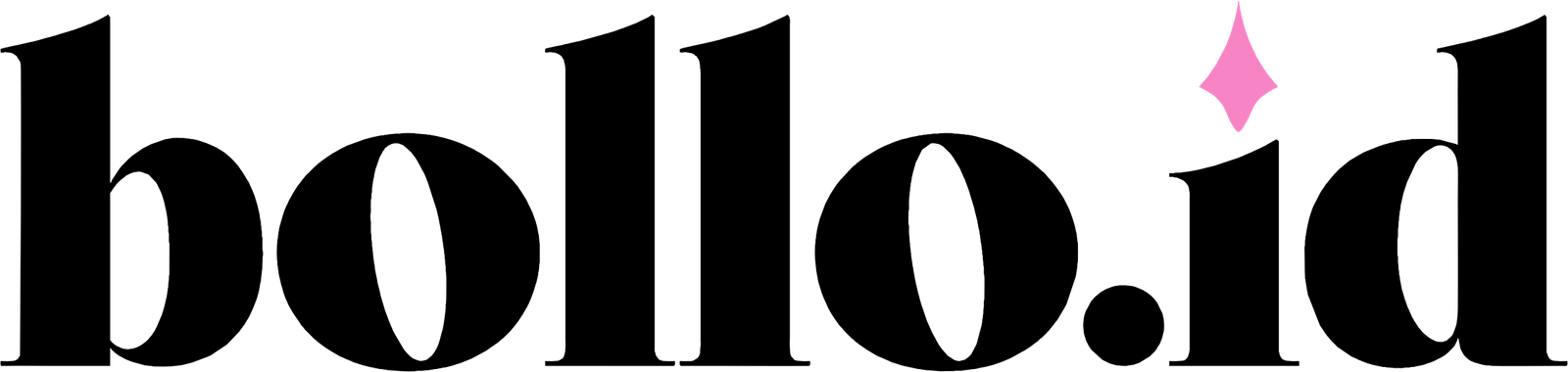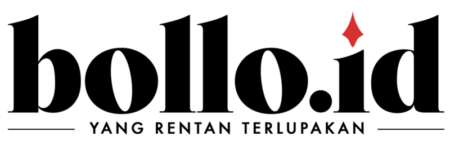Saat Firman Saleh, dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Hasanuddin, didapati bersalah melakukan kekerasan seksual, majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan pidana dua tahun enam bulan penjara yang lebih berat dari tuntutan jaksa. Namun di ruang sidang kelas I itu, pada Rabu pekan lalu, korban justru tidak merasa menang. Baginya, setiap hari sejak 25 September 2024 adalah hukuman tanpa akhir, tubuh yang drop, perawatan di ruang intensif rumah sakit, trauma yang kambuh setiap kali harus melihat wajah pelaku, bahkan hanya lewat layar panggilan video.
“Korban ini tidak hanya berkorban sekali, tapi berkorban untuk kedua kalinya,” kata Aflina Mustafaina, Ketua Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) Sulawesi Selatan, salah satu pendamping korban, dalam jumpa pers usai sidang.
“Dia rela mengulangi trauma demi satu tujuan agar tidak ada korban lain di Unhas.”
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Tujuan mulia itu, ternyata, adalah beban yang hampir mustahil. Dari sekitar 300 laporan kekerasan seksual yang masuk ke Satgas PPKS Unhas sejak didirikan pada 4 November 2022. Kasus Firman Saleh, dengan nomor perkara 1381/Pid.Sus/2025/PN Makassar adalah satu-satunya yang berani menembus tembok polisi, jaksa, dan pengadilan. Sisanya?
“Tidak ada tindak lanjut serius dan tidak ada perhatian nyata dari universitas,” kata Aflina.
“Masih ada sekitar 300 predator seksual yang bercokol di Unhas. Ada yang masih mengajar, ada yang dimaafkan, ada yang sudah profesor.”
Itu sebabnya, kata Pino, korban rela berkorban.
“Dia tidak ingin ada korban lain. Seharusnya Unhas memberikan penghargaan besar.”
Tuntutan yang Menghina Undang-Undang
Jaksa Penuntut Umum Nur Fitriani menuntut Firman Saleh pidana penjara satu tahun enam bulan dan denda Rp10 juta. Padahal, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS mengancam pidana maksimal empat tahun penjara dan denda Rp50 juta. Karena terdakwa berstatus pendidik, ancaman pidana itu wajib ditambah sepertiganya sehingga setara dengan lima tahun empat bulan penjara.
“Tuntutan itu sangat normatif,” ujar Aflina Mustafaina dari Koalisi Bunga Mawar untuk Kesetaraan dan Kesepadanan. “Pertimbangannya tidak pernah berperkara, sopan, kepala rumah tangga. Jaksa mengabaikan relasi kuasa yang sangat kuat.”
Dalam pleidoinya, Firman Saleh menolak mengakui perbuatannya. Pelaku juga tak pernah minta maaf. Hanya setelah ditahan pada 30 Juni 2025, ibunya mendatangi ibu korban untuk meminta maaf. Sejak proses di Satgas PPKS, tujuh pernyataannya hanya satu yang benar. Bandingkan dengan korban, dari sepuluh pernyataan, satu yang keliru—tepatnya soal jam kejadian, tapi CCTV membuktikan.
“Sampai detik akhir di persidangan pun tidak diakui (perbuatannya).”
Untunglah majelis hakim, Ketua Wahyudi Said, anggota Zulkarnaen dan Kurnia Dianta Ginting memutuskan di atas tuntutan berupa 2,5 tahun penjara, denda Rp12 juta, dan restitusi Rp6,45 juta ke korban.
“Tapi ini bukan akhir. Besok bisa saja terdakwa banding.” kata Samsang Syamsir, Koordinator FIK Ornop Sulsel.


Vonis Bukan Akhir Pemulihan
Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Devi Rahayu, menegaskan bahwa putusan pengadilan terhadap pelaku kekerasan seksual tidak otomatis menuntaskan penderitaan korban. Dalam kasus kekerasan seksual yang menjerat dosen Universitas Hasanuddin, Firman Saleh, Devi menilai pemulihan korban dan dukungan sosial masih menjadi pekerjaan rumah besar negara dan masyarakat.
Menurut Devi, pelaporan kasus kekerasan seksual ke aparat penegak hukum dilakukan korban dengan tujuan memperoleh keadilan yang menyeluruh. Proses pidana tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang dibentuk sebagai respons negara terhadap tingginya angka kekerasan seksual serta keterbatasan regulasi sebelumnya dalam melindungi korban.
“Pemidanaan pelaku penting, tetapi keadilan bagi korban tidak berhenti divonis. Korban membutuhkan dukungan masyarakat agar tidak berjuang sendirian,” kata Devi.
Ia juga menyoroti masih kuatnya stigma terhadap korban kekerasan seksual. Dalam banyak kasus, korban justru menghadapi kecenderungan disalahkan, terutama karena kuatnya budaya patriarki di masyarakat. Pertimbangan nama baik keluarga pun kerap menjadi beban tambahan bagi korban saat memutuskan melaporkan kekerasan yang dialaminya.
“Situasi ini berdampak pada relasi sosial korban. Perhatian publik sering terpusat pada korban dengan berbagai penilaian, bukan pada pelaku,” ujar Devi.
Devi menegaskan, UU TPKS telah mengatur hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Namun, implementasi di lapangan masih sangat bergantung pada keberpihakan aparat penegak hukum, institusi pendidikan, serta ketersediaan layanan pendampingan yang memadai.
Ia menilai seluruh fase dalam perkara kekerasan seksual, mulai dari peristiwa kekerasan, proses hukum, hingga pascaputusan, merupakan fase berat bagi korban karena melibatkan penderitaan multidimensi, baik fisik, mental, sosial, maupun ekonomi.
Terkait persepsi publik, Devi menyebut masih banyak kesalahpahaman yang menganggap keadilan telah tercapai ketika pelaku dijatuhi hukuman. Padahal, dalam sejumlah kasus, hukuman yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan beratnya tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU TPKS.
Dalam konteks kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, Devi menekankan bahwa relasi kuasa harus menjadi pertimbangan utama. Pelecehan seksual fisik yang dilakukan oleh tenaga pendidik merupakan pelanggaran serius karena berdampak struktural terhadap korban dan mencederai ruang aman pendidikan.
“Trauma akibat kekerasan seksual tidak memiliki batas waktu yang pasti. Tanpa penanganan profesional, dampaknya bisa berlangsung bertahun-tahun, bahkan seumur hidup,” kata Devi.
Komnas Perempuan, lanjutnya, mendorong negara, kampus, dan masyarakat untuk memastikan korban memperoleh pemulihan yang layak serta dukungan berkelanjutan agar dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.
Korban yang Tak Pernah Pulih
Rentang waktu antara kejadian September 2024 hingga putusan 2026 merupakan “proses hukum yang sangat panjang” dan “sangat tidak adil” bagi korban. Aflina menceritakan, korban berkali-kali dipanggil penyidik untuk memberikan keterangan ulang. Saksi-saksi, termasuk orang pertama yang diajak korban bicara setelah kejadian, turut dipanggil.
“Korban mengalami trigger pada saat dipertemukan dengan pelaku dua kali. Satu kali di Polda via video call, meski berbeda ruangan, drop psikisnya sampai sakit satu bulan,” kata Pino, sapaannya.
Saat memberikan kesaksian dan bertemu terdakwa di pengadilan, sakit fisiknya sampai hari ini belum sembuh.
Tuntutan jaksa yang hanya satu tahun enam bulan justru memperparah keadaan. Restitusi sebesar Rp6.455.000 terasa jauh dari memadai jika dibandingkan dengan biaya waktu, tenaga, dan beban emosional yang harus ditanggung korban, termasuk rangkaian perawatan medis di rumah sakit.
Kampus yang Berpura-pura Tak Tahu
Kehadiran tiga dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) dihadirkan sebagai saksi meringankan. Dalam wawancara dengan Bollo, 5 Februari, Burhan Kadir mengakui bahwa ia dipanggil ke persidangan pada 12 Januari lalu—bukan oleh pengadilan, melainkan atas permintaan istri terdakwa. “Ini murni urusan pribadi dan permintaan istri terdakwa,” katanya tegas.
Sebagai saksi, Burhan hanya bisa menceritakan keseharian Firman selama ini. Bagaimana ia sebagai rekan kerja. “Tidak melihat kejadian atau berada di lokasi saat kejadian jadi kesaksiannya cuma seputar keseharian (terdakwa),” ujarnya.
Di persidangan, hakim dan jaksa bertanya seputar relasi kerja. “Kenal dengan terdakwa sebagai apa, kenal sama korban sebagai apa, berapa lama kenal, bagaimana proses pembimbingan skripsi, bisa memang kah sampai malam bimbingannya?” ujar Burhan menirukan pertanyaan hakim.
Burhan mengaku sangat mempertimbangkan dampak sosial dari kesaksiannya. “Kampus seharusnya menjadi ruang aman, dan setiap kontribusi akademik harus sejalan dengan upaya perlindungan korban serta pencegahan kekerasan seksual,” katanya.
Tapi ia juga mengakui: “Kampus tidak tahu kalau saya sebagai saksi meringankan.”
Bollo telah menghubungi Kaharuddin dan Eri Iswari, dua saksi lain. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada respons. Pesan yang dikirimkan hanya centang dua.
Koordinator Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK Ornop) Sulsel, Samsang Syamsir, menilai kehadiran akademisi sebagai saksi meringankan dalam perkara seksual bisa memantik efek chilling.
“Korban itu bukan hanya mengalami kekerasan secara fisik atau seksual, tetapi juga mengalami trauma yang panjang, rasa takut, dan tekanan mental yang terus berulang,” kata Samsang.
Status ASN yang Mengendap
Sampai saat ini, status Aparatur Sipil Negara (ASN) Firman Saleh belum dicabut. Dekan FIB, Andi Muhammad Akhmar, mengatakan kampus belum menerima SK Menteri mengenai pencabutan itu.
“Ketiga dosen yang menjadi saksi tidak mewakili institusi,” tambahnya dalam pesan singkat, 6 Februari.
Di sisi lain, Pino menyerang rekomendasi kampus kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) yang redaksi suratnya “memohon untuk mempertimbangkan” pelaku dipecat.
“Kalau mau tegas, tidak perlu pertimbangan aksi mahasiswa. Kampus harus bertanggung jawab moral.”
Samsang menambahkan, perlindungan korban harus jadi prioritas. Sebelum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) intervensi, pendampinglah yang menjaga keamanan, memantau pergerakan korban, siapa yang menemani, termasuk keluarganya.
PR yang Belum Beres
Putusan bukan akhir. Bagi korban, pemulihan jangka panjang masih menanti. Bagi kampus, PR untuk membangun safeguard policy belum selesai.
“Jika putusan inkrah, kampus harus memecat otomatis,” kata Pino. “Tapi meski di bawah dua tahun, seharusnya moralitas sudah cukup alasan.”
Korban sendiri sudah lulus, tapi trauma tidak kunjung tamat.
“Kita belum selesai memperjuangkan kampus bebas kekerasan seksual,” kata Samsang. “Masih banyak PR kita bersama.”
Hingga saat ini, kepastian belum ada. Firman Saleh masih punya hak banding. Dan sekitar 300 laporan lain masih mengendap di lemari Satgas PPKS Unhas.
Catatan: Kasus ini masih membuka kemungkinan upaya hukum lanjutan. Namun bagi korban, perjuangan untuk pulih baru saja dimulai.
Editor: Kamsah Hasan