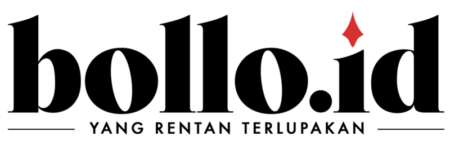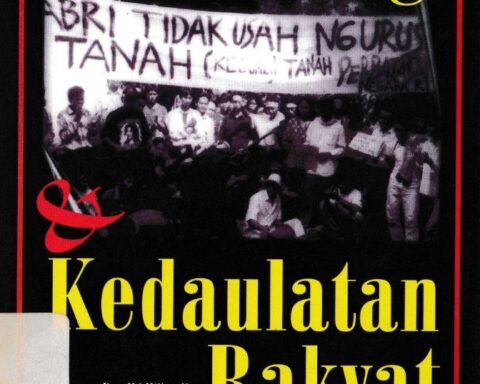Kepada yang terhormat,
KOTA
di,-
Tempat
Pertama-tama, saya ucapkan selamat ulang tahun yang keempat abad lebih. Semoga engkau sehat dan stabil selalu.
Saya sebenarnya tak pernah berpikir menyuratimu, apalagi memprotesmu. Karena saya tahu, sekeras apa pun bunyi protes kepadamu, engkau hanyalah bergeming. Engkau memang mendengar protes, tetapi engkau tetap beku laksana es balok. Protes engkau anggap hanya kentut berlalu. Itulah mengapa saya hanya menyuratimu.
Bila punya waktu, bacalah surat ini. Baca saja. Engkau mau membacanya, itu kesyukuran bagiku. Setelah kamu baca, kamu mau simpan surat ini atau membuangnya, terserah padamu. Asalkan kamu baca saja. Tak merespons pun tak soal.
Sebab memang saya tak pernah berharap engkau merespons surat ini. Engkau merespons atau tidak, terserahlah. Karena saya tahu, keluhan tak pernah kau respons.
Kota, engkau sebenarnya diciptakan untuk apa? Engkau dibangun untuk siapa? Engkau ditata untuk apa sebenarnya? Jawaban pertanyaan-pertanyaan itu barangkali engkau tahu, bahwa semuanya untuk warga yang menghunimu.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Para ilmuwan kuno hingga ilmuwan modern, perencana dan perancang kota, semuanya menyatakan bahwa engkau diperuntukkan bagi seluruh warga. Kehadiranmu mengabdi untuk seluruh warga, setidaknya memberi mereka kenyamanan, keamanan, dan mata pencaharian yang layak. Karena itu, engkau haruslah sayang pada warga.
Tetapi engkau tampaknya tak adil. Kasih sayangmu diskriminatif. Warga yang kau sayangi hanyalah warga yang berduit sahaja. Warga yang tak pernah mendompeti lembaran uang dua ribu rupiah, warga yang tak pernah alpa sarapan roti bakar dan madu. Warga yang punya rekening tak secuil.
Engkau memberi tempat hanya pada warga yang raganya tak pernah terkena sinar matahari selain karena mereka jogging. Engkau cukup peduli pada mereka yang berkeringat hanya saat berolahraga. Engkau bela rasa hanya pada mereka yang bisa mewariskan hartanya hingga lapis ketujuh. Engkau begitu perhatian pada mereka yang tak pernah memasak selain dimasakkan oleh babu yang diupahnya.
Engkau mendengarkan mereka yang berjejer mobil di garasinya. Engkau membuka mata pada mereka yang berkali-kali plesiran atau melancong ke provinsi lain hingga luar negeri. Engkau membuka hati pada mereka yang bertubi-tubi umrah. Engkau mengulurkan tangan besarmu hanya pada mereka yang kerap menyogokmu atau mereka yang lihai mencuri di atas tubuhmu.
Baca Juga: Masih Ingatkah Kita Becak?
Kota, sebagai warga, sebenarnya saya sangat kecewa denganmu.
Engkau tak adil. Warga tak berduit engkau acuhkan. Mereka yang tak punya tabungan jumbo tak kau hiraukan. Padahal, saban hari mereka tercekik dengan kebutuhan ekonomi yang tak ekonomis. Di dapur-dapur mereka jarang lagi ditemukan terasi. Padahal, di pasar-pasar tradisional terasi masih banyak dijajakan dengan murahnya.
Mengapa engkau tak adil pada pedagang kecil di pasar-pasar dan pedagang kaki lima? Saban hari mereka menyetor pajak retribusi, tetapi setiap saat mereka merasa terancam direlokasi. Kota, tidakkah mereka telah berkontribusi kepadamu? Atau uang yang mereka setor itu kamu anggap receh?
Kota, mengapa engkau terlalu kapitalis? Wargamu tak boleh kau sedot seenaknya. Mereka bukan sebatang rokok yang habis diisap lalu dibuang. Kamu kan tahu, tugasmu menghimpun semua kalangan untuk mewujudkan keadaban bersama. Orang-orang kecil kau sedot bukanlah tindakan beradab. Kamu lupa, ya, Pancasila sila kedua itu?
Kota, mengapa engkau membiarkan orang-orang berduit menyanggahmu dengan uang? Ingat, uang bukanlah vitamin yang baik untukmu. Uang yang sering disebut investasi itu, dalam waktu lama, akan menggerogoti imunmu. Memanglah engkau kota tua, bergaram merintangi tantangan zaman. Tetapi jangan lupa, uang investasi dalam tempo lama hanya merampas keseimbanganmu. Imunmu goyah.
Kota, sadarlah, engkau kini mulai tak seimbang. Setiap musim penghujan, engkau banjir. Hujan sejam, banjir berjam-jam. Dan yang sering terdampak adalah orang-orang kebanyakan—terutama warga lorong. Drainase tersumbat. Memang drainase pernah dikeruk, tetapi itu beberapa tahun lalu.
Ketika banjir begitu, engkau menyalahkan warga yang membuang sampah sembarangan. Memang itu satu soal. Tetapi soal paling serius adalah karena engkau mengizinkan orang-orang berduit membangun bisnis di atas lahan yang sebenarnya berfungsi menyerap air hujan. Sehingga air hujan tak sanggup kau tampung lagi seperti sedia kala.
Engkau memang kota berlaut. Tetapi engkau mulai kalut saat banjir datang. Lautmu tak sanggup mengakomodasi air banjir yang menumpuk. Karena lautmu tak seimbang pula seperti dulu. Mengapa begitu? Saya tahu, engkau tahu masalahnya.
Lautmu ditimbun tanpa ingin tahu dampaknya. Ratusan hektar lautmu disulap jadi daratan bisnis megah. Ruang gerak air pada lautmu menyempit. Daratan bisnis megah itu merampas keseimbangan lautmu. Dengan itu, kaum pebisnis memanen rupiah, wargamu menuai derita ketika banjir melanda.
Kota, sebagai warga, sebenarnya saya sangat kecewa denganmu.
Kota, derita wargamu tak kunjung sudah-sudah. Di lorong, kemiskinan menumpuk. Mungkin sudah berabad-abad lamanya. Wargamu di lorong mencari kerja hanya untuk bekal kebutuhan dalam sepekan. Mereka terima upah sekali sepekan—itu pun kalau mereka dapat job. Mereka buruh, tukang bangunan, kuli, tukang parkir, hingga tukang tagih utang.
Dan tahukah kamu, Kota, di lorong-lorong banyak beredar rentenir berjubah koperasi simpan pinjam. Padahal, tak ada yang simpan, yang ada hanyalah pinjaman berbunga yang tak harum, dan mencekik. Tetapi warga tahu, bagaimana cekikan itu menyesakkan dada. Menempuh itu adalah keterpaksaan. Sebab mereka tak punya sertifikat rumah yang dapat digadai di bank.
Mereka tak punya mobil yang dapat digadai di lembaga pembiayaan. Mereka tak punya SK PNS yang bisa dijaminkan di bank pemerintah. Mereka tak punya perhiasan yang bisa dijadikan tanggungan di pegadaian. Yang mereka punya hanyalah KTP dan Kartu Keluarga, dan itulah syarat administrasi untuk meminjam uang di rentenir; mudah, namun tak murah.
Kota, sebagai warga, sebenarnya saya sangat kecewa denganmu.
Kota, kau sebenarnya tega, membiarkan kekerasan berputar bagai jarum jam. Lihat di sana, pada leher seorang gadis yang melintas di jalan, tertancap busur tajam. Lihat di sana, orang-orang lari ketakutan lantaran sekawanan preman muda tengik menarik karet busur di tangannya. Mengapa kau diam dengan kejadian itu, Kota?
Kota, engkau memang kejam, seolah membiarkan warga di lorong-lorong berperang laksana gerilyawan. Dengan parang, dengan badik, dengan busur, dengan batu sebagai senjata. Perang di sana tak kunjung padam. Perang di sana hanya istirahat bagai musafir yang mampir di tengah perjalanannya, lalu esok melangkah lagi.
Perang di sana meletus setiap saat. Dan kenyamanan—keamanan lorong—tak dapat diprediksi. Cuaca dapat diprediksi, tetapi perang kota di lorong sana sulit diprediksi. Mengapa engkau membiarkan itu semua, Kota?
Kota, tahukah engkau, perang itu melambangkan bila engkau tak punya cinta, dan pada akhirnya wargamu juga krisis cinta. Sudilah engkau mencari cara menyudahi perang tak beradab itu agar cinta dapat tumbuh dalam ruang yang tak tercekik.
Kota, engkau memang tampak terang, tetapi sebenarnya engkau gulita. Engkau terang karena lampu-lampu, bukan karena pancaran aura dan jiwamu. Aura dan jiwamu gelap lantaran kasih sayangmu tak adil, perlakuanmu diskriminatif, tangan besarmu tak merangkul semua kalangan. Martabatmu sebagai ruang bagi semua manusia terkelupas.
Untuk sementara, demikian surat saya, Kota. Engkau jangan maknai ini sebagai surat protes, karena saya tahu engkau tak gembira diprotes. Selain itu, saya pun takut padamu, karena saya tahu engkau punya banyak penjaga yang hanya mau tersenyum padamu sahaja.
Sekali lagi, ini bukan surat protes, Kota. Bukan juga surat kebencian, bukan pula surat kemarahan. Barangkali ini hanya surat kekecewaan yang muram. Mungkin sebentar lagi kamu anggap gurau basi yang tak berguna.
Dan satu lagi, Kota, janganlah kau sombong, janganlah congkak, karena itu tak pantas untukmu, dan tak baik bagi wargamu yang merintih derita di lapis bawah sana. Ingat itu.
Editor: Kamsah Hasan