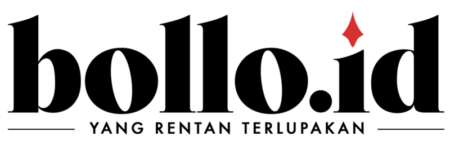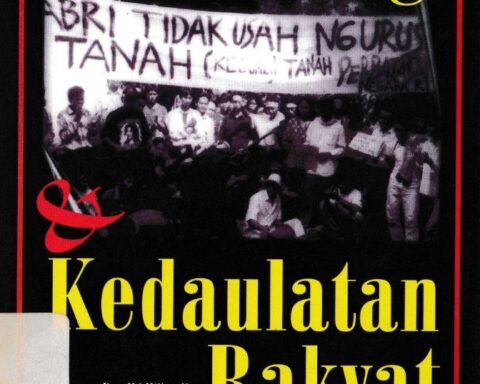Di kepulauan ini, kita kerap meminjam bahasa yang tak sepenuhnya kita percaya. Kita bilang pepohonan “tumbang”, seakan mereka memilih menyerah. Kita bilang hutan “mati”, seolah ia mengambil keputusan sendiri. Padahal pohon tidak pernah ingin mati. Yang memutuskan nasib mereka adalah manusia – dengan kapak, rencana tata ruang, dan tanda tangan pejabat yang memandang tanah sebagai lembar kosong yang siap dicoret.
Bencana besar di tiga provinsi Sumatra pada akhir November hingga awal Desember 2025 adalah catatan kaki dari keputusan-keputusan itu. Data BNPB per Rabu, 3 Desember, 753 orang ditemukan meninggal. Sebanyak 650 orang masih hilang, 2.600 terluka, 1,5 juta terdampak, dan 576 ribu lebih mengungsi. Angka-angka itu biasanya kita dengar dalam rapat anggaran – dingin, padat, tanpa getir. Seakan kita telah mufakat bahwa penderitaan adalah bagian dari biaya pembangunan.
Tentu tidak. Bencana ini bukan kemurkaan alam yang tiba-tiba turun dari langit. Ia hasil dari sebuah kronologi yang lebih panjang daripada curah hujan. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia kehilangan hampir 10 juta hektare tutupan pohon. Lebih dari empat juta hektare di Sumatra saja sejak 2001. Tahun 2023, Indonesia masih masuk lima besar dunia dalam kehilangan hutan primer. Kita menurunkan laju deforestasi, tetapi tidak menghentikannya; bahkan keberhasilan statistik itu tak banyak berarti di daerah yang kini berantakan.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Kerusakan yang kini menenggelamkan kampung-kampung itu sudah tercatat jauh sebelumnya. Aceh sudah kehilangan lebih dari 320 ribu hektare hutan primer basah. Sumatera Utara hampir 400 ribu hektare. Hulu sungai-sungai yang dulu teduh berubah menjadi ladang sawit, kebun industri, atau lubang tambang. Ketika akar hilang, tanah meluncur. Ketika bukit dibuka, air kehilangan kendali. Kita tahu rumusnya tapi kita seperti memilih untuk melupakannya.
Di balik bencana, ada ekonomi yang bekerja. Ada harga tandan sawit yang terus didorong naik. Ada pabrik yang lapar pasokan. Ada konsesi yang diberikan tanpa jeda. Ada prosedur perizinan yang lebih sering membaca rekomendasi investor ketimbang suara warga. Dan hasilnya tak pernah mengejutkan; yang tenggelam bukan gedung-gedung tinggi. Yang terseret bukan kantor pemerintahan. Yang hanyut selalu rumah-rumah warga. Sialnya, mereka yang tak pernah dimintai pendapat ketika batas-batas konsesi digambar di atas tanah mereka.
Setiap kali bencana datang, negara mengulang liturgi yang sama. Pejabat hadir dengan rompi seragam. Kamera menyesuaikan sudut terbaik. Bantuan dibagikan; janji evaluasi ditegaskan. Setelah itu, kesenyapan kembali berkuasa. Izin jalan terus. Perusahaan yang sama menanami tebing-tebing yang sama. Di banyak tempat, warga kembali menetap di lokasi yang sama, seperti menunggu perulangan.
Ada yang lebih senyap dari itu. Absennya suara moral dari institusi yang seharusnya menjaga nurani publik. Kita selalu melihat doa bersama, zikir memohon keselamatan, atau khutbah yang mengajak sabar. Namun hampir tak pernah kita dengar pernyataan tegas bahwa mengubah hutan lindung menjadi perkebunan adalah kedurhakaan terhadap sesama manusia. Bahwa memperjualbelikan izin adalah tindakan yang merampas masa depan satu desa. Alam diberi tugas memaafkan; manusia tak diberi teguran.
Krisis Ekologis dan Moral
Krisis ekologis ini adalah krisis keberanian moral. Kita tak berani menyebut perusakan hutan dalam skala besar sebagai kejahatan, meski korban-korbannya lebih banyak daripada beberapa konflik bersenjata. Kita kehilangan pejabat yang memahami bahwa izin buka lahan bukan hanya administrasi, tapi keputusan yang menentukan hidup dan mati seseorang. Kita kehilangan pemuka masyarakat yang bersedia menyebut dosa ekologis dengan bahasa yang tidak berputar-putar.
Ironi terbesar justru hadir di panggung bencana. Kita menyaksikan para pejabat yang tampil paling hidup ketika ribuan orang kehilangan rumah. Mereka menyusuri lumpur sambil memberi instruksi seakan bencana ini datang tanpa tanda. Kita tidak mendengar kalimat sederhana namun penting.
“Saya ikut bertanggung jawab,”
“Saya akan mundur.”
Tak ada malu yang diucapkan. Padahal setiap korban menyimpan jejak kesalahan. Izin yang terlalu mudah, pengawasan yang terlalu longgar, dan pengetahuan yang terlalu sering disingkirkan oleh kepentingan lain.
Sumatra hanyalah halaman pertama dari kitab yang sedang ditulis negara. Kalimantan, dengan Barito dan Kapuas yang terus dibuka, telah memberi peringatan lewat banjir awal 2025 yang merendam puluhan ribu orang. Papua, yang menyimpan hutan primer terbesar, kini dilalui jalan untuk proyek ketahanan pangan.
Deforestasinya mencapai lebih dari 25 ribu hektare pada 2024 dan terus meningkat pada 2025. Sulawesi kehilangan hingga seperlima tutupan hutannya dalam 15 tahun. Di Jawa, hutan yang tersisa hanya sekitar tiga persen, sementara lereng Merapi dan Slamet terus digerus tambang pasir dan vila-vila baru.
Ada kesamaan dari seluruh kawasan itu. Izin lahir dulu, bencana menyusul. Perbedaannya hanya waktu. Jika kebijakan ekstraktif terus berjalan, moratorium sawit tetap bocor, dan AMDAL tetap menjadi dokumen yang disesuaikan dengan keinginan pemilik modal, tragedi di Aceh, Sumbar, dan Sumut akan menjadi pola, bukan penyimpangan.
Dalam negeri yang pepohonannya mati dalam kesunyian, para pejabat justru tampil dengan suara paling lantang. Mereka tampak paling sibuk ketika rakyat terbaring, dan paling tenang ketika hutan runtuh. Dua kematian itu – kematian pohon dan matinya kepekaan – saling menguatkan.
Pada akhirnya, kita berhadapan dengan sebuah pertanyaan yang sederhana.
Jika ratusan pohon dapat ditebang demi sebuah izin, dan ratusan warga dapat mati karenanya, mengapa tak satu pun pejabat bersedia mundur demi keselamatan publik?
Pertanyaan itu akan terus menggantung. Dan selama ia tak dijawab, kita tinggal menunggu hujan berikutnya.