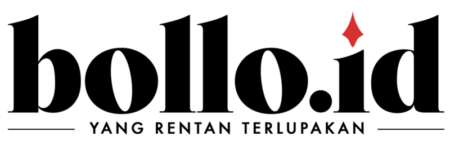Pemindahan artefak daerah dari balai arkeologi yang ada di berbagai daerah ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pusat menjadi polemik. Mobilisasi itu dinilai sentralistik.
Ini bermula pada Oktober 2023, lalu. BRIN mengumumkan rencana pembangunan gedung khusus koleksi artefak di BRIN pusat yang bertempat Cibinong, Jawa Barat. Tujuannya, memusatkan temuan arkeologi dari seluruh Indonesia dengan alasan perawatan, keamanan, dan kemudahan penelitian.
“Mulai Juni 2024, beberapa daerah seperti di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Bali, dan Papua mengalami wacana pemindahan,” kata Koordinator Aliansi Penjaga Jejak Peradaban, Andi Muh Syahidan Ali Jihad dalam webinar “Sentralisasi Artefak: Solusi atau Merusak Data?”, Senin, 1 September 2025.
“Masyarakat, termasuk masyarakat adat menolak rencana tersebut,”
Basran Burhan, seorang arkeolog menganggap pemindahan artefak ini begitu sentralistik, karena akan menyulitkan akses masyarakat setempat ke artefak tersebut. Jarak yang jauh, peluang dikenakan biaya, dan izin birokratis mungkin kelak dihadapi masyarakat.
“Ya, tentu saja bukan hanya untuk mahasiswa ya, karena barang ini kan barang publik, sehingga ya semua orang berhak untuk bisa mengakses temuan-temuan tersebut, baik mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat,” kata Basran.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Dalam webinar ini, Sasa Sofyan Munawar, Direktur Pengelolaan Koleksi Ilmiah BRIN menjelaskan tata kelola koleksi ilmiah di BRIN, yang menyimpan koleksi ilmiah 7.778 spesimen artefak.
Pemindahan ini, kata Sasa akan diiringi dengan digitalisasi data koleksi ilmiah. Data artefak bisa diakses di website BRIN yang terbuka untuk masyarakat (publik).
Melanjutkan dari penjelasan Sasa tentang digitalisasi data, Fakhri dari tim riset BRIN bilang, keamanan data tersebut, menjadi salah satu alasan pemindahan fisik artefak. Digitalisasi data artefak daerah ini kemudian dijadikan tanggapan atau respons atas isu pemindahan artefak yang sentralistis.
“Tidak ada perubahan data yang kami lakukan karena data yang tersimpan di masing-masing artefak yang berada di masing-masing balai, eks balai, itu tetap akan terikut ke artefak yang kami bawa,” kata Fakhri.
“Jadi kalau dalam konteks BRIN, temuan arkeologi ini itu dipandang sebagai koleksi ilmiah.”
Meski begitu, Dosen Arkeologi Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Muhammad Syaiful, bilang dalam kepentingan akademik, pemindahan artefak ini turut membatasi akses mahasiswa, dosen, peneliti, dan masyarakat terhadap artefak daerah. Pemindahan artefak daerah ke pusat hanya menjadi solusi satu pihak, yaitu BRIN.
“Apakah ini solusi? Saya pikir ini adalah solusi untuk BRIN,” katanya.
“Tetapi, ini menjauhkan untuk mengakses data tersebut, menghilangkan satu ruang belajar, ruang untuk menikmati, ruang untuk memanfaatkan data-data ini karena ketika sudah di Cibinong, tentu aksesnya sangat sulit karena ada jarak yang jauh.”
Baca juga: Melihat Kehidupan di Balik Gugusan Karst Maros
Lebih lanjut, Supriadi dari Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) mengatakan pemindahan artefak ini berkaitan dengan isu identitas, kepemilikan, dan menghilangkan konteks asli artefak.
“Contoh Maros Point ketika kita menemukan (itu di Cibinong), kita kehilangan konteks dia ditemukan di mana, kapan ditemukannya, dalam lapisan tanah seperti apa dia ditemukan, berasosiasi dengan apa, (sehingga) hanya sekedar materi yang telah diukir-ukir, dia bukan lagi artefak tapi sekedar materi yang tidak bisa memberikan informasi (konteks lokal),” kata Supriadi.
Kalau dipusatkan, kata Supriadi, makna lokal itu berubah menjadi data berlabel museum yang lebih ilmiah. Narasi masyarakat lokal dianggap sekunder, padahal itu bagian dari konteks asli artefak.
“Sebagai produk budaya, tentu ada keterikatan secara emosional. Ada hubungan emosional antara budaya material dan masyarakat. Masyarakat sekarang bukan mereka yang buat, tetapi terkait baik karena warisan leluhur nenek moyang,” terangnya.
Editor: Agus Mawan W