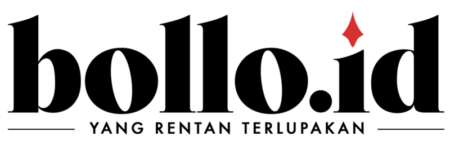Bollo.id – Di Posko SAR Desa Tompobulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Senin 19 Januari 2026, negara hadir melalui bahasa.
“Dalam kurun waktu golden time ini, kita mengharapkan ada keajaiban dan tim SAR mampu menemukan seluruh korban,” ujar Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii kepada wartawan. Ia mengatakan upaya pencarian terus dilakukan dengan memaksimalkan operasi SAR jatuhnya pesawat ATR 42-500 karena pencarian masih berada dalam masa golden time.
Kalimat itu segera dikutip media, beredar luas, dan menjadi penanda resmi tentang bagaimana publik diminta merasakan bencana: berharap, bukan bertanya.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Kata keajaiban diucapkan di tengah keterbatasan teknis dan waktu yang terus menyusut. Secara operasional, golden time merujuk pada 72 jam pertama pencarian korban, fase paling menentukan peluang hidup. Namun ketika istilah teknis itu dibungkus bahasa harapan, realitas bergeser. Yang diproduksi bukan lagi informasi tentang kemungkinan dan risiko, melainkan emosi kolektif yang dikelola. Di titik inilah bahasa negara bekerja, bukan hanya menyampaikan keadaan, tetapi mengatur bagaimana duka dialami dan dimaknai.
Peralihan dari data ke harapan ini melahirkan apa yang oleh Jean Baudrillard sebut sebagai hiperrealitas. Bukan realitas yang sekadar dilebihkan, melainkan realitas buatan yang menggantikan kenyataan itu sendiri. Dalam kondisi hiperreal, batas antara yang mungkin dan yang diinginkan menjadi kabur. Fakta kehilangan bobotnya, sementara narasi yang paling bisa diterima secara emosional justru menjadi dominan.
Ucapan “kita harap keajaiban” karena itu bukan sekadar empati personal. Ia adalah simulasi makna. Secara faktual, peluang korban selamat menurun seiring waktu dan kondisi geografis. Namun secara simbolik, harapan justru diperkuat dan disebarkan. Publik tidak dihadapkan pada angka, risiko, atau keterbatasan teknis, melainkan pada kemungkinan yang terus dibiarkan terbuka, meski hampir nihil.
Dalam situasi bencana, bahasa harapan bekerja sebagai penyangga realitas. Kematian, yang secara teknis semakin mungkin, ditunda pengakuannya melalui diksi. Selama kata keajaiban masih diucapkan, realitas belum sepenuhnya ditutup. Publik hidup di ruang antara belum ditemukannya korban dan kemungkinan korban masih hidup. Di ruang antara itulah harapan dikonsumsi.
Bahasa semacam ini tidak netral. Ia memiliki fungsi politik. Harapan menggeser fokus dari pertanyaan yang lebih berbahaya. Apa yang salah, apakah ada kelalaian, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Ketika ruang publik dipenuhi harapan, kritik struktural tertunda. Akuntabilitas menunggu giliran, sementara emosi dikelola.
Media berperan penting dalam reproduksi mekanisme ini. Dengan mengutip pernyataan pejabat tanpa membandingkannya dengan data teknis atau probabilitas faktual, media ikut membangun realitas simbolik. Yang diproduksi bukan informasi yang lengkap, melainkan emosi yang menenangkan. Dalam kondisi ini, media tidak lagi sekadar menyampaikan kenyataan, tetapi menjadi pabrik simulasi, mengulang harapan hingga terasa hadir dan nyata.
Akibatnya, publik tidak sedang menghadapi kematian, melainkan mengonsumsi harapan. Realitas keras tentang batas kemampuan manusia, kegagalan sistem, atau kemungkinan terburuk dikaburkan oleh bahasa yang lebih bisa dihidupi secara emosional. Harapan tidak lagi merepresentasikan kenyataan, tetapi menggantikan kenyataan itu sendiri.
Dalam kerangka hiperrealitas, keajaiban tidak harus benar secara faktual. Cukup efektif secara psikologis dan simbolik. Ia menenangkan kecemasan, menjaga wibawa institusi, dan menunda evaluasi. Negara hadir sebagai penutur empati, bukan sebagai subjek yang siap diuji. Selama harapan masih beredar, kegagalan belum perlu diakui.
Bencana, pada akhirnya, bukan hanya peristiwa alam atau kecelakaan teknis. Ia juga peristiwa bahasa. Di sanalah makna diproduksi, emosi dikelola, dan tanggung jawab dinegosiasikan. Ketika realitas terlalu keras untuk diterima, bahasa menawarkan jalan keluar yang lebih ramah secara emosional.
Namun jalan keluar itu memiliki harga. Kematian yang ditunda pengakuannya, kegagalan yang tidak segera dievaluasi, dan pertanyaan kritis yang digeser ke belakang. Dalam ruang hiperreal itulah, yang pertama-tama diselamatkan bukan korban, melainkan ketenangan kolektif dan bersamanya, wibawa kekuasaan.
Jumat 23 Januari, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban ke-10 kecelakaan pesawat ATR 42-500 di Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dengan temuan tersebut, seluruh awak dan penumpang pesawat ATR 42-500 dinyatakan telah ditemukan. Masa pencarian pun berakhir, bersamaan dengan berakhirnya ruang harapan yang selama berhari-hari dipertahankan melalui bahasa.
Editor: Kamsah Hasan