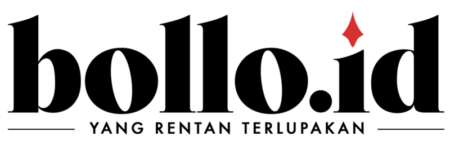Hari ini, 22 Desember 2025, linimasa kita kembali penuh ucapan: “Selamat Hari Ibu.” Ada yang mengunggah foto masa kecil, ada yang mengirim bunga, ada pula yang menuliskan terima kasih paling tulus—sering kali baru setahun sekali. Semua itu hangat, manusiawi, dan perlu. Namun, justru karena hangat itulah Hari Ibu mudah “dibekukan” menjadi seremoni.
Hari untuk memuji ibu sebagai sosok pengasuh tanpa lelah, lalu besoknya kita kembali normal. Normal versi lama. Beban pengasuhan ditumpuk di pundak perempuan, kerja-kerja domestik dianggap “kodrat” sehingga tak terlihat nilainya, dan akses kesehatan ibu masih menyisakan jurang di banyak daerah.
Padahal, Hari Ibu di Indonesia lahir bukan dari industri kartu ucapan, melainkan dari sejarah gerakan perempuan yang radikal. Itu adalah detail yang sengaja dilupakan karena mengganggu kenyamanan.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Sejarah yang Dicuri oleh Industri Bunga
Tanggal 22 Desember dipilih karena berkaitan dengan Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta (1928), sebuah pertemuan yang—dalam konteks kolonial—revolutionary. Di hadapan pemerintah Hindia Belanda yang mengawasi ketat, para perempuan pribumi yang hadir bukan membicarakan resep masakan, melainkan poligami, kawin paksa, perceraian sewenang-wenang, dan pendidikan bagi anak perempuan. Tokoh-tokoh seperti Suwarni Pringgodigdo, Soerastri Karma Trimurti, dan Roekmini menyusun strategi untuk menempatkan perempuan sebagai subjek politik, bukan objek domestik.
Negara kemudian menetapkan 22 Desember sebagai Hari Ibu melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959, yang memasukkan “Hari Ibu pada tanggal 22 Desember” sebagai salah satu hari nasional (bukan hari libur). Ini adalah pengakuan formal. Perempuan adalah motor sejarah, bukan sekadar mesin reproduksi.
Tapi apa yang tersisa dari semangat itu? Sekarang Hari Ibu lebih mirip Black Friday (hari belanja besar-besaran) versi keluarga. Momen konsumsi emosional yang mengomodifikasi rasa bersalah. Parsel mahal, makan malam mewah, dan paket “me time” menjadi simbol apresiasi—seolah cinta bisa diukur dengan transaksi. Yang hilang adalah diskusi soal keadilan struktural. Siapa yang menanggung biaya “me time” itu? Siapa yang mengurus anak saat ibu menikmati diskon spa? Jawabannya tetap, perempuan lain; nenek, pembantu, atau kakak perempuan yang juga jarang dihargai.
Kita harus jujur. Industri Hari Ibu—bunga, kartu, perhiasan—tidak membantu ibu; industri itu membantu dirinya sendiri. Keuntungan mereka bergantung pada ketidakadilan yang tetap ada. Kalau semua ibu benar-benar didukung sistem, siapa yang akan membeli “hadiah penghibur”?
Ekonomi Pengasuhan: Ketika Cinta Digolongkan sebagai Defisit
Mari kita bicara angka, karena puisi tidak membayar tagihan. ILO melaporkan perempuan di Asia-Pasifik mengerjakan empat kali lebih banyak kerja perawatan tak berbayar dibandingkan pria. Jika kita hitung secara konservatif: seorang ibu rata-rata di kota besar menghabiskan 5-7 jam sehari untuk kerja domestik dan pengasuhan. Dengan UMR Jakarta (2025: Rp 5,3 juta), nilai kerja itu adalah sekitar Rp 2,5-3 juta per bulan yang tentu saja tidak pernah dilihat sebagai “pendapatan” keluarga.
Sosiolog Prancis Louis Chauvel pernah menyebut keluarga sebagai “tempat kelas menengah menguras dirinya sendiri.” Namun di Indonesia, pengurasan itu berlangsung timpang. Ibu-ibu kelas menengah urban masih mungkin membeli me time dengan menyewa pengasuh, memesan layanan daring, atau sekadar mencuri jeda di sela rutinitas. Sebaliknya, ibu-ibu di pedalaman harus menempuh hingga 15 kilometer berjalan kaki demi pelayanan antenatal. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan perempuan berpendidikan rendah menghabiskan hampir delapan jam sehari untuk kerja rumah tangga—beban tak berbayar yang jarang dihitung sebagai kerja, apalagi dihargai sebagai kontribusi ekonomi.
Ketimpangan itu menemukan bentuk lain di dunia kerja melalui apa yang disebut Motherhood Penalty, istilah yang diperkenalkan pada 2001 dalam studi The Wage Penalty for Motherhood karya Michelle Budig dan Paula England. Konsep ini menjelaskan kerugian sistematis yang dialami perempuan setelah menjadi ibu: gaji yang stagnan atau terpangkas, akses tunjangan dan cuti yang terbatas, hingga tertutupnya peluang promosi. Akar masalahnya berkelindan dengan stereotip lama bahwa perempuan adalah pengasuh utama yang semestinya tinggal di rumah.
Tak mengherankan jika ibu yang kembali bekerja kerap dicurigai kurang kompeten atau tidak sepenuhnya berkomitmen. Studi Kelton Global pada 2018, yang dilakukan untuk Bright Horizons, mencatat 72 persen orang tua yang bekerja meyakini perempuan menerima sanksi karier karena membangun keluarga. Sesuatu yang nyaris tak dialami laki-laki. Tekanan ini bahkan menghantui perempuan sebelum menikah, memaksa mereka seolah memilih antara karier atau keluarga. Pandemi COVID-19 memperjelas jurang itu. Pada 2020, sekitar 34 persen laki-laki dengan anak menerima promosi, sementara hanya 9 persen perempuan dalam kondisi serupa yang mengalami nasib yang sama.
Ketika kita merayakan “pengorbanan” ibu, kita sebenarnya melegitimasi sistem ini. Kita mengubah eksploitasi menjadi kebajikan. Bayangkan jika kita merayakan buruh pabrik dengan mengatakan, “Terima kasih sudah mau diupah murah.” Itu bukan apresiasi; itu justifikasi ketidakadilan.
Kematian Ibu: Skandal yang Dibiarkan Berulang
WHO melaporkan pada 2023, kehamilan dan persalinan masih menjadi pertaruhan hidup bagi banyak perempuan. Lebih dari 700 perempuan meninggal akibat penyebab yang sebenarnya dapat dicegah. Artinya, hampir setiap dua menit satu ibu kehilangan nyawa. Bukan karena ketiadaan pengetahuan medis, melainkan karena akses yang tak pernah benar-benar merata.
Memang, dunia mencatat kemajuan. Sejak 2000 hingga 2023, rasio kematian ibu global turun sekitar 40 persen. Namun penurunan itu tidak dibagi secara adil. Lebih dari 90 persen kematian ibu pada 2023 terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah, tempat layanan kesehatan sering kali jauh, mahal, atau kekurangan tenaga. Padahal, satu hal sudah jelas: perawatan oleh tenaga kesehatan yang terampil sebelum, selama, dan setelah persalinan mampu menyelamatkan nyawa perempuan dan bayi baru lahir. Yang masih kurang bukanlah solusi, melainkan kemauan dan keberpihakan untuk memastikan setiap ibu bisa menjangkaunya.
Narasi Hari Ibu jarang menyentuh ini. Lebih mudah memposting “Ibu adalah pahlawan tanpa tanda jasa” daripada mendesak pemerintah daerah mengalokasikan APBD untuk fasilitas obstetri. Bahasa itu penting. Kata “pahlawan” mengimplikasikan pilihan sukarela untuk mati. Padahal, tak seorang pun memilih meninggal di persalinan. Mereka mati karena tak punya pilihan.
Cuti Melahirkan dan Kegagapan Negara
Inggris memberikan hingga 52 minggu cuti melahirkan. Swedia punya sistem “use it or lose it” untuk cuti ayah, memaksa pembagian tanggung jawab. Estonia bahkan memberikan 82 minggu dengan bayaran penuh. Di Indonesia? UU Ketenagakerjaan (sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja) memberikan 3 bulan cuti bersalin, tapi banyak perempuan takut mengambil penuh karena khawatir dianggap “tidak komitmen”.
Yang lebih memalukan adalah cuti ayah: hanya dua hari. Dua hari untuk menghadapi perubahan radikal dalam kehidupan keluarga. Ini bukan kebijakan keluarga; ini adalah lelucon. Dan lelucon ini pun tidak efektif.
Kebijakan semacam ini bukanlah kelalaian teknokratik; itu adalah kebijakan berbasis gender. Ia berasumsi perawatan adalah urusan perempuan. Dan ketika negara berasumsi demikian, pasar akan mengikuti: upah perempuan lebih rendah, karirnya terhambat, dan ia yang pertama kali di-PHK saat krisis.
Kasus di Lapangan: Dua Ibu, Dua Indonesia
Mari kita lihat dua realitas.
Ibu pertama: Ani, 35 tahun, Jakarta. Ani adalah manajer marketing di perusahaan multinasional. Ia memiliki satu anak, bayi berusia 8 bulan. Ani bisa kembali bekerja karena ia membayar pengasuh profesional Rp 5 juta per bulan. Lebih tinggi dari UMR banyak daerah. Ia merayakan Hari Ibu dengan makan malam di restoran mewah, Instagram Story yang estetik, dan satu tas branded. Ia merasa dihargai.
Tapi siapa yang benar-benal bekerja? Pengasuhnya, Mbak Sari, yang meninggalkan anaknya sendiri di desa untuk merawat anak Ani. Mbak Sari tidak mendapat cuti bersalin, tidak ada jaminan kesehatan, dan ketika sakit, ia masih harus bekerja karena “siapa lagi yang mau jagain bayi?” Hari Ibu untuk Mbak Sari adalah hari kerja biasa dengan sedikit bonus.
Ibu kedua: Yuliana, 28 tahun, Sumba. Yuliana memiliki tiga anak. Ia tidak punya akses kontrasepsi efektif karena desanya hanya ada bidan yang datang dua kali sebulan. Saat hamil anak ketiga, ia mengalami pendarahan, tapi harus menunggu suami pulang dari ladang untuk diantar ke puskesmas, 4 jam perjalanan dengan motor. Untungnya, ia selamat. Banyak yang tidak.
Hari Ibu untuk Yuliana adalah hari di mana ia berharap ada cukup beras untuk anak-anaknya. Ia tidak pernah mendengar Kongres Perempuan 1928. Ia tidak tahu 22 Desember punya makna historis. Ia hanya tahu, setiap hari adalah hari kerja, dan sakit atau sehat, ia harus berfungsi.
Inilah yang tidak diungkap oleh perayaan Hari Ibu. Ia adalah hari yang sangat berbeda untuk kelas yang sangat berbeda.
Neoliberalisme dan Romantisasi Pengorbanan
Kita hidup di era di mana perusahaan multinasional mengklaim “mendukung ibu” sambil melawan kenaikan upah minimum. Di mana platform e-commerce menggelar “Mother’s Day Sale” untuk produk rumah tangga—mengirim pesan implisit: “Ibu yang baik adalah ibu yang bisa membeli ini.”
Yang lebih sinis adalah co-optasi feminisme oleh pasar. “Girl boss” culture mengajarkan perempuan untuk “bisa memilikinya semua”: karir, keluarga, dan diri sendiri. Tapi tidak pernah dijelaskan bahwa “semua” itu berarti mengorbankan tidur, kesehatan mental, dan hak atas waktu luang. Sementara itu, pria “bisa memilikinya semua” tanpa harus menjadi “boy boss”. Mereka cukup menjadi laki-laki.
Hari Ibu yang sesungguhnya harus menolak romantisasi ini. Ia harus menjadi hari penghitungan: berapa banyak keuntungan perusahaan dihasilkan dari kerja gratis ibu? Berapa banyak pajak yang tidak dibayar karena kerja domestik tidak dianggap “ekonomi”? Dan berapa banyak nyawa yang harus hilang sebelum kita menganggap ini sebagai krisis, bukan tragedi individu?
Tiga Tuntutan yang Tidak Bisa Ditunda
Hari Ibu yang otentik harus memiliki agenda politik, bukan hanya agenda konsumsi. Ini tiga tuntutan yang harus jadi sorotan. Pertama, infrastruktur perawatan universal. Ini bukan soal “membantu ibu”, tapi soal membangun negara kesejahteraan yang layak. Setiap kecamatan harus memiliki daycare berkualitas dengan subsidi negara. Tidak “diserahkan ke swasta”, tapi dijamin sebagai hak warga seperti sekolah negeri. Dan ini harus diikuti dengan pembenahan sistem rujukan maternal yang berfungsi, termasuk ambulans desa yang siap 24 jam.
Kedua, pengakuan dan kompensasi kerja domestik. Kerja perawatan harus dihitung dalam PDB. Perempuan yang menjadi ibu rumah tangga harus mendapatkan jaminan sosial yang setara dengan pekerja formal. Bukan karena “menganggur”, tapi karena mereka melakukan pekerjaan produktif yang menopang ekonomi. Ini bisa melalui skema asuransi sosial yang di-contribute oleh suami atau negara.
Ketiga, representasi politik dan dekriminalisasi hak reproduksi. Kongres Perempuan 1928 menuntut suara dalam politik. Hari ini, kita masih berjuang untuk kuota 30 persen yang efektif. Bukan sekadar jumlah, tapi kekuatan untuk mengubah kebijakan. Dan itu harus termasuk hak atas kesehatan reproduksi lengkap, termasuk aborsi aman. Tidak ada ibu yang merdeka jika ia tidak menguasai tubuhnya sendiri.
Hadiah Terbaik adalah Kebijakan, Bukan Kue
Hadiah terbaik untuk Hari Ibu bukanlah membuat ibu merasa “paling berjasa” hari ini, lalu membiarkannya sendirian besok pagi. Hadiah terbaik adalah memastikan perempuan—para ibu dan calon ibu, juga mereka yang memilih tidak menjadi ibu—punya hak yang utuh: aman, sehat, didukung, dan dihargai sebagai manusia merdeka.
Kita bisa terus memberi mereka selimut kata-kata. Atau kita bisa memperbaiki atap yang bocor.
Pilihannya ada di tangan kita yang ironisnya, juga tangan yang pernah mereka basahi air mata kelahiran kita.
Selamat Hari Ibu, 22 Desember 2025. Rayakan dengan cinta dan dengan perubahan yang bisa diukur, bukan hanya yang bisa diunggah.