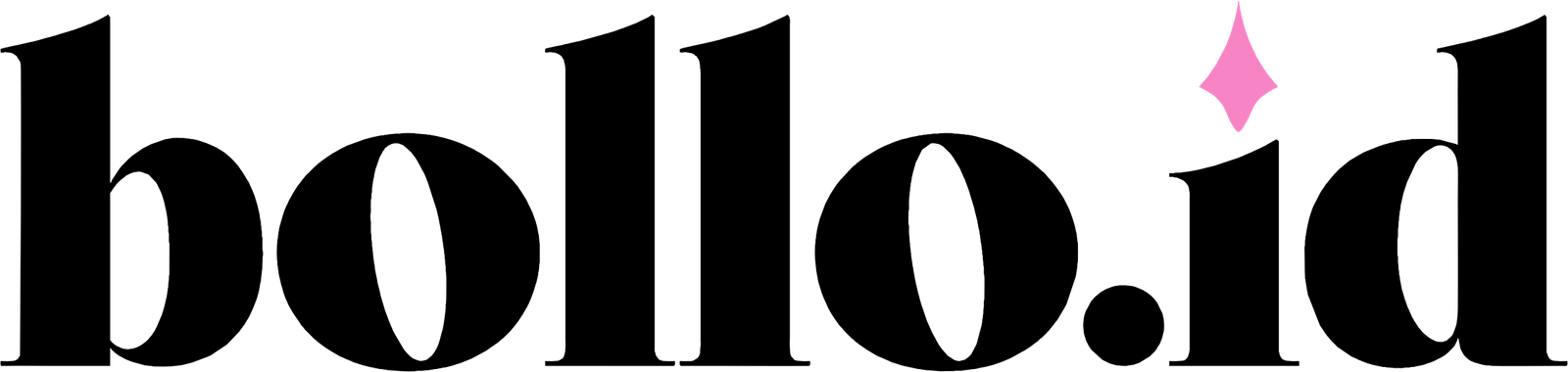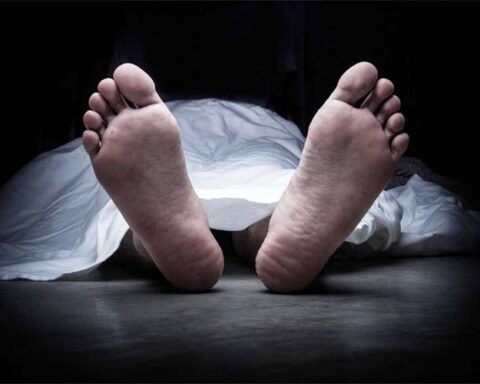Bollo.id — Tiga dekade sudah, warga di Desa Limapoccoe, merawat resistensi. Bertahan di tengah konflik tapal batas kawasan hutan, yang datang dengan serangkaian manipulasi di bawah era orde baru. Lahan yang mereka tinggali puluhan tahun saat ini menjadi pusat konflik dengan pengelola hutan pendidikan Universitas Hasanuddin (Unhas).
Sejak ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) pada saat itu pula, warga yang tinggal di sekitar lokasi tak pernah dilibatkan dalam berbagai rencana kerja pihak pengelola. Kawasan hutan berlokasi di Bengo-bengo, ditetapkan sebagai KHDTK, dan telah dijadikan hutan pendidikan Unhas sejak 31 Maret 1980.
Secara administratif hutan pendidikan ini mencakup tiga wilayah. Yakni Kecamatan Cenrana, Camba, dan Mallawa. Luasnya mencapai 1300 ha. Sejak saat itu hingga sekarang, warga sudah tidak bisa mengolah tanahnya untuk pertanian atau perkebunan lagi.
Situasi ini tentu memicu timbulnya konflik karena pengelola hutan pendidikan terkesan menutup pintu dan tak mempertimbangkan kehadiran warga yang turun temurun menempati lokasi tersebut. Jauh sebelum ditetapkan sebagai KHDTK. Pihak Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (Gakkum KLHK) memandang persoalan itu sebagai sesuatu yang urgen.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Apalagi bila dibiarkan berlarut. Informasinya, warga bahkan harus “kucing-kucingan” dengan pengelola jika hendak mengecek kondisi lahannya yang masuk dalam KHDTK. Informasi lain menyebut bahwa warga bisa tetap berkebun di dalam area hutan pendidikan. Namun mereka tak diperbolehkan menebang dan membawa kayu keluar dari kawasan.
Ada semacam aturan yang ditetapkan pengelola. Menurut Kepala Balai Gakkum KLHK Sulsel Ali Bahri diperlukan pendekatan sistemik yang harus diterapkan pihak pengelola dengan warga. Ini untuk menghindari hal-hal ilegal di dalam kawasan hutan. Ia menyarankan Unhas untuk membuat model untuk memberdayakan masyarakat.
“Ini tantangan, tapi sekaligus peluang untuk kampus, bagaimana bisa memberdayakan masyarakat dengan dibuat satu model pemberdayaan, kalau menurut saya sih dilegalisasi saja dengan kemitraan yang penting masyarakat tidak melakukan ekspansi secara terus-menerus begitu ya,” kata Ali kepada wartawan saat konferensi pers penelitian perubahan spasial akibat ekspansi Industri Sawit di Sulsel dan Sulbar oleh Forest and Society Research Group (FSRG) Fakultas Kehutanan Unhas, Rabu, 30 Juli 2025.
Menurut Ali, warga tidak perlu terus-menerus dimusuhi atau dianggap pelanggar hukum karena “kucing-kucingan”, tapi sebaiknya diajak bermitra secara legal melalui pemberdayaan. Legalisasi tersebut menurutnya menjadi kompromi.
Warga mestinya tetap diberi ruang melalui model kemitraan agar mereka bisa beraktivitas dalam batas-batas yang telah ditetapkan. Intinya jangan sampai melanggar aturan. Ketimbang membiarkan praktik diam-diam yang selama ini terjadi.
“Kalau kita tahan itu zona inti dari kawasan. Kalau dia mainnya di pinggir gitu, kenapa tidak diberdayakan, itu satu. Yang kedua kalau KHDTK mau butuh kita ya kita siap, tapi dampaknya ya begitu argo jalan kita tidak akan berhenti, begitu lampu tekan argo itu kita jalan, rompi orens,” lanjutnya.
Ia mengatakan begitu perintah atau instruksi penindakan dikeluarkan, aparat akan menjalankan tugasnya sesuai prosedur, dan warga akan menghadapi konsekuensinya, seperti dikenai sanksi hukum atau ditertibkan. Rompi orens merujuk kepada orang yang ditindak.
Ali bilang, masih ada peluang bagi warga untuk diberdayakan selama tidak mengganggu zona inti kawasan hutan tersebut. Namun, ia juga menegaskan bahwa jika aparat penegak hukum diminta turun tangan, maka proses hukum akan berjalan tanpa kompromi.
Ia juga menyebut alasan warga “kucing-kucingan” dengan pengelola. Menurutnya karena status kawasan berubah dan warga sudah terlanjur bergantung pada lahan itu. “Ini tantangan, tantangan pengolahan, karena mereka kehilangan akses (mengurus tanahnya karena dari sana penghidupannya) untuk dia, untuk anak, untuk cucu,” katanya.
“Mereka akan cenderung mencemari (tanahnya) karena dia sudah tidak punya rumah lagi karena (tanahnya) di situ sudah masuk kawasan, sehingga seperti tadi, yang terjadi adalah kucing-kucingan secara terang-terangan,” Ali menambahkan.
Bagi warga, tanah itu bukan cuma tempat tinggal dan bekerja, tapi simbol kesinambungan ekonomi dan identitas keluarga. Ia mengakui bahwa penetapan kawasan hutan menghilangkan akses hidup warga yang sudah menjadi hidup mereka secara turun-temurun di sana.
KHDTK dan Industri Sawit, Sama?
KHDTK membatasi masyarakat mengakses lahannya yang termasuk kawasan hutan pendidikan. Pembatasan tersebut juga terjadi dalam industri sawit. Keduanya sama-sama membatasi akses masyarakat atas tanah yang sebelumnya mereka kelola dengan alasan modernisasi tani.
“Sejak orde baru, pemerintah melihat bahwa daerah-daerah yang terpencil atau daerah-daerah perdesaan ini perlu dimodernkan,” kata Abd Rahman Abdullah, Peneliti FSRG, Rabu, 30 Juli 2025.
Ketika KHDTK ditetapkan, negara atau lembaga menghapus kebun warga demi proyek ilmiah. Warga dilarang mengakses lahan yang dulunya mereka kelola. Alasannya adalah demi pendidikan, konservasi, dan ilmu pengetahuan, yang dianggap lebih modern.
Jadi menurutnya, modernisasi berarti warga desa harus keluar dari lahannya sendiri. Begitu juga dengan sawit dianggap oleh negara sebagai bentuk kemajuan ekonomi pedesaan. Lahan desa juga diambil alih oleh perusahaan sawit atas nama investasi dan pembangunan.
Warga kehilangan lahan karena modernisasi mengakibatkan warga kehilangan kontrol atas ruang hidup. “Setiap kali melihat (industri sawit), selain perubahan lingkungan dan perubahan landscape, kami melihat bagaimana perubahan sosial dari adanya perubahan yang seperti itu,” ucap Rahman.
“Nah, di banyak kasus, sudah banyak literatur yang menunjukkan bahwa sawit tidak hanya mengubah landscape hutan atau landscape pertanian, tapi juga dia mengubah penghidupan masyarakat lokal,” lanjut Rahman.
Atas nama modernisasi, pemerintah membatasi akses warga desa ke lahannya sendiri, baik melalui KHDTK, maupun melalui industri sawit oleh perusahaan. Dua-duanya membuat masyarakat desa tersingkir dari tanah yang mereka kelola turun-temurun.
Editor: Sahrul Ramadan