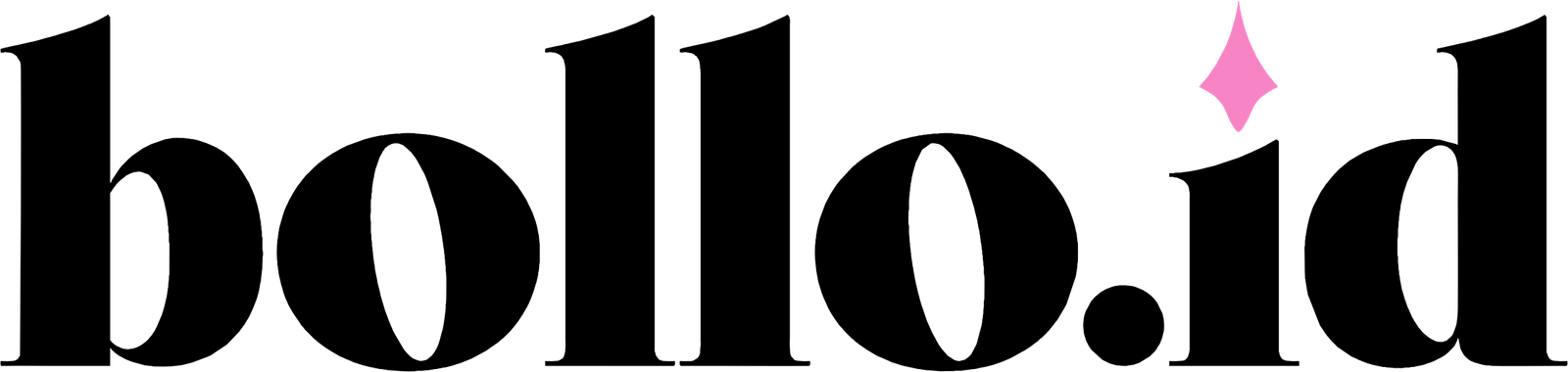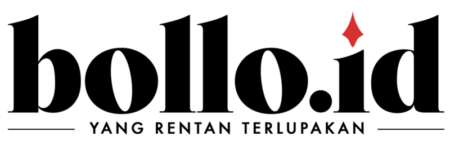Dua desa di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), Desa Limapoccoe dan Rompegading mulai sepi. Banyak warga yang tinggal di kampung itu memilih merantau karena tanah mereka, yang semula jadi sumber penghidupan diklaim Departemen Kehutanan pada masa orde baru, bermula pada tahun 1970 hingga 1972, dengan Kawasan Hutan Lindung.
Sementara, para warga yang masih bertahan di kampung itu hidup dalam ketidakpastian dan hanya menggantungkan hidup pada sisa-sisa lahan warisan yang tak masuk dalam kawasan hutan.
Sekarang, tanah yang tersedot ke dalam kawasan hutan itu jadi lokasi pusat konflik agraria antara warga dengan pengelola hutan pendidikan Universitas Hasanuddin (Unhas), setelah pemerintah menyerahkannya ke kampus merah itu.
Bollo.id menemui sejumlah warga di Desa Limapoccoe dan Rompegading, Kecamatan Cenrana, Maros pada awal Juli 2025. Untuk menggali cerita dari mereka yang hidupnya sudah tak menentu.
Dalam laporan ini, Bollo.id tidak mengungkap identitas warga yang menjadi narasumber. Semua nama narasumber telah disamarkan dengan pertimbangan keamanan.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Perampasan Lahan di Cenrana pada masa orde baru
Siang itu, Syamsuddin baru saja pulang dari kebunnya. Di pinggangnya dia ikat sebilah parang. Parang itu selalu dibawa Syamsuddin ketika berangkat ke kebun untuk memotong rumput gajah, salah satu jenis rumput yang sering digunakan sebagai pakan sapi yang dia ternak.
Syamsuddin adalah seorang bapak berusia 56 tahun. Dia menjadi salah satu yang tanahnya masuk kawasan hutan lindung di Dusun Jambua, Desa Limapoccoe, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulsel pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto di orde baru.
Cerita ini bermula dari kedatangan Departemen Kehutanan ke kampung itu. Para jawatan kehutanan itu mengecek lahan-lahan yang ditanami warga. “Untuk mengontrol supaya tidak ada maling,” kata Syamsuddin, Selasa 8 Juli 2025.
(Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Republik Indonesia ke-6 periode tahun 2009 hingga 2014, Departemen Kehutanan telah berubah jadi Kementerian Kehutanan.)

Setelah kedatangan perdana itu, Departemen Kehutanan kembali ke kampung Syamsuddin.
Hari itu, mereka tak lagi datang untuk sekedar melihat-lihat saja. Para jawatan dan anak buahnya yang tiba di lokasi menanam pohon jambu mete dan pohon pinus di lahan milik warga.
Pohon-pohon itu ditanam berselingan dengan tanaman milik warga agar dapat dijadikan contoh oleh para warga yang tinggal di kampung itu.
Tetapi, pohon yang ditanam tersebut tak bertahan lama. Para warga yang sudah menaruh curiga mencabut pohon-pohon itu setelah jawatan dan anak buahnya pulang.
“Karena nanti diambil lahan,” kata Syamsuddin. “Ada juga kesadarannya warga waktu itu.”
Tak berhasil dengan cara itu, mereka datang dengan cara yang lebih halus. Departemen Kehutanan minta warga tanam pohon akasia, jambu mete, dan pohon pinus. Tujuannya, demi penghijauan.
Agar tak dicurigai, penanaman pohon diinstruksikan langsung oleh pemerintah setempat yang menjabat saat itu, seperti kepala desa atau kepala dusun.
Kala itu, pemerintah berjanji bahwa ketika pohon-pohon yang ditanam tersebut telah tumbuh besar, maka kelak akan jadi milik warga.
Tak ada perjanjian tertulis, macam hitam di atas putih ketika penanaman pohon akasia itu dilakukan. Semua orang yang melibatkan diri percaya dengan iming-iming pemerintah kala itu.
Setiap warga yang menanam pohon di kampung itu juga diupah Rp 5 hingga Rp 25 per hari.
“Otomatis kalau orang tidak berpendidikan pasti mau,” ketus Syamsuddin. “Karena saya digaji kemudian untuk saya itu pohonnya.”
“Jadi,” Syamsuddin melanjutkan cerita. “Berlomba-lomba warga tanami akasia di lokasinya karena itu pohon akasia kalau dibikin tiang kan kuat.”
Penanaman itu digelar pada tahun 1972 silam. Saat itu Syamsuddin masih berusia 7 tahun.
Ada tujuh desa, kata Syamsuddin yang mengalami hal sama. Itu satu kecamatan saja, Cenrana. Hal serupa juga terjadi di Rompegading, desa yang berbatasan langsung dengan Desa Limapoccoe.
Jaya, seorang pria berusia 71 tahun di Rompegading. Di kampungnya, pengklaiman tanah-tanah warga bermula pada tahun 1970-an. Departemen Kehutanan datang. Minta warga tanam pohon pinus dan akasia di lahan garapan warga.
Alasannya persis sama: penghijauan. Dan warga yang melibatkan diri juga diupah per hari.
“Karena mungkin dia lihat gersang toh, bukit-bukit, rumput padang ji,” kata Jaya.
“Bibit tanamannya dari kehutanan. Kehutanan gaji masyarakat. Ada kepala-kepala balainya toh yang turun,” kata Jaya.
“Ada juga itu yang di bawahnya kepala cabang. Itu yang tanya masyarakat. Ini nanti kalau berhasil kayu, masyarakat yang akan punya,”
“Ujung-ujungnya tidak bisa ji diambil [kayu].”
Di Rompegading, warga yang tanam pohon telah berusia dewasa.
Jaya yang masih duduk di bangku kelas dua sekolah menengah pertama ketika itu hanya bertugas membuat dendengan, sebuah wadah yang terbuat dari batang bambu untuk menampung bibit tanaman.
Satu dendengan berukuran 4×1 meter, dapat menampung seribu bibit pohon. Dan dari hasil pembuatan dendengan itu, Jaya diberi upah Rp 25.
Pohon-pohon akasia ditanam di area pegunungan, tempat warga mencetak lahan demi menghasilkan nafkah keluarga. Kebun. Ladang.
Dari situ, lahan-lahan milik warga yang tadinya hanya padang-padang rumput perlahan berubah. Belakangan dia tahu statusnya pun berubah jadi hutan lindung.
“Begitu ji asal mulanya,” Jaya menunjuk arah perbukitan. “Pinus dengan akasia yang di atas itu.”
Dan ketika sebuah wilayah berubah menjadi Hutan Lindung, warga tak lagi dapat berbuat banyak. Membuka lahan untuk berkebun, menebang pohon, akan berakhir pidana bagi mereka.
Dalam sebuah penelitian, kawasan hutan tersebut kemudian jadi hutan pendidikan Universitas Hasanuddin (Unhas), sejak 31 Maret 1980, dengan luas areal 1300 ha.
Hutan pendidikan itu diperuntukan buat kegiatan praktek, penelitian, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama penelitian, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Kawasan hutan pendidikan yang dikelola Unhas ini menghampar dari Kecamatan Cenrana, Camba, hingga Mallawa–di mana desa yang ditempati Syamsuddin dan Jaya berada.
Tahun 2005, Unhas mengusulkan peningkatan status hutan ini jadi Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK), dan kemudian disetujui oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan No. 86/Menhut II/2005. Lewat penunjukan ini, hutan pendidikan meluas jadi 1.460,50 hektare.
Tahun 2017, Menteri Kehutanan resmi menetapkan hutan pendidikan Unhas jadi KHDTK, lewat surat penetapan.
Apa yang terjadi di Desa Limapoccoe dan Rompegading, Kecamatan Cenrana, Maros ini bukanlah sesuatu yang baru. Persoalan yang dihadapi para warga di kampung itu merupakan persoalan bersama bagi warga di Indonesia–terutama mereka yang hidup di antara kawasan hutan–yang telah berakar sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dan persoalan ini terjadi secara struktural.
Pembentukan hutan negara di Indonesia ini diawali dengan bagaimana negara kolonial mengekstraksi serta mengelola hutan di Jawa dengan membentuk perundang-undangan dan badan khusus kehutanan untuk menguasai dan mengelola tanah, pohon, dan tenaga kerja.
Louis Napoleon yang memerintah Belanda pada tahun 1808 hingga 1811 menunjuk Marsekal Daendels sebagai gubernur Jenderal untuk Hindia Belanda.
Di masa itu, Jenderal Daendels mengorganisasi pengelolaan hutan jati pada tahun 1808 melalui dinas kehutanan pemerintah Dients van Boswezen dengan hak-hak untuk menguasai dan mengelola tanah, pohon, dan tenaga kerja.
Beberapa elemen utama dalam sistem Daendels yaitu: Semua hutan ditetapkan sebagai lahan milik negara (landsdomein) untuk dikelola demi keuntungan negara. Kemudian, pengelolaan hutan ini diserahkan ke Dinas Kehutanan yang didirikan secara langsung untuk tujuan tersebut.
Selain itu, hutan dibagi dalam persil untuk ditebang dan ditanami kembali dengan suatu basis rotasi. Dan, akses penduduk desa pada pohon jati dilarang dan hanya pengambilan kayu mati, juga hasil-hasil hutan non kayu yang diperbolehkan.
Penguasaan ini menguat seiring Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) Hindia Belanda diterbitkan pada 1870, dan membuka jalan bagi pengklaiman sepihak lewat azas Domein verklaring, yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya secara resmi menjadi milik negara.
Tahun 1945, kepulauan ini lepas dari jajahan dan segera memproklamasikan kemerdakaan. Di awal kemerdekaan para elit-elit politik mendorong pengelola hutan di Indonesia menemukan cara-cara baru pengaturan hutan. Agar sejalan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Terutama pasal 33 yang menyatakan bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Meski telah menerbitkan UU Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960 dan menghapus Domein verklaring, jawatan kehutanan yang telah mewarisi sekitar tiga juta hektar tanah hutan tidak lekas membangun tatanan kelembagaan dan pengaturan yang baru. Pengelola hutan di jawatan kehutanan tersebut bersikukuh untuk tetap melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Boswezen pada masa kolonial dahulu.
Agenda reforma agraria yang semula dicanangkan oleh pemerintah, segera menemukan kebuntuan. Ketika Soeharto berkuasa sejak tahun 1966-1998, UUPA dan agenda reforma agraria dibekukan, dan membuka karpet merah bagi perusahaan swasta untuk menguasai lahan-lahan. Di sektor hutan, perampasan lewat kawasan hutan kian menguat. Dan inilah yang didapati oleh warga di Jambua dan Rompegading pada 1970-an. Sebuah konflik agraria yang berusia puluhan tahun.

Desa Limapoccoe dan Rompegading sebelum jadi kawasan hutan
Jauh sebelum Indonesia jadi republik, Jambua dulunya bagian sebuah kerajaan. Masyarakat setempat menyebutnya: Kerajaan Cenrana, memerintah dengan membawahi tiga wilayah, yaitu Samata, Kaluku, dan Bengo.
“Kerajaan dulu di sini, makanya orang bilang Karaeng Kaluku. Kaluku artinya gelar untuk orang yang memerintah di sini sebagai kepala kampung,” kata Agung, seorang warga di Dusun Jambua, Maros.
Pada masa penjajahan singkat Jepang, kata Agung, para warga yang tinggal di kawasan Cenrana banyak masuk ke hutan untuk mengungsi. Di dalam hutan, mereka membuka lahan dan mengolahnya jadi ladang dan tegalan. Menanam jagung dan kacang sebagai pelanjut penghidupan.
“Di situlah mereka berkebun,” terang Agung.

Tapi ketika kesuburan tanah yang diolah tersebut tak lagi cocok menumbuhkan tanaman jangka pendek–seperti jagung dan kacang, tanah itu kemudian ditanami kemiri (Aleurites moluccanus). Dua hingga tiga tahun sejak mereka mengelola tanah itu.
“Baru pindah lagi [ke lokasi lain],” kata Agung. “Dulu kan orang sistemnya berpindah-pindah [lahan huma].”
“Inilah tanda kalau ini saya yang punya tanah karena di situ tumbuh kemiri saya,” ucap Agung. “Saya yang tanam.”
Nenek Syamsuddin misalnya kata Agung, yang kerap berpindah-pindah lahan kala itu. “Ada sepuluh kali pindah [nenek Syamsuddin], jadi luas itu lahan kemirinya dulu,” kata dia.
“Ditanami kemiri atau jati merah. Selalu berpindah-pindah, makanya anak keturunannya mengatakan itu tanah punyanya nenekku.”
Tanah-tanah yang menyebar di berbagai tempat inilah yang kemudian menjadi letak konflik antara warga dengan pemerintah sampai sekarang. Pemerintah mengklaim bahwa tanah itu masuk kawasan hutan, sementara warga yang tinggal di kampung itu berpendapat lain.
“Karena ada bukti [pohon kemiri],” kata Agung.
“Kami memang tidak punya sertifikat karena sertifikat itu kan di belakang pi baru ada.”
Pada awalnya, Desa Limapoccoe dan Rompegading di Kecamatan Cenrana, Maros merupakan hamparan padang rumput. Para warga yang tinggal di tempat itu, mengolah lahan mereka jadi sawah, ladang, dan tempat memelihara hewan ternak, sapi dan kerbau.
“Iya, kayak padang-padang begini dulu sampai ke dalam sebelum penghijauan. Makanya dilepas sapi,” kata Syamsuddin.
Tapi Syamsuddin bilang, lahan-lahan milik keluarga kepala desa tidak ikut tersedot kawasan hutan. Warga tak protes karena tak ingin cari perkara, sebab keluarga kepala desa ditakuti.
“Jadi dia [mantan kepala desa] ji yang luas lahannya. Tidak ada yang masuk sampai di sini kawasan [hutan],” terangnya.
“Ini [lahan] masih sempat disertifikatkan, tapi yang sebelahnya tidak,” Syamsuddin menunjukkan lahan milik mantan kepala desa yang memerintah ketika itu.

Bollo.Id menyusuri sejumlah lokasi di Jambua untuk melihat batas-batas dan sejauh mana kawasan hutan tersebut mengubah hidup warga.
Di tempat itu, sebagian besar lahan yang dulunya dikelola warga, kini telah ditanami berbagai macam pohon, seperti pohon akasia, pinus, dan jambu mete. Lahan itu juga dipasangi pagar kawat berduri.
Di sepanjang jalan setapak yang berkelok-kelok terdapat patok semen dengan ukiran tahun 1975, sebagai tanda tapal batas kawasan hutan–yang kini bagian Hutan Pendidikan Unhas. Di antara jalan rabat beton dan lereng-lereng tempat kebun warga berjejalan.
Lahan milik nenek Syamsuddin misalnya, yang semula seluas 1 hektar di tempat itu, sebagian besar telah masuk dalam kawasan hutan.
Padahal, kata Syamsuddin, lahan peninggalan sang nenek itu rencananya akan diwariskan kepada anak dan cucunya, termasuk dirinya.
Selain pohon kemiri, tanda yang membuktikan bahwa lahan tersebut milik Syamsuddin ialah pagar yang disusun oleh sang nenek, dari ribuan bongkahan batu. Batu-batu ini, menurut Syamsuddin, jauh telah ada di lahan itu – sebelum pihak kehutanan membentangkan kawat berduri di kampung itu.
“Itu sana yang ditanami jagung. Tinggal itu,” Syamsuddin menunjuk lahan miliknya yang tersisa.
“Itu yang di bawah saya lahanku sampai ke pinggir sungai, yang ditanami jagung. Yang ada rumput gajahnya.”
Di tempat itu, Syamsuddin juga menanam jati putih (Gmelina arborea), yang kelak digunakan buat bikin rumah. Pohon jati yang ditanam neneknya tak lagi dapat dipanen, karena telah masuk kawasan hutan.

Di Rompegading, lahan yang dulunya dikelola warga juga telah diklaim pemerintah, dan masuk dalam kawasan hutan.
“Ada lahanku, di kawasan hutan sebagian,” kata Jaya.
Sebelum Departemen Kehutanan mengubah separuh Rompegading jadi hutan lindung pada tahun 1970, Jaya punya lahan di lima lokasi yang berbeda di kampung itu.
Lahan itu dulunya digunakan Jaya bersama sang ayah untuk menanam pohon kemiri dan aren (Arenga pinnata,) jenis pohon palem yang biasanya digunakan warga untuk memproduksi gula merah.
“Tiga tempat yang diambil di kawasan, dari lima tempat,” kata Jaya. “Dua sisanya di luar kawasan.”
Sejak itu, dia tak lagi pernah menggarap dan meremajakan pohon kemiri miliknya.
“Buahnya ji [kemiri] yang diambil di kawasan sekarang, tidak ditanami mi, tidak bisa mi buka [lahan] karena masuk kawasan,” ungkap Jaya.
Warga mulai merantau karena tanah mereka telah dirampas
Sore itu, saya bersama Syamsuddin berjalan menyusuri jalan setapak, melewati rumah-rumah warga di Dusun Jambua, Cenrana. Kampung itu tampak sepi, tak ada warga yang terlihat selama perjalanan.
Klaim sepihak kawasan hutan yang terjadi di Jambua telah memaksa warga meninggalkan kampung mereka. Satu persatu warga yang tinggal di kampung itu, kata Syamsuddin, memilih merantau karena tak ada lagi lahan yang dapat mereka tanami untuk jadi sumber pendapatan.
Lahan-lahan yang semula jadi tumpuan keluarga paling tidak telah masuk kawasan hutan.
“Makanya kurang warga di sini, hampir semua pergi ke Sulawesi Tenggara, ke mana mana. Pindah domisili sementara, tapi ada juga yang sudah menetap,” ungkap Syamsuddin.


Jumlah penduduk yang bermukim di Dusun Jambua, menurut Syamsuddin, pada awalnya tercatat sebanyak 400 kepala keluarga. Dan “sekarang tinggal 200 kepala keluarga,” Syamsuddin tertawa.
Di tengah kekalutan ini, warga di kampung itu menganggap bahwa merantau merupakan jalan satu-satunya demi menggapai penghidupan lebih laik.
Syamsuddin mencontohkan, rumah-rumah warga yang dibangun berjejer di sepanjang jalan tersebut berasal dari hasil jerih payah mereka selama di perantauan.
“Kalau tetap di sini apa mau diandalkan?”
“Bukan hasil di sini, kan sedikit saja sawah baru tadah hujan. Itu saja ada [hasil panen] kalau musim hujan, cuma sepuluh karung.”
Di Rompegading, banyak warga juga pilih merantau. Hutan Pendidikan telah menyempitkan lahan-lahan yang bisa digarap oleh warga.
“Banyak [merantau] sampai sekarang. Tapi bagus juga pergi merantau karena dulu pas-pasan, sekarang bisa mi meningkat pendapatannya,” kata Jaya.
Saling berbagi di ruang yang sempit
Syamsuddin yang dulunya masih anak-anak di kampung itu, kini telah menjadi seorang bapak tiga anak.
Namun lahan milik Syamsuddin telah menyempit. Sementara dia harus menghidupi anak-anak dan istrinya. Lahan peninggalan nenek Syamsuddin yang tersisa di Jambua kini 27 are, yang semula 1 hektar.
Tapi keterbatasan ini tak menghalangi Syamsuddin berbagi ke kawannya yang bernasib miris sepertinya. Di salah satu lahan miliknya, Syamsuddin mengolah lahan bergantian bersama temannya, Rasyid.
“Temanku ji itu yang tanam jagung sekarang di sawahku,” terang Syamsuddin.
Rasyid adalah seorang pria yang baru saja balik merantau dari Papua karena usahanya di sana bangkrut.
Hidup Rasyid kini bergantung pada warga yang bersedia meminjamkan lahannya untuk digarap secara bergantian di Jambua.
Untuk dapat menambal kebutuhan ekonomi keluarga, Rasyid juga bekerja serabutan, buruh harian, dan supir. Dia seperti ini karena satu hal: Karena lahan milik keluarga istrinya telah diklaim kawasan hutan pendidikan, menyisihkan sepetak kecil sawah.
“Dipinjam-pinjam saja dulu lahannya orang,” kata Rasyid yang tahun ini akan berusia 43 tahun. “Kadang ada yang sewakan [lahannya], kadang juga tidak.”
Di Rompegading, lahan yang dikelola warga juga kian menyempit.
Jaya misalnya, yang dulunya hidup dari hasil penjualan buah kemiri yang melimpah, kini sudah tak dapat lagi berharap banyak dari tanamannya.
“Buahnya ji yang diambil yang di kawasan sekarang. Tidak ditanami mi, tidak bisa mi buka karena ada kawasan,” Jaya mengeluh.
Jaya dan keluarganya berhenti menanam kemiri setidaknya sejak tahun 1985.
Di masa itu, muncul sebuah peraturan: Tentang larangan menebang pohon di dalam kawasan hutan. Karena begitulah larangan di kawasan hutan lindung. “Itu yang buat banyak masyarakat komplain, tidak mau diambil tanahnya,” ungkap Jaya.
Jaya sendiri tak protes keras, karena dia masih diperbolehkan mengambil biji-biji kemiri yang jatuh ke tanah.
Namun, bagaimana pun itu tetap saja jadi pukulan telak terhadap pendapatan ekonominya.
Ini beralasan, sebab pohon-pohon kemiri punya masa produktif dan perlu peremajaan. Tapi peremajaan berarti menentang aturan. “Tidak produksi mi sekarang itu kemiri. Agak tua mi dan tidak bisa mi diolah,” terang Jaya.
“Tidak bisa mi kemiri sekarang karena harus diremajakan, cuma tidak bisa juga diremajakan karena masuk kawasan hutan.”
Jaya bilang setiap warga yang melanggar aturan, seperti menebang pohon sudah pasti berhadapan dengan polisi hutan.
“Pasti mi datang lagi polisi hutan. Biasa dia menegur, tidak boleh menebang, tidak boleh membuka lahan,”
“Saya pernah ditegur, bilang tidak boleh ambil kayu dalam kawasan,”
“Saya bilang kayuku tonji kuambil pak.”
Dalam suatu kejadian, pernah ada warga melanggar aturan. Warga tersebut, kata Jaya, disatroni polisi hutan karena berkebun di dalam kawasan hutan.
“Ditembak di atasnya. Angin ji ditembak bukan orangnya, ditakut-takuti,” kata dia.
“Di kampung baru kejadiannya, polisi hutan yang kasih takut karena di kawasan,” sambung Jaya.
Sejak saat itu, sudah tidak ada lagi warga yang berani membuka lahan di dalam kawasan hutan.
“Selain yang na buka memang toh baru anu [masuk kawasan hutan]. Itu mami yang pinggir-pinggir kawasan [dikelola warga],”
Selain lahan yang kian menyempit, Jaya menduga, pinus yang ditanami bikin sulit persediaan air.
“Padahal sebelum ditanami pinus, masih banyak sumber-sumber air. Sekarang tidak ada mi, tambah susah kalau mau diairi sawah,” Jaya cerita.
“Musim hujan pi baru bagus.”
***
Sebelum pemerintah mengklaim lahan milik warga di Desa Limapoccoe dan Rompegading masuk dalam wilayah kawasan hutan, para warga yang tinggal di kampung itu juga hidup dari hasil penjualan ternak sapi.
Kala itu, lahan-lahan yang dikelola warga belum diklaim pemerintah, dan masuk dalam kawasan hutan seperti sekarang.
Di Rompegading, pemeliharaan sapi yang dilakukan warga sangat massif pada tahun 1968 hingga 1985.

Jaya misalnya, yang tinggal di kampung itu bahkan sempat mengembala sapi hingga 40 ekor. Dia menggunakan lahan padang di area pegunungan untuk memelihara sapi pada tahun 1970-an.
“Begitu ada pinus, susah mi perumputannya sapi,” kata Jaya.
Sedang di Limapoccoe, kata Syamsuddin, warga sengaja tidak menanam pohon-pohon di lahan padang yang tandus. Mereka sengaja karena padang itu jadi area bagus untuk memelihara sapi.
“Penghasilan utamanya kan sapi, itu yang kemudian dibelikan sawah,” terang Syamsuddin.
Tapi kondisi telah berubah, wilayah itu jadi kawasan hutan. “Sudah tidak ada lagi padang], dipagar mi semuanya,” terang Syamsuddin.
Dan jika mereka memaksakan, mereka akan berhadapan dengan teror moncong senjata dari polisi hutan.
“Sudah lama mi dilarang. Jangankan mengelola, menebang kayu sebesar betis saja itu dilarang. Apalagi yang ditanam itu [kayu], tidak bisa juga diambil,” kata Syamsuddin.
“Kapan kau ambil itu [kayu], pasti ada petugas dari polisi hutan.”
Perjuangan warga mendapatkan kembali lahan di Cenrana
Syamsuddin baru menyadari lahannya telah dirampas pemerintah saat dia remaja, dan menempuh pendidikan di sekolah menengah atas.
“Saya pelajari-pelajari, kenapa ini semakin sempit tanahku,” kata Syamsuddin.
Penguasaan kawasan hutan ini menimbulkan kemarahan warga. Mereka pun menentang.
Syamsuddin sendiri kerap kali mendapati pengelola kawasan hutan memasang patok secara diam-diam di area lahan miliknya. Dan ketika dia mendapatinya, dia akan menentang.

Dia bahkan dengan berani membuang semua patok-patok pembatas yang telah dipasang.
“Saya bilang jangan patok di situ. Bahkan dia terakhir pakai patok kayu, saya buang di sawah-sawahku itu,” kata dia.
“Saya kan bayar pajaknya, saya buang.”
Ketika pengelola datang mencari warga yang telah membuang patok-patok milik kehutanan tersebut, Syamsuddin tak pernah mundur dan berdebat dengan mereka.
“Saya bilang mana duluan, saya punya leluhur atau kehutanan?”
“Apa kehutanan ada leluhurnya di sini. Makanya dia [pengelola] tidak berani juga.” sambung Syamsuddin.
Syamsuddin pernah bertemu dengan pihak Unhas untuk membahas macam aturan-aturan yang diberlakukan secara sepihak di dalam kawasan hutan.
Hari itu mereka berdebat.
“Kalau ada itu prof dari Unhas, biasa pertanyaanku yang mana duluan warga di sini atau kehutanan?” kata Syamsuddin.
“Dia [Prof] bilang tetap tidak bisa ditebang kayu.”
“Jadi kehutanan duluan?” Syamsuddin menimpali. “Baru ini kayu yang tanam nenekku,”
“Makanya kalau ada prof di sini, saya bilang ke dia kalau sebenarnya dia pihak pelaku juga.”
“Tapi dia bilang saya kan hanya diperintahkan,” ketus Syamsuddin.
“Tapi kan kamu tahu. Coba tanyakan hatimu, ini punyanya betul kehutaan atau punyanya masyarakat.”
Dalam beberapa kesempatan, Syamsuddin juga kerap kali dipanggil pemerintah kecamatan karena dianggap melawan pemerintah.
“Saya bilang bukan saya melawan pemerintah, cuma sebagai warga negara kita punya hak. Masa kalau macam saya, itu tanah pemberian satu-satunya dari orang tua [mau diambil],” jelas Syamsuddin.
Sikap Syamsuddin yang berani melawan itu, menuai dukungan dari para warga di Dusun Jambua. “Saya lebih baik mati berdarah daripada mati kelaparan.”
Pada momentum Pemilihan Umum (Pemilu), Syamsuddin sering kali didatangi para calon yang ingin duduk di kursi jabatan. Mereka meminta dukungan suara, dan berjanji akan membantu mengembalikan tanah warga yang dirampas pemerintah.
Tapi lagi-lagi ketika mereka telah duduk di kursi jabatan, janji itu tak kunjung ditepati.
“Pak bupati itu dia pergi di sini, dengan catatan janji,” terang Syamsuddin.
Sahabat Syamsuddin, Agung juga pernah mencalonkan diri menjadi kepala desa di kampung itu.
Hanya saja, setiap kali dia maju mencalonkan diri, nasib Agung tak pernah mujur.
“Selalu nomor dua kalau maju pemilihan. Apa gunanya, tidak duduk. Lebih baik saya berhenti,” Agung tertawa.
***
Sampai hari ini, permintaan warga di Limapoccoe dan Rompegading hanya satu, yaitu: Patok pembatas kehutanan tersebut agar dimundurkan, sehingga warga tinggal di kampung itu juga memiliki lahan yang dapat mereka kelola.
Sejak 19 September 2025 Bollo.id telah menghubungi Prof. A Mujetahid, Dekan Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin untuk wawancara konflik agraria yang melibatkan kawasan hutan pendidikan dan telah mengirimkan surat permohonan wawancara secara resmi. Namun, hingga laporan ini diterbitkan, permintaan itu belum ditanggapi.
Baca juga: Doa, Dapur, Kecemasan: Merawat di Bawah Bayang Penggusuran
Editor: Agus Mawan W