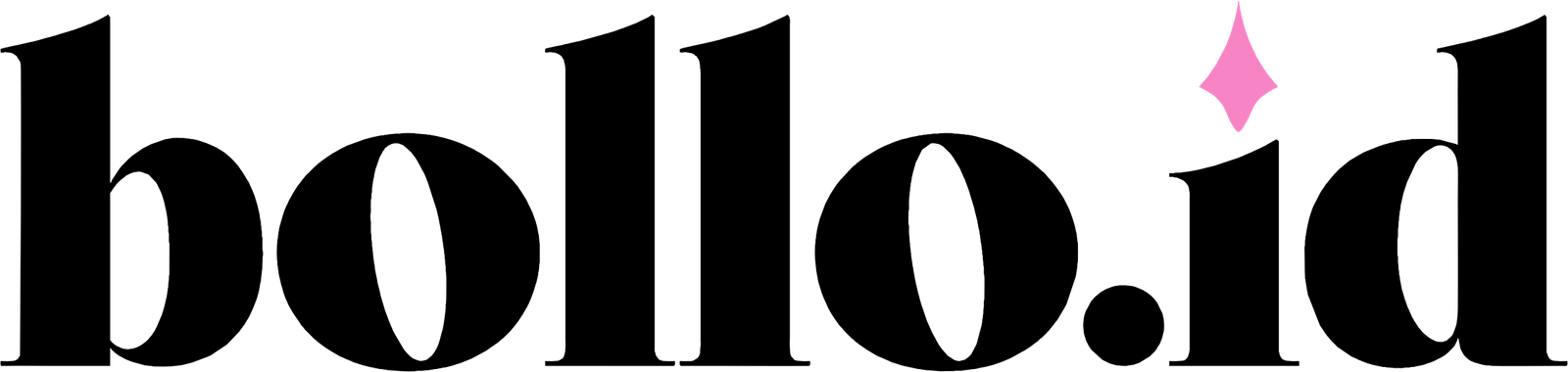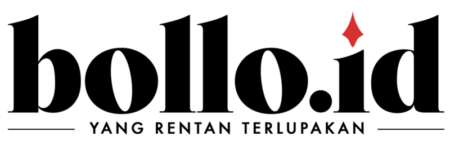Kampung Mangarabombang—dalam bahasa Makassar berarti mencium bau ombak—kini menahan napas. Di pesisir, perahu-perahu tertambat berhari-hari, menunggu gelombang yang tak pernah datang lagi.
Di beranda rumah berdinding seng, Syamsiah (48) memandangi laut yang tak lagi utuh. Di sanalah dulu ia memungut kerang tude (Bivalvia) dan kerang ekor kanjappang (Lingula sp), dengan telapak kaki terendam setengah betis. Kini, tempat itu telah berubah menjadi daratan baru. Lahan reklamasi tumbuh seperti pulau asing di hadapan kampungnya.
Dari tempat ia berdiri, tower crane Makassar New Port (MNP) menjulang, mencakar langit. Tingginya menutup cakrawala yang dulu ia hafal lebih baik daripada punggung tangannya sendiri. Cakrawala tempat ia membaca cuaca, menakar pasang, dan menggantungkan hidup.
Sekarang, yang tersisa hanya gema ingatan yang tenggelam bersama reklamasi.
“Tidak ada lagi suara ombak,” ucapnya pelan, seperti takut suaranya memecah sesuatu yang rapuh.
“Kampung ini sudah tidak sesuai namanya.”
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Rumah yang Mulai Retak
Masuk ke ruang tamunya, keterpurukan menyapa lebih cepat daripada salam. Lantai semen dipoles tipis, dingin seperti sisa malam yang tak pergi. Sofa plastik mengelupas, warnanya luntur. Dua lemari tua berdiri kurus, pintunya terbuka menampilkan ruang kosong tempat piring dan mangkuk dulu tersusun. Di sudut, bekas kulkas dan televisi tinggal jejak.
“Tinggal kenangan,” katanya. Kata-katanya jatuh pelan ke lantai, pecah tanpa suara.
Sejak reklamasi menutup laut dangkal pada 2017, pendapatan keluarga Syamsiah perlahan runtuh. Ia dan suaminya hidup dari perahu kayu kecil yang didorong arus pagi. Perahu itu terlalu tua untuk dipuji, tapi setia membawa mereka ke tempat yang selalu memberi.
Setiap ember kerang berarti sesuatu: makan malam, uang seragam sekolah, juga sedikit tabungan di bawah baju. Pendapatan harian Rp80–150 ribu bukan angka mengesankan, tapi ritme hidup yang membuat hari esok mungkin.
Laut bagi keluarga nelayan adalah rekening abadi yang tidak pernah kosong. Kini, laut itu diubah menjadi daratan buatan. Di atasnya berdiri kontainer dan crane. Di bawahnya, kerang-kerang yang menopang ekonomi perempuan terbenam tanpa tanda.
Tangkapan hilang. Peran perempuan sebagai pengolah hasil laut padam seketika. Yang runtuh bukan hanya mata pencaharian, tapi sistem penyangga kehidupan komunitas.
“Kadang saya putus asa sekali,” ucap Syamsiah.
Suara itu terlalu datar, seperti seseorang yang selesai bertengkar dengan nasib. Ia bercerita tentang anak-anak sambil mengusap lutut, seperti ada nyeri lama di sana. Satu putus sekolah di kelas dua SMP; dua tahun menunggak. Dua lainnya masih SD. Satu tinggal jauh di Kendari. Setiap kali menerima kabar dari anaknya, ia merasa bersalah.
“Kadang ku bilang, mau bunuh diri saja,” katanya.
Kata-kata itu jatuh pelan, tapi membekas lama. Ia menyebutnya tanpa drama, seolah sedang menyebut daftar belanja yang tidak terbeli: beras, minyak, gula, dan harapan.
Bagi Syamsiah, pikiran seperti itu datang bukan dalam ledakan, tetapi dalam keheningan. Saat dapur tidak berasap. Saat anaknya menangis minta jajan. Saat ia menghitung uang koin di toples plastik lalu sadar jumlahnya bahkan tak cukup untuk setengah liter bensin.
Ia tahu butuh pertolongan.
“Pusingki,” ujarnya.
“Mauji pergi RS… psikiater. Tapi tidak ada uang.”
Stres itu menumpuk tanpa suara, lalu muncul dalam retakan-retakan kecil di rumah. Pola asuh anak-anaknya kacau. Di dapur, kaleng susu kosong tergeletak di pojok, tak terbeli berbulan-bulan. Anak bungsunya, yang dulu meneguk susu formula setiap pagi, kini hanya menyusu badan. Pilihan terakhir yang mampu ia sediakan.
Setiap kali melewati pagar Pelindo, sebuah papan nama biru keperakan yang menempel di dinding pelabuhan, Syamsiah merasa dadanya mengencang. Seolah ada tangan tak terlihat yang meremas paru-parunya. Tulisan “PELINDO” itu memantul pada kaca helm pekerja, dan tembok baru. Pengingat keras tentang laut yang terhapus dari hidupnya.
“Ini mi ambil ki mata pencaharianku,” katanya dalam bahasa Makassar, setengah marah, setengah patah.
Ibu-ibu lain mengeluhkan hal yang sama. Ada rasa kehilangan mendalam. Bukan hanya kehilangan ruang hidup, tetapi juga kehilangan martabat sebagai pencari nafkah.
Hilangnya suara laut itu baginya bukan hanya perubahan alam, tetapi pengingat bahwa tempat bekerja mereka telah diambil.
Suaminya berhenti melaut. Kecelakaan kerja beberapa tahun lalu membuat tubuhnya tak lagi kuat untuk pekerjaan berat. Ia mengojek bila ada motor pinjaman. Kadang ia menyapu di pabrik jagung di depan kampung. Pendapatan tak menentu.
Syamsiah mencoba bertahan dengan menjual sop ubi. Modal ia pinjam dari tetangga atau rentenir kecil.
“Kalau ada modal buka, kalau habis tutup lagi,” katanya. Pembeli semakin sepi. Uangnya habis untuk menutup pinjaman.

Ketika Lingkungan Dirusak, Perempuan Paling Dulu Terluka
Yang Syamsiah rasakan bukan sekadar tragedi personal. Rahma Amin, akademisi Universitas Sawerigading Makassar, menyebutnya feminisasi kemiskinan. Fenomena di mana krisis lingkungan dan ekonomi menghantam perempuan lebih dulu dan lebih dalam.
Ekofeminisme, cara pandang yang melihat perempuan dan alam terikat nasib serupa, menjelaskan alam memproduksi pangan; perempuan memelihara dan memastikannya sampai ke meja. Ketika ruang hidup digusur, dampaknya menjalar ke tubuh perempuan, ke dapur yang makin sepi, hingga ke jam kerja yang memanjang tanpa upah.
Di pesisir Tallo, perempuan bukan penonton. Mereka mengolah hasil tangkapan, menjaga sirkulasi pangan, menutup celah krisis rumah tangga. Reklamasi memutus semua itu. Akses laut tertutup, perairan tercemar lumpur dan minyak. Yang runtuh bukan hanya mata pencaharian, tapi sistem penyangga kehidupan komunitas.
“Secara sosiologis, dampaknya berlapis: hilangnya ruang tangkap, hilangnya pendapatan, utang, beban kerja perempuan meningkat,” kata Rahma.
“Mereka mencari jalan lain sementara kerja domestik tetap menunggu tanpa kompromi.”

Lumpur pantai yang dulu habitat kerang, kini jadi tempat pembuangan sampah plastik dan limbah rumah tangga/Foto: Putri Ayu Lestari
Sepotong Laut yang Hilang

Makassar New Port bukan proyek kecil. Ketika Presiden Joko Widodo meresmikan tahap pertamanya pada 22 Februari 2024, ia menyebutnya lompatan besar logistik nasional. Pemerintah menggadang MNP sebagai hub logistik terbesar di Indonesia Timur. Simpul perdagangan yang bisa mengubah arah ekonomi kawasan.
Nilai investasinya Rp89,57 triliun. Tahap awal menelan 52 hektare lahan, membentang 1.280 meter di sepanjang garis pantai. Di balik angka itu, ada Kampung Tallo. Bagi pejabat hanya titik kecil di peta, tapi bagi ratusan keluarga adalah seluruh dunia.
Riset Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar (2024) mencatat reklamasi dan aktivitas konstruksi MNP memukul sedikitnya 202 keluarga nelayan perempuan di Tallo.
“Seharusnya nelayan menjadi subjek dalam pembangunan pesisir. Di Tallo, mereka bahkan tidak diberi ruang bicara,” ujar Kepala Departemen Riset WALHI Sulsel, Slamet Riadi.
Warga mengingat jelas hari-hari pertama proyek menggusur laut. Air yang dulu jernih tiba-tadi berubah cokelat pekat. Lumpur hitam muncul dari dasar perairan, bercampur tumpahan minyak kapal. Bau getir itu menempel di udara, di pakaian, di kulit anak-anak.
Habitat tude dan kanjappang pun perlahan hilang. Dua komoditas yang selama puluhan tahun menjadi tulang belakang ekonomi perempuan Tallo lenyap.
Tak ada lagi perempuan yang pulang dengan ember basah dan cerita asin. Laut terkubur. Dan bersamanya, cara hidup yang diwariskan dari buyut ke cucu.
Ekonomi Perempuan
Di pesisir Tallo, perempuan adalah denyut harian yang menggerakkan rumah-rumah kayu itu. Mereka bangun paling pagi, turun ke laut saat matahari enggan muncul, mengumpulkan kerang dari lumpur dangkal. Mereka pengatur kas rumah tangga, penjaga ritme makan.
“Ketika laut diurug, perempuan yang paling dulu jatuh miskin,” kata Slamet.
Solidaritas Perempuan Anging Mamiri mencatat sembilan kelompok nelayan perempuan kehilangan mata pencaharian tetap. Satu kelompok terdiri dari sembilan hingga sebelas orang. Pendapatan kecil tapi stabil itu hilang seperti air surut tanpa kembali.

Hasiah, 70 tahun, merasakan runtuhnya memori kolektif. Di Pancayya, gang sempit yang mengular seperti lorong ingatan, ia menghabiskan lebih dari setengah abad hidup. Ketika tiba di sini pada 1984, pesisir masih lapang. Pohon mangga menaungi halaman; suara laut menyelinap sampai ruang tamu seperti tamu lama.
Telapak kaki anak-anaknya tumbuh di atas pasir itu. Dapurnya beraroma asin dan ikan rebus.
“Dulu turun sedikit saja, pasti ada uang,” kenangnya. “Biar lima ribu, sepuluh ribu, tapi ada.”
Sekarang: kosong.
Setiap langkah di Pancayya seperti menyusuri album foto yang memudar.
Zaenab, 49 tahun, merasakan runtuhnya mobilitas sosial. Ia tak pernah membayangkan berakhir sebagai petugas kebersihan pergudangan. Dulu ia menghabiskan pagi di tepi laut, menancapkan kaki ke lumpur, memungut kerang bersama ibu-ibu kampung. Tawa mereka bersaing dengan suara ombak.
Sekarang, ia menyapu lantai semen berbau solar. Ritme pasang surut digantikan derap forklift. Ia bertahan hanya 8 bulan.
“Saya terbiasa di laut. Laut itu bukan cuma tempat cari nafkah. Itu identitas,” katanya, suara bergetar seperti tali perahu ditarik terlalu kencang.
Ketika Kehilangan Tak Bisa Ditebus
PT Pelindo IV, pengelola MNP, rutin mengumumkan program tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL). Pelatihan kewirausahaan, pemeriksaan kesehatan gratis, penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dalam rilis resmi, program itu tampil rapi. Foto seremonial, senyum pejabat, dan daftar kegiatan.
“Masyarakat sekitar bagian penting dalam setiap pembangunan,” kata Executive Director Pelindo Regional 4, Abdul Azis, di laman resmi perusahaan.

Namun, di lorong-lorong Tallo, respons warga tak seindah narasi perusahaan.
“Seperti memberi payung saat rumah sudah ambruk,” kata Zaenab.
Zaenab menggeleng mendengar daftar TJSL. Laut yang selama puluhan tahun menjadi ruang hidup kini hilang, tapi yang datang justru seminar PHBS.
“Buat apa periksa kesehatan? Kami punya KIS,” katanya. “Pelatihan usaha pun tak banyak membantu. Dikasih pelatihan, tapi tidak ada modal, tidak ada pasar. Sama saja menyuruh kami bertahan tanpa alat.”
Bagi mereka, hilangnya laut bukan sekadar kehilangan profesi. Laut adalah aset produktif intergenerasional yang menyediakan pendapatan harian—sebuah “rekening abadi” yang tak bisa diganti dengan pelatihan 3 jam dan sertifikat.
Kekecewaan itu merembet menjadi ketegangan baru. Di kampung yang dulu hidup dari ombak, kini muncul garis halus yang tak terlihat tapi terasa. Ada warga menerima profesi baru sebagai penjaga gudang hingga buruh serabutan. Ada pula yang bertahan dengan sisa tradisi meski tak ada hasil. Juga ada yang tersangkut di tengah; tak ingin meninggalkan identitas nelayan, tapi tak punya ruang kembali.
“Yang kami butuhkan bukan pelatihan,” Zaenab menegaskan, “tapi ganti rugi yang bisa menyambung hidup,” sambungnya kemudian.
Di antara laporan kinerja dan slide CSR biru-perak, kalimat itu tidak pernah muncul. Tidak ada di rilis resmi. Tidak ada di media sosial korporasi. Tapi di lorong-lorong Tallo, kalimat itulah yang paling sering terdengar. Seperti gema dari laut yang hilang.
Bollo.id telah mengajukan permintaan wawancara resmi ke Pelindo IV sejak Mei 2025. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan tertulis.
Pembangunan Datang Tanpa Ketukan
Menurut WALHI, masalah utama MNP bukan hanya dampaknya, melainkan proses yang cacat sejak awal. Lima komunitas nelayan—Tallo, Kalukubodoa, Cambayya, Buloa, dan Gusung—tidak pernah benar-benar dilibatkan dalam konsultasi publik sebagaimana diwajibkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Nelayan tidak dianggap sebagai subjek. Tiba-tiba laut mereka diurug,“ kata Slamet.
Dokumen AMDAL, kata Slamet, tidak pernah dipaparkan secara terbuka. Warga menerima perubahan tanpa informasi resmi, hanya mendengar kabar dari mulut ke mulut atau saat tembok reklamasi sudah berdiri. Banyak nelayan baru mengetahui batas proyek ketika garis beton membelah pandangan ke laut.
Slamet menyebut pola ini pemiskinan struktural. Ketika pembangunan menyingkirkan ruang hidup tanpa memberi transisi layak. Secara ekologis, reklamasi memutus daur alami bentang pantai.
Bagi warga, MNP adalah penanda bahwa pesisir berubah tanpa mereka. Tekanan ekonomi membuat banyak keluarga hidup dari utang. Perempuan yang kehilangan laut beralih menjadi buruh pabrik dengan upah harian Rp50–75 ribu. Setengah dari penghasilan dulu.
“Dulu kalau anak butuh apa-apa, tinggal turun ke laut. Sekarang semua harus dibeli, tapi uang tidak ada,” ujar Syamsiah.
Tembok yang Tak Pernah Tercatat
Dari halaman rumah Syamsiah, pelabuhan tumbuh seperti batas baru yang tak pernah mereka sepakati. Di baliknya, pemerintah bicara efisiensi logistik. Di sisi sini, warga Tallo menghitung hari tanpa laut, tanpa kerang, dan tanpa pendapatan.
Di antara dua kepentingan itu, ada ruang kosong yang tak pernah diisi; kehendak warga yang hilang dari peta pembangunan.
Kini, ketika aktivitas MNP terus berlangsung, dampak reklamasi di pesisir Tallo tak pernah sungguh usai. Tak pernah tercatat dalam dokumen proyek berapa harga yang dibayar Kampung Tallo—sebuah ruang hidup yang dihapus, persis seperti debur ombak yang menghilang dari telinga Syamsiah.
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi Bollo.id dan Project Multatuli untuk koleksi “Jendela Perempuan”.