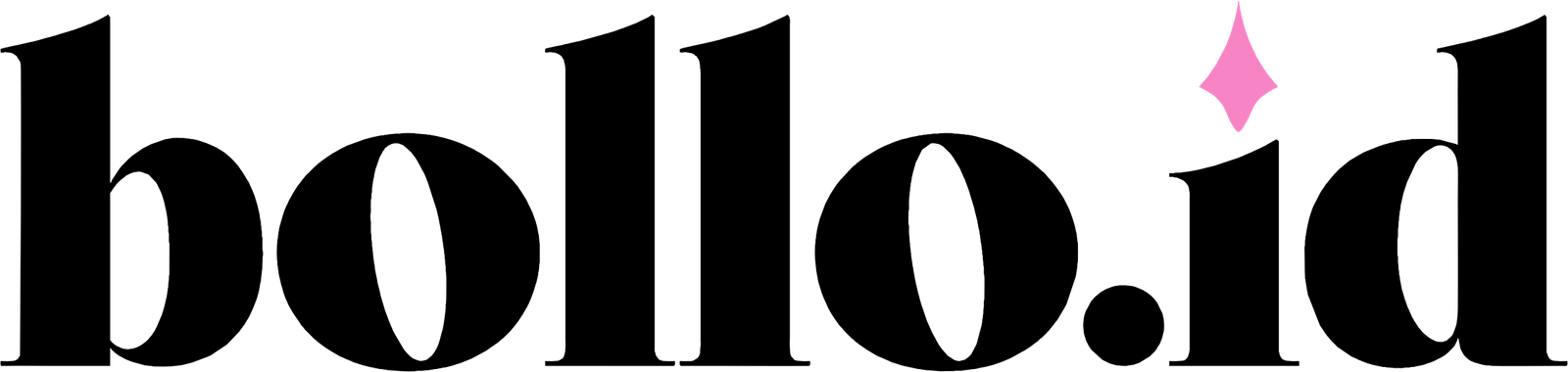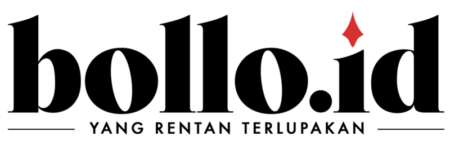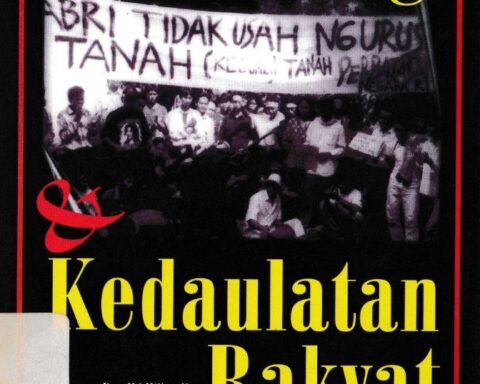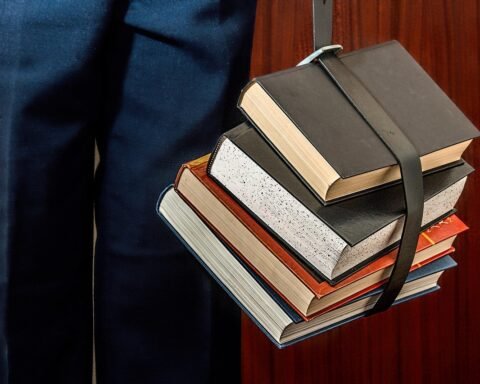Indonesia, sebagai negara yang secara harfiah dan kiasan berada di tengah Cincin Api, mengalami irama kehidupan yang dibentuk oleh aktivitas tektonik yang dinamis. Pergeseran lempeng tidak hanya membentuk bentang alam, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat membangun tanah air mereka. Di wilayah Indonesia bagian timur, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), masyarakat telah membangun pengetahuan ekologi tradisional (PET) dan keterampilan berbasis tempat untuk mengakses air tawar di daerah aliran sungai yang dinamis.
Pulau Sumba di selatan NTT adalah salah satu wilayah yang menghadapi tantangan air paling sulit untuk bertahan hidup. Berada di zona iklim muson tropis yang kering, masyarakat Sumba, khususnya kelompok etnolinguistik Kodi, telah mengembangkan sistem adaptasi yang unik untuk mengelola air. Sebuah penelitian etnografi jangka panjang yang dilakukan hampir tiga dekade (dari 1997 hingga 2025) mengungkapkan bagaimana interaksi masyarakat Kodi dengan ekosistem air tawar telah berubah seiring dengan transformasi sosio-ekonomi dan ekologi.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Karst, Muson, dan Irama Alam
Sumba adalah platform karbonat yang terangkat oleh aktivitas tektonik, menjadikannya pulau terumbu karang yang muncul di atas permukaan laut. Karakteristik geologis ini, ditambah dengan kondisi iklim muson, menciptakan dinamika hidrologi yang ekstrem. Hidrologi Sumba didominasi oleh karst, di mana air hujan yang melimpah (dengan curah hujan tahunan berkisar antara 3721 hingga 661 mm/tahun antara 1998 dan 2009) sebagian besar terakumulasi di permukaan air (sungai, mata air, doline, gua) dan air tanah (akuifer).
Irama ketersediaan air diatur oleh siklus tahunan muson dan fenomena siklus seperti ENSO (El Niño Southern Oscillation) dan Indian Ocean Dipole (IOD). Musim Hujan dipengaruhi oleh muson barat laut Asia yang basah dan hangat (April hingga November), sementara Musim Kemarau didominasi oleh muson tenggara Australia yang lebih kering dan dingin (Mei hingga Oktober).
Fluktuasi ini sangat dramatis. Sebagai contoh, pada tahun 1997, curah hujan sangat minim karena El Niño parah dan IOD positif, menyebabkan mata air dan sungai menyusut. Sebaliknya, pada tahun 2022, La Niña yang kuat dan IOD negatif membawa curah hujan yang melimpah, bahkan menyebabkan banjir di beberapa lokasi. Adaptasi tradisional masyarakat Kodi sangat bergantung pada ritme ini; air hujan adalah sumber utama selama Musim Hujan bagi sebagian besar penduduk. Mereka menangkap air yang mengalir dari atap ilalang atau logam menggunakan talang (bambu) dan menyalurkannya ke dalam tangki beton (sistem penampungan air hujan). Selain air hujan, masyarakat juga sangat bergantung pada mata air dan sungai sepanjang tahun.
Sungai yang Menghilang: Dampak Perubahan Ekologi
Bentuk daratan Sumba diatur oleh garis patahan utama yang membagi pulau menjadi sisi selatan (mengalir ke Samudra Hindia) dan sisi utara (mengalir ke Selat Sumba atau Laut Sawu). Di wilayah Kodi, tiga daerah aliran sungai yang besar di sisi selatan adalah Pola Pare, Wai Ha, dan Bondo Kodi. Sementara itu, di sisi utara, terdapat Sungai Kori.
Sungai Kori, salah satu jalur air utama di Kodi sisi utara, pernah mengalir sepanjang tahun. Namun, sungai aggraded ini (sungai yang alirannya tertimbun sedimen) sekarang menjadi kering. Berdasarkan sejarah lisan, Sungai Kori telah berhenti mengalir sepanjang tahun sebanyak tiga kali sejak era kolonial awal. Meskipun aliran tahunan sempat kembali dua kali, sejak kali ketiga (sekitar 2010 dan 2012), aliran permanen itu belum kembali. Hilangnya sumber air vital ini memaksa masyarakat yang selama ini membangun kehidupan di sekitarnya untuk mencari alternatif.
Infrastruktur Baru dan Kegagalan Non-Linear
Dalam 28 tahun terakhir, meskipun sumber air alami seperti mata air (contohnya Waikabubak dan Waikelo yang terkenal karena debit airnya yang besar, masing-masing 1000 l/s) dan air hujan tetap menjadi tumpuan utama, Kodi menyaksikan munculnya infrastruktur air buatan abad ke-21. Infrastruktur ini meliputi sumur bor, tangki air (cistern), jaringan pipa logam, keran rumah tangga, dan kios air.
Salah satu proyek besar adalah “Pro Air,” jaringan pipa dan pompa yang dirancang untuk mendistribusikan air dari sumber hulu ke hilir menggunakan gravitasi atau pompa bertenaga surya. Tujuannya adalah mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan masyarakat untuk bepergian ke sungai atau mata air.
Namun, pengalaman masyarakat dengan sistem hasil rekayasa ini bersifat nonlinear. Meskipun Pro Air memungkinkan masyarakat mengambil air di lokasi yang lebih dekat (melalui kios air pinggir jalan, keran di halaman, atau air mancur publik), banyak fasilitas ini yang gagal. Contohnya, sebuah air mancur publik yang berfungsi pada tahun 2023 sudah tidak berfungsi pada tahun 2025 karena pipa ke mata air rusak dan tidak ada dana untuk perbaikan. Pro Air bahkan dikabarkan meninggalkan proyek-proyeknya sekitar tahun 2020. Akibatnya, ketika pengembangan infrastruktur gagal, masyarakat Kodi kembali bergantung pada sumber daya alam yang terbukti secara historis (mata air, sungai, air hujan). Ketahanan adalah kualitas yang melekat pada adaptasi budaya di wilayah kering tropis Indonesia.
Stratifikasi Sosial dan Akses Air yang Tidak Merata
Perubahan hidrososial di Kodi tidak terjadi secara homogen atau seragam; dampaknya bersifat heterogen dan tidak merata. Akses terhadap air sangatlah terstratifikasi, dipengaruhi oleh status sosial, garis keturunan, pekerjaan, dan terutama lokasi tempat tinggal relatif terhadap jalan.
Masyarakat yang tinggal di sepanjang atau dekat jalan beraspal memiliki status dan hak istimewa yang lebih tinggi, memudahkan mereka mengakses layanan dan pasar. Di abad ke-21, hak istimewa ini semakin diperkuat karena infrastruktur perpipaan (seperti Pro Air) cenderung dipasang di sepanjang jalan beraspal, dan pengiriman air menggunakan truk tangki menjadi lebih mudah.
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan tren peningkatan penggunaan sumur bor. Persentase rumah tangga di Sumba Barat Daya yang mengandalkan sumur bor sebagai sumber utama meningkat dari 2,50% pada tahun 1997 menjadi 40,05% pada tahun 2024. Sementara itu, persentase yang bergantung pada air permukaan dan air hujan turun dari 82,20% menjadi 54,99% pada periode yang sama.
Namun, penelitian etnografi di tingkat desa menunjukkan gambaran yang lebih detail dan tidak seragam. Di Desa Waiholo, hampir 100% penduduk masih menggunakan air hujan, mata air, dan sungai pada tahun 2022, bahkan setelah kegagalan instalasi utilitas di sana. Sebaliknya, di Desa Wailabubur yang berdekatan, pada tahun 2022, 90% penduduk telah beralih mengakses air dari keran Pro Air atau tangki (cistern), dan infrastruktur Pro Air bertahan lebih lama di sana.
Baca juga: Air Susah di Pesisir ‘Kota Dunia’
Komodifikasi dan Ancaman Air Laut
Seiring dengan peningkatan sumur bor dan tangki, bisnis pengiriman air menggunakan truk tangki juga meningkat. Air yang dulunya merupakan sumber daya umum kini dikomodifikasi. Truk tangki mengisi air dari sumur bor dan menjualnya ke rumah tangga yang memiliki tangki. Selama Musim Kemarau, penjualan air sumur ini meningkat, karena rumah tangga yang memiliki tangki tidak dapat mengandalkan air hujan gratis. Komodifikasi ini mengubah ekonomi politik lokal.
Di masa depan, masyarakat Kodi juga menghadapi ancaman dari proses geodinamik yang baru: kenaikan permukaan air laut. Meskipun Pulau Sumba terus terangkat karena aktivitas tektonik (misalnya, laju pengangkatan di Cape Laundi berkisar 0,5 hingga 0,65 mm/tahun), laju pengangkatan historis ini lebih lambat daripada laju kenaikan permukaan air laut global. Antara tahun 1993 dan 2010, kenaikan permukaan air laut rata-rata global adalah 3,2 mm/tahun. Kenaikan permukaan laut diperkirakan akan terus melampaui laju pengangkatan pulau, yang kemungkinan akan menyebabkan masuknya air asin lebih jauh ke ekosistem air tawar pantai.
Ketahanan Budaya di Tengah Perubahan
Perubahan hidrologi dan sosial adalah komponen yang terintegrasi dalam adaptasi budaya di pulau tropis yang sangat musiman. Masyarakat Kodi bertindak sebagai agen dalam perubahan multidimensi ini; mereka beradaptasi dan bertahan. Mereka memilih apa yang harus dipertahankan, dipinjam, dan dilepaskan.
Saat mereka menemukan perubahan yang berhasil, seperti penggunaan tangki air buatan, mereka mengintegrasikan ide dan materi baru ke dalam struktur sosial dan ekologi yang ada. Fleksibilitas ini—dalam menyesuaikan diri terhadap bentuk perubahan yang fana, siklus, dan permanen—adalah mekanisme reproduksi sosial dalam budaya Kodi.
Untuk menghadapi tantangan global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 6 PBB, yaitu memastikan akses terhadap air dan sanitasi untuk semua, pemahaman mendalam tentang pengalaman lokal masyarakat seperti Kodi sangat penting. Penelitian ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat Kodi, ketahanan bukanlah sekadar kata, melainkan fondasi budaya yang memungkinkannya terus berinteraksi secara dinamis dengan sumber daya air di tanah air mereka, meskipun dihadapkan pada infrastruktur yang gagal, perubahan iklim, dan stratifikasi sosial yang semakin meningkat.
Tulisan ini dirujuk dari sebuah artikel penelitian yang tayang di Forest and Society Journal, dengan judul: Rhythms for Living: Fluid Cultural Adaptations within the Dynamic Watersheds of Eastern Indonesia. Ditulis oleh Cynthia Twyford Fowler dari Wofford College, Spartanburg, USA; Blajan Konradus dari Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia; Sri Widinugraheni dari Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia; dan Agustinus Gergorius Raja Dasion dari Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia.