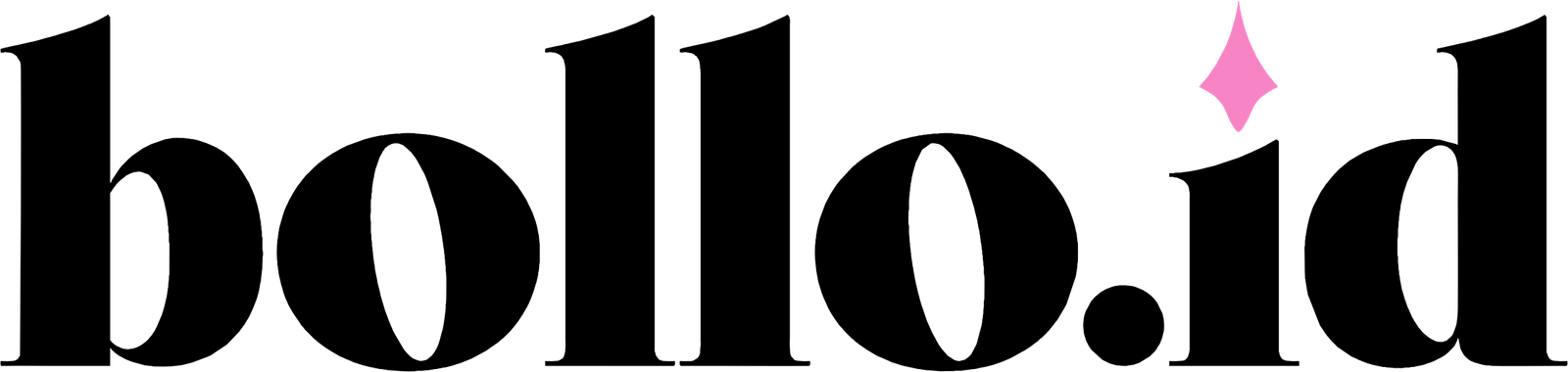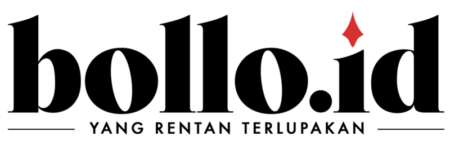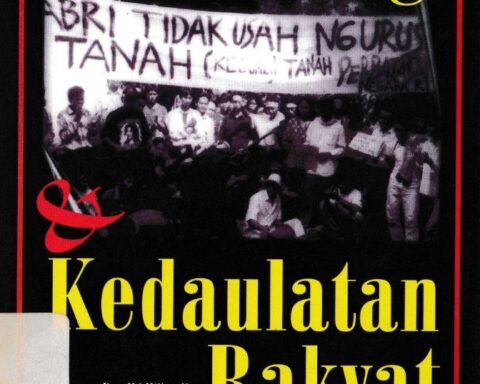Sekelompok anak kecil usia SD bermain perang-perangan. Mereka menggunakan kardus bekas yang dibentuk menyerupai pistol dan senapan. Ada juga yang memegang gulungan kardus seperti tongkat, seraya mengejar “lawannya”. “Dooooorrrr”, “majuuu”, “serbuuu”—begitu teriakan di antara mereka. Begitulah pertempuran sengit di sebuah hunian padat di kota ini pada siang itu.
Di sekitar medan “perang” bocah-bocah itu, beberapa ibu rumah tangga sedang asyik bergosip ria di depan sepetak kedai rudin di bawah rumah panggung kayu. Bocah-bocah yang “bertempur” tadi adalah anak, ponakan, atau cucu para ibu berdaster itu.
Di dalam kedai tersebut, beberapa kebutuhan rumah tangga dijajakan. Kelapa parut, beberapa jenis sayuran, garam, cabai, kunyit, jahe, bawang merah dan bawang putih, terasi, mi instan, kopi, gula pasir dan gula aren, rokok, biskuit, roti, hingga minyak goreng kemasan tersedia lengkap.
Bahkan, kedai itu juga menyajikan mi instan siram dan kopi hitam. Mi instan itu tak dimasak, hanya diseduh air panas dari termos. Begitu pula kopinya. Harganya sungguh bersahabat. Saya bersama seorang rekan sempat menyantap mi siram dan menyeruput segelas kopi susu di siang itu.
“Minyak goreng setengah liter, Indomie dua buah, rokok Surya tiga batang, catat yah,” begitu kata seorang ibu muda yang berbelanja di kedai itu kepada penjaga kedai. Rokok tiga batang itu mungkin untuk suaminya.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Rupanya kedai tersebut melayani bon. Tetangga sekitar boleh meminjam barang yang dijajakan di sana. Sang pemilik kedai—seorang ibu paruh baya—mencatat belanjaan si ibu muda tadi di sebuah buku tulis lusuh yang disimpannya di dalam laci uang.
Menurut pemilik kedai, rata-rata tetangga di sekitarnya melunasi utang kedai dalam tempo sebulan, bahkan lebih. Namun, ada juga yang melunasinya dalam seminggu atau dua minggu. “Tergantung jadwal gajian suaminya. Biasanya suaminya terima upah setiap hari Sabtu, si ibu muda tadi melunasi utangnya hari Minggu. Suaminya buruh angkat barang di sebuah toko grosir pakaian di depan sana,” kata pemilik kedai itu.
Di sela-sela itu, seorang lelaki paruh baya dengan celana pendek, topi lusuh, sandal jepit, dan jaket mirip rompi datang membeli rokok setengah bungkus, roti dua biji, serta sebotol air mineral. Lelaki berkulit legam itu membayar tunai belanjaannya. “Kalau dia, tak pernah mengutang. Dia tukang parkir di depan toko bahan bangunan dan warung kopi,” kata si pemilik kedai.
Begitulah sepenggal rekam sosial pergaulan manusia di sebuah lorong sempit, padat penghuni, di kota luas ini.
Rumah hunian di dalam lorong-lorong Kota Makassar memang nyaris tanpa spasi. Bahkan, ruang bagi setitik sinar matahari pun hampir tak tersedia. Itulah sebabnya, rumah-rumah dalam lorong umumnya tak berpagar di sisi samping dan belakang. Pagar hanya tertancap di bagian depan rumah, itu pun tak seluruhnya, sebab banyak pula rumah yang sama sekali tanpa pagar di kawasan lorong. Di satu sisi, rumah tanpa pagar melambangkan krisis lahan. Di sisi lain, fenomena itu menandakan batas-batas sosial di dalam lorong nyaris tak ada. Dengan begitu, keriuhan komunalisme dalam lorong senantiasa bergelora.
Kota Makassar memiliki luas wilayah daratan sekitar 175,77 kilometer persegi. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk kota ini tercatat sekitar 1,47 hingga 1,48 juta jiwa. Kepadatan penduduknya tergolong tinggi, mencapai lebih dari 6.000 hingga 8.400 jiwa per kilometer persegi.
Kepadatan itu sesungguhnya tersusun dari lorong-lorong. Lorong-lorong membentang di dalam ruang kota yang luas ini. Jika diasosiasikan dengan makhluk hidup, kota ini persis gurita raksasa, dan lorong-loronglah tentakelnya. Justru karena itulah kota ini disebut metropolitan. Metropolisme sebuah kota, salah satunya, dicirikan oleh kepadatan penduduk.
Sayangnya, kota beribu lorong ini tak memiliki data akurat mengenai jumlah ruas lorong di dalamnya. Untunglah ada sebuah studi yang dikemukakan Pratiwi Wulandari dalam tesisnya pada Program Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin tahun 2024. Dalam studinya berjudul Social Policy of Lorong Wisata for Improving the Welfare of the Poor in Makassar City, Pratiwi mencatat jumlah lorong di Kota Makassar sekitar 7.250.
Di 7.250 lorong itu, denyut kehidupan memiliki dinamika masing-masing. Tentu dengan gaya dan proses yang berbeda-beda. Namun, pluralitas denyut kewargaan dalam ribuan lorong tersebut memiliki satu kesamaan: keragaman proses sosial di dalam lorong adalah representasi riil kehidupan warga negara dengan beragam keterbatasan. Entah keterbatasan sosial, ekonomi, akses pembangunan, maupun keterbatasan lain yang saling bertaut.
Ibarat makhluk hidup, lorong adalah manusia yang serba terbatas.
Tetapi hunian di dalam lorong, faktanya, nyaris tanpa batas. Rumah-rumah warga umumnya berdempet tanpa spasi secenti pun. Yang berjarak di dalam lorong barangkali hanya tiang listrik.
Saat terjadi pemadaman listrik pada malam hari, warga di dalam lorong tumpah ke pinggir lorong, di sekitar drainase, seraya mengipas badan dengan potongan kardus bekas. Kipas angin tak berfungsi di dalam rumah; keluar ke pinggir lorong pun, dengan kipas manual di tangan, hawa masih terasa pengap. Artinya, sirkulasi udara di dalam lorong tak pernah benar-benar normal lantaran nihilnya spasi hunian. Bahkan, cahaya sinar matahari nyaris tak lagi memiliki tempat di dalam lorong.
“Tetapi saya senang tinggal di lorong. Setiap hari berjumpa dengan orang-orang. Ramai, tak sunyi, tak pernah lengang. Beda kalau di kompleks perumahan, lebih sering kita melihat tikus-tikus liar dibanding manusia,” kata seorang warga lorong di kota ini.
Pendapat itu masuk akal. Di kompleks perumahan, kesunyian kerap menjadi lanskap sehari-hari. Pagi masih temaram, orang-orang berangkat kerja, anak-anak menuju sekolah. Menjelang magrib, bahkan malam hari, mereka kembali. Rumah bagi warga kompleks perumahan hanyalah ruang istirahat saat malam tiba.
Itu artinya, di balik lorong yang padat sesak, interaksi sosial justru tumbuh subur. Watak kemanusiaan berlangsung aktif di kawasan lorong. Semua terkoneksi dan saling memerlukan.
Di kawasan Jalan Manuruki, Kota Makassar, dua puluh tahun lalu, lorong-lorong menjadi simpul pertemuan antara warga dan mahasiswa. Di sana, ribuan unit rumah kos terhampar. Rumah warga banyak berfungsi ganda: separuh untuk keluarga, separuh lainnya menjadi kamar kos. Kawasan itu boleh dikata sebagai “lorong mahasiswa”. Bahkan, tak sedikit dosen dan pegawai IAIN Alauddin yang bermarkas di rumah kos di kawasan tersebut.
Kebutuhan sehari-hari warga dan mahasiswa berputar di lorong-lorong. Warga menjajakan kamar kos; sebagian lainnya menjual keperluan harian bagi mahasiswa. Warung campuran, warung kue, nasi dan lauk pauk bergelora di sana. Ekonomi berputar cepat di lorong-lorong Manuruki dan sekitarnya pada masa itu.
Bahkan, air bersih pun pernah menjadi komoditas. Beberapa warga dan mahasiswa harus memesan air bersih untuk mengolah keperluan dapur. Sebuah mobil pikap tua, dengan tandon jumbo di bak belakangnya, berputar-putar menyusuri lorong menjajakan air bersih. Harganya bervariasi, tergantung volume jeriken milik konsumen.
Di sebuah lorong lain, seorang pria dewasa dengan sepeda motor tampak mendatangi rumah beberapa warga. Di motornya bergelantungan panci, wajan, baskom, gelas, dan peralatan dapur lainnya. Di lengannya tergantung sebuah tas kecil berisi buku tulis tebal. Rupanya ia pedagang alat-alat dapur dengan sistem kredit. Dua kali seminggu ia datang menagih pelanggannya, yang sebagian besar ibu rumah tangga di lorong.
Di hari lain, seorang pria dewasa dengan sepeda motor datang menagih beberapa warga yang meminjam uang. Ia seorang rentenir yang berkeliling lorong setiap hari. Bunganya tak main-main: 15 hingga 20 persen dari jumlah dana yang dipinjam. Syaratnya sederhana, hanya fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.
Seorang kakek yang bekerja sebagai tukang bangunan setiap sore berurusan dengan sang rentenir itu. Ia mengambil kredit untuk mengganti giginya dengan gigi palsu. Entah berapa tahun lamanya sang kakek harus melunasi cicilan gigi palsu tersebut.
Di ruang lorong lain, seorang ibu tua setiap pagi beranjak menuju sebuah kompleks perumahan yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Para pelanggannya berdomisili di kompleks itu. Si ibu tua bekerja serabutan sebagai tukang cuci dan pembersih rumah. Mencuci pakaian, menyetrika, serta menyapu dan mengepel lantai menjadi pekerjaan tetapnya.
Karena pelanggannya hanya satu, dua, atau tiga rumah, saban hari pekerjaannya rampung sekitar pukul 14.00 siang, bahkan kadang menjelang Asar.
Padahal, di zaman ini jasa cuci pakaian atau laundry telah menjamur. Namun pelanggan si ibu tua enggan memanfaatkannya. Ia mengaku telah puluhan tahun berprofesi demikian. Pelanggannya setia, dan ia pun lebih setia—demi kepulan asap di dapur, demi membantu suaminya mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kebetulan, sang suami bekerja sebagai sopir mobil dengan upah yang tak seberapa.
***
Lorong-lorong di Kota Makassar tak pernah sunyi, bahkan ramai dua puluh empat jam. Kompleksitas di dalam lorong kerap memantik cekcok asmara rumah tangga. Sepasang suami-istri kadang bertengkar gegara perselingkuhan. Teriakan keras atau bunyi dinding tripleks yang ditinju sering memekikkan telinga tetangga sebelah.
Bahkan, bentrok massa kerap meletus di kawasan lorong tanpa diketahui musabab yang jelas. Lorong-lorong di bagian utara kota ini acap kali menjadi arena perang antarkelompok massa tanpa akar persoalan yang terang. Mereka umumnya terdiri dari anak-anak sekolah, remaja, hingga pria dewasa. Perang di lorong sempit itu bisa meletus kapan saja. Entah siang, malam, atau dini hari dengan pemicu yang kerap remeh-temeh.
Seorang rekan yang berdomisili di kawasan Tinumbu menuturkan, pemicu perang sering bermula dari hal-hal kecil. Pertengkaran antar anak-anak tiba-tiba berubah menjadi perang antarwarga dewasa. “Sejak dulu selalu begitu,” kata rekan itu. Maka perang di sana pun berkelanjutan, seolah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Perang yang tak berkesudahan itu kian ganas. Bukan hanya busur panah atau senjata tajam yang digunakan. Di sana, bom molotov mulai menjadi bagian dari repertoar kekerasan lorong. Pada 24 September lalu, enam rumah warga terbakar setelah dilempari bom molotov.
Begitulah perang lorong di kawasan utara kota ini. Bila gemuruh bentrokan tak terdengar, bukan pertanda gencatan senjata telah tercapai. Ia hanya rehat sejenak. Di sana, perang lorong bergerak seperti spiral atau laksana sinetron bersambung. Selalu berulang, selalu menemukan episode barunya sendiri.
Lorong Politik
Ketika musim pemilu dan pilkada tiba, lorong-lorong di Kota Makassar pun tersasar. Pekerja politik masuk lorong silih berganti, persis antrean di sebuah WC umum. Warga lorong disambangi. Mereka datang tanpa diundang.
Mula-mula, para pekerja politik itu, entah tim sukses, calon legislatif, atau calon wali kota, datang membawa harapan dan menabur janji kesejahteraan. Mereka menyatakan iba. Rasa kemanusiaan disebut sebagai motivasi masuk lorong. Kadang-kadang, di antara mereka lalu menyelipkan kartu nama, stiker, atau sembako. Sembako yang daya tahannya tak lebih dari sepekan.
Warga lorong tentulah antusias. Mereka tak mempersoalkan itu. Mereka terbuka menerima siapa saja pekerja politik yang datang mengetuk pintu-pintu lapuk rumah mereka. Semua diterima. Bukan karena mereka benar-benar memahami apa yang disampaikan para pekerja politik itu.
Tetapi warga lorong tak bodoh. Mereka tahu maksud dan tujuan para pekerja politik masuk lorong. Mereka paham betul: pekerja politik itu hendak dipilih. Mereka tahu, berdasarkan pengalaman, bahwa para pekerja politik itu hanya masuk lorong sekali dalam lima tahun. Usai terpilih, mereka menghilang. Saat menjabat, mereka terbang ke sana-kemari di luar area lorong. Maka siasat pun digencarkan.
Siasat utamanya sederhana: siapa pun pekerja politik yang bertandang, semua diterima—termasuk segala pemberiannya, entah sembako atau amplop. Namun, dalam satu rumpun kartu keluarga, pilihan di bilik suara tak pernah tunggal. Siasat itu dijalankan dengan kesadaran penuh bahwa selepas terpilih, para pekerja politik itu akan lenyap tanpa jejak. Kaki mereka tak kunjung bertapak lagi di setapak-setapak lorong.
Warga lorong sadar, siapa pun yang terpilih, lorong tetap bolong dari pembangunan. Mereka tahu kesejahteraan hidup mereka tak memiliki hubungan langsung dengan siapa yang mereka coblos. Mereka paham, citra negatif lorong sebagai hunian kumuh, jorok, dan akrab dengan kekerasan tak pernah sungguh-sungguh berubah.
Mereka juga tahu, pemerintah dan wakil rakyat yang terpilih tak pernah benar-benar serius merancang program khusus untuk transformasi lorong. Akibatnya, lorong dibiarkan tetap kumuh, jorok, dan identik dengan rasa aman yang tak kunjung normal. Lorong hampir selalu terabaikan dari arus utama pembangunan kota.
Politik lorong berlanjut dalam Pilkada Wali Kota Makassar periode 2013–2018. Danny Pomanto yang berpasangan dengan Syamsurijal “Deng Ical” mengangkat “lorong” sebagai wacana politik. Mereka mendefinisikan diri dalam pertarungan pilkada saat itu sebagai “anak lorongnya Makassar”. Politik lorong pun berputar kencang. Mereka sukses memanen suara dan memenangkan pilkada pada masa itu.
Tak berhenti di situ, politik lorong berlanjut melalui pemilihan ketua RT/RW yang dirintis Wali Kota Makassar Danny Pomanto pada periode pertamanya memimpin Kota Daeng (2013–2018). Untuk pertama kalinya di Makassar, ketua RT dan RW dipilih langsung oleh warga. Para kandidat pun memasang baliho-baliho mini di lorong daerah pemilihannya masing-masing. Foto dan tagline terpampang di baliho itu, layaknya calon legislatif.
Ketua RT dan RW yang terpilih kemudian ditugaskan mengelola wilayahnya agar tetap rukun sekaligus mendukung program Pemerintah Kota Makassar. Para ketua RT/RW itu pun diganjar honor bulanan. Bahkan, pada satu masa, mereka difasilitasi alat komunikasi oleh Wali Kota Danny Pomanto.
Pemilihan langsung ketua RT/RW tersebut konon dilapisi argumen teoretis: demokrasi harus dipraktikkan hingga lapis paling bawah. Namun, perlahan, demokrasi pemilihan RT/RW itu ditengarai beraroma politis. Program tersebut dianggap sebagai siasat Danny menghimpun kekuatan politik di lapis akar rumput untuk menopang periode keduanya.
***
Meski demikian, sejumlah program Pemerintah Kota Makassar pada masa itu memang didorong masuk ke lorong-lorong. Para ketua RT/RW berperan aktif menggerakkan program-program tersebut. Optimisme pembangunan lorong sempat tumbuh. Dalam dua periode kepemimpinan Danny, semangat transformatif lorong pernah disiarkan, dari program bersih-bersih lorong hingga gagasan “Lorong Wisata”.
Drainase lorong dibersihkan oleh Pemkot Makassar. Miliaran rupiah anggaran digelontorkan untuk mengangkat sedimentasi yang menumpuk bertahun-tahun. Drainase-drainase itu kemudian ditutup dengan cor beton.
Gerakan bersih-bersih lorong berlanjut. Bank sampah dirintis di dalam lorong meski perkembangannya cenderung stagnan. Tenaga pengangkut sampah disebar ke lorong-lorong. Warga diseru mengemas sampah dalam kantong plastik lalu meletakkannya di depan rumah masing-masing. Setiap hari, sampah pun tampak berjejer di lorong, laksana barisan serdadu. Pada jam-jam tertentu, petugas kebersihan yang dikoordinasikan pemerintah kelurahan datang mengangkutnya.
Lorong-lorong pun dibuat terang benderang. Lampu-lampu bertiang oranye dipasang di sepanjang lorong. Pada malam hari, lorong tak lagi temaram. Gulita perlahan disingkirkan oleh cahaya lampu.
Program “Lorong Wisata” juga digagas Danny dalam masa pemerintahannya. Tujuannya membangun ekonomi lokal, ketahanan pangan, dan pariwisata berbasis masyarakat. Lorong-lorong hendak disulap menjadi destinasi dengan potensi UMKM, pertanian skala kecil—sayur, ikan, maggot—serta seni seperti mural dan bonsai. Fasilitas pendukung seperti Wi-Fi dan CCTV turut dijanjikan, demi menciptakan ruang hidup yang lebih produktif, mempererat solidaritas warga, sekaligus memberi manfaat ekonomi langsung bagi penduduk setempat.
Lorong Wisata diposisikan sebagai inovasi Pemerintah Kota Makassar: mengubah gang sempit menjadi pusat ekonomi mikro, wisata mini, dan ruang sosial yang produktif—bukan sekadar objek wisata biasa. Maka pengecatan lorong pun digalakkan. Tembok-tembok kusam dicat dengan bantuan pemerintah kota. Menyusul kemudian lomba-lomba Lorong Wisata.
Sejumlah lorong merespons program itu. Lahan-lahan kosong di kawasan lorong dimanfaatkan. Di kawasan Cokunuri, Kelurahan Gunung Sari, misalnya, RT dan RW berpadu mengembangkan budi daya sayur alami dengan sistem hidroponik. Bibit dan pupuk kompos diperoleh dari bantuan Pemerintah Kota Makassar melalui pemerintah kelurahan setempat.
Namun, sayangnya, program ini tak berjalan maksimal. Wisata lorong yang diimpikan tak pernah benar-benar terwujud sebagaimana yang dijanjikan. Entah apa saja kendalanya.
Sebagian kalangan justru memandang program Lorong Wisata sebagai “pelarian” Pemerintah Kota Makassar atas kegagalannya memenuhi ketentuan ruang terbuka hijau (RTH). Aturan mengenai RTH termaktub dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mewajibkan minimal 30 persen ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Porsi itu terdiri atas 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat, demi menjamin kualitas lingkungan hidup, keseimbangan ekologis, serta keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Kota Makassar memiliki luas sekitar 175,8 kilometer persegi. Dengan demikian, target luasan RTH yang wajib dipenuhi adalah 30 persen dari total wilayah tersebut, atau sekitar 5.273 hektare—setara dengan 52,73 kilometer persegi. Hingga dua periode kepemimpinannya, luasan RTH yang berhasil ditorehkan Danny Pomanto baru sekitar 12,42 persen. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 18 persen RTH di Kota Makassar.
Untuk menutup defisit ruang hijau itu, Pemerintah Kota Makassar kemudian mencanangkan lorong sebagai arena hijau. Warga lorong diseru menanam bunga, sayuran, cabai, dan tanaman lainnya. Argumen pemerintah kala itu, selain untuk menjawab krisis ruang hijau, juga agar warga tak lagi merogoh kocek untuk membeli cabai di pasar. Namun pertanyaannya sederhana: bagaimana warga menjalankan anjuran itu di tengah lorong yang sempit? Jangankan menaruh pot tanaman, ruang untuk meletakkan sandal pun nyaris tak tersedia.
***
Begitulah Makassar. Kota besar yang megah ini sesungguhnya tak layak disebut metropolitan di kawasan timur Indonesia jika tak berlorong. Di balik gemerlapnya, paru-paru kota ini adalah lorong. Di sanalah denyut kehidupan kota berdetak dengan irama riuh—tentang kerja, utang, harapan, konflik, dan siasat bertahan hidup.
Lorong menegaskan dirinya sebagai salah satu titik paling jujur dari eksistensi negara. Mengintip lorong berarti menyimak negara dalam wujud paling telanjang. Maka, memarginalisasi lorong dalam proses pembangunan bukan sekadar kelalaian kebijakan, melainkan cara negara menanam penyakit bagi tubuhnya sendiri.
Editor: Kamsah Hasan