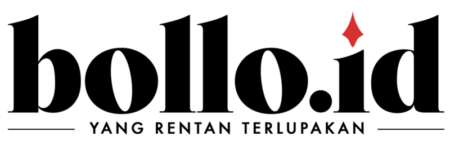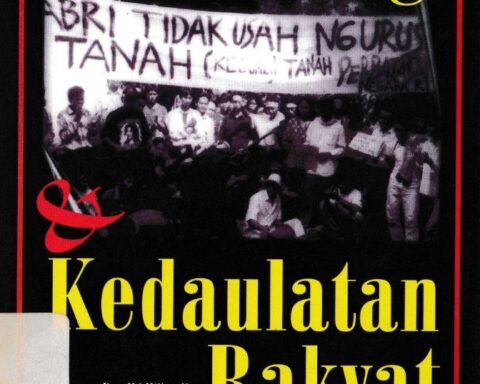Secara sederhana, film ini mengisahkan Biba yang berprofesi sebagai guru berupah minim bersama Rizky sebagai videografer pernikahan yang berusaha bangkit, untuk menggelar pesta pernikahannya yang sederhana. Namun, mimpi tersebut terhalang oleh keluarga Biba, dalam hal ini Puang Ngugi sebagai tantenya yang sadar akan status sosial. Demi mengenyangkan gengsi sosial dan harapannya untuk meraup uang passolo (uang sumbangan kepada pelaksana pernikahan), keluarga Biba yang divokalkan oleh Puang Ngugi bersikeras untuk mengadakan pesta yang megah nan meriah.
Di tengah persiapan pernikahannya, Biba dan Rizky terperangkap dalam lingkaran keruwetan dan kekonyolan. Mulai dari daftar tamu yang kian ditambah oleh Puang Ngugi bersama dengan suaminya, Puang Lallo. Belum lagi desakan dekorasi yang megah hingga panggung elekton dua malam. Sehingga, impian untuk pernikahan sederhananya semakin jauh dari mata. Dengan ini, baik Biba, Rizky, maupun Ibu Biba, berhasil dibuat pasif oleh Puang Ngugi yang aktif merencanakan misi gengsinya di hadapan masyarakat.
Sebagai karya seni yang menggambarkan realitas, film Uang Passolo mengingatkan saya secara pribadi dan kita pada umumnya, bahwa ada satu kenyataan yang sering kita alami, tetapi jarang kita refleksikan, yaitu pernikahan bukan sekadar peristiwa personal. Ia adalah peristiwa sosial, bahkan politik, dalam arti paling sehari-hari. Pernikahan menjadi panggung di mana relasi kuasa, jasa, gengsi, dan utang budi dipertontonkan secara sah di hadapan publik.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Dalam konteks masyarakat Bugis, Susan Bolyard Millar dalam bukunya Bugis Weddings: Ritual of Social Location in Modern Indonesia mengungkapkan bahwa pernikahan kerap berfungsi sebagai arena temporer di mana hierarki sosial dan jaringan kekerabatan diubah ketika masih terbelakang atau dipertegas ketika sudah mapan. Hal tersebut disebabkan karena memang hubungan sosial antar-orang Bugis kerap diwarnai dengan nuansa kompetitif dan hierarkis. Dapat dilihat dari fenomena tarif ‘uang panai’ atau uang belanja yang diklasifikasikan, tokoh-tokoh penting dicantumkan di undangan, hingga kostum pengantin yang dimegahkan.
Lanjut Millar, dalam masyarakat ini, di satu sisi, individu saling bersaing untuk memperoleh status capaian yang lebih tinggi, dan pernikahan adalah ‘lahan basah’ untuk memulai konstruk sosial secara halus. Tentu dalam fenomena ini, orang tua atau ‘tau matoa’ berperan penting dalam menentukan arah kedudukan sosial yang akan ia dapatkan setelah menikahkan buah hatinya. Namun, film yang disutradarai oleh Andi Burhamzah tersebut, justru menyorot figur lain yang sering menemani orang tua calon mempelai di tengah hiruk-pikuk persiapan hingga acara selesai. Ia adalah tante atau bibi. Sosok yang tampak ‘hanya membantu’ secara sukarela, tetapi sesungguhnya menyimpan kuasa atau otoritas sosial yang dampaknya tidak kecil.
Sebagai upaya membedah keresahan sebagai penulis, saya menganalisis mekanisme dimensi politik yang terjadi dalam pernikahan Bugis menggunakan kerangka yang dicetuskan Pierre Bourdieu. Konsep tersebut mencakup habitus, arena, dan modal. Ketiga hal itu menjadi jalan untuk memungkinkan kita membaca relasi ’habitus’ dalam sebuah ‘arena’ bersama dengan ‘modal-modal’ yang mengitarinya.
Secara sederhana, ‘habitus’ (internal subjek) merupakan sebuah kondisi, sikap, cara, dan gaya subjek menghadirkan dirinya yang bekerja di bawah kesadaran. Adapun ‘arena’ (eksternal subjek) dapat berupa keluarga, masyarakat, atau tempat yang menjadi lokus praktik sebuah ‘habitus’ dengan kode atau aturan tertentu yang memungkinkan adanya perebutan posisi. Sehingga, menurut Bourdieu, setiap arena atau masyarakat diwarnai oleh dominasi, ada yang menguasai dan dikuasai. Sedangkan ‘modal’ (pelicin/senjata) merupakan konsentrasi kekuatan yang beroperasi dalam ‘arena’ agar mampu terus bertahan di dalamnya.
Dalam konteks pernikahan Biba dan Rizky, dapat diklasifikasikan menjadi dua arena, besar dan kecil. Pernikahan, menjadi ‘arena besar’ tempat berbagai aktor atau ‘habitus’ dalam hal ini Puang Ngugi untuk bertemu, bernegosiasi, dan berkompetisi. Sejak awal, ia secara sadar merencanakan agar pernikahan keponakannya itu, sebisa mungkin dapat dihadiri oleh banyak orang, termasuk keluarga ‘lain kali’ yang diasosiasikan sebagai orang luar bahkan tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali. Hal tersebut diupayakan agar yang diundang memiliki tanggung jawab moral/siri’ untuk memenuhi undangan tersebut dengan uang passolo’.
‘Modal’ di sini tidak hanya berupa uang, tetapi juga jaringan sosial, reputasi, dan legitimasi moral. Tampak Puang Ngugi saat menjelang pernikahan Biba, ia begitu rajin mendatangi beberapa pesta pernikahan. Saat tiba di acara tersebut, dengan mulut yang dimonyongkan serta gestur menampakkan amplop kepada pelaksana acara, ia secara tersirat mengucapkan “jangan lupa datang ke acaraku beserta uang passolo’mu, ya!” Seketika, Puang Ngugi menaruh beban moral kepada sang pemilik acara untuk datang ke acara pernikahan Biba yang sebentar lagi digelar.
Kemudian ‘arena kecil’ yang sebenarnya dampaknya besar, tampak jelas melalui praktik uang passolo’ itu sendiri. Ia adalah modal ekonomi yang langsung dikonversi menjadi modal sosial (ikatan timbal balik) secara tidak langsung, sekalipun esensi uang passolo’ itu sebenarnya hanya sekadar membantu sang tuan rumah dalam menutupi beban biaya yang telah digunakan selama prosesi pernikahan. Namun, semakin hari, esensi tersebut mengeras menjadi modal simbolik berupa ‘utang budi’ dan ‘kehormatan’ atau siri’. Tentu, tidak ada satupun orang Bugis yang ingin dilecehkan siri’-nya.
Secara historis dan normatif, uang passolo’ berangkat dari semangat solidaritas, membantu sesama. Namun, sebagaimana yang dihadapkan film tersebut, praktik ini tidak berhenti pada satu peristiwa. Uang passolo’ bekerja dalam logika memori sosial. Dapat dilihat ketika Puang Ngugi bersama Puang Lallo mencatat nominal uang yang disumbangkan oleh para tamu undangan. Selain itu, peristiwanya selalu diingat dan kewajibannya diwariskan. Ketika pihak yang memberi sumbangan suatu hari menggelar acara, penerima sebelumnya secara moral ‘fardu ‘ain’ atau wajib personal untuk hadir dan memberi sumbangan dengan nominal yang setara atau lebih. Memberi di bawah nominal sebelumnya dipandang tidak etis dan mencederai hubungan sosial.
Dalam kerangka Bourdieu, inilah proses konversi modal yang terus berulang. Uang tidak lagi sekadar alat bantu, tetapi menjadi instrumen pembentuk relasi kuasa. Solidaritas perlahan berubah menjadi struktur kewajiban yang mengikat. Lalu, mengapa dengan tante dalam hal ini Puang Ngugi menempati posisi strategis dalam struktur kuasa atas pernikahan keponakannya? Pertanyaan inilah yang muncul dan diangkat secara implisit dalam film.
Jawabannya terletak pada posisi sosial yang unik. Puang Ngugi berada di antara bukan orang tua kandung, tetapi juga bukan orang luar. Ia sering kali hadir dalam momen-momen krusial kehidupan keluarga, terutama ketika orang tua khususnya ayah Biba meninggal dunia. Dalam film tersebut, relasi antara Biba dan Puang Ngugi memperlihatkan bagaimana bantuan material dan emosional di masa lalu berubah menjadi legitimasi moral di masa kini.
Dengan kontribusi besar dalam acara pernikahan, Puang Ngugi sedang mengaktifkan dan mempertegas modal simbolik yang ia miliki. Ia tidak perlu menyatakan klaim secara terbuka. Jasa historisnya sudah cukup menjadi dasar otoritas. Dalam bahasa Bourdieu, ini adalah bentuk dominasi simbolik, sebuah kuasa yang bekerja tanpa paksaan, karena diterima sebagai sesuatu yang wajar.
Yang membuat relasi kuasa ini jarang dipertanyakan adalah habitus. Dalam masyarakat pada umumnya, termasuk di Bugis, membantu keluarga adalah kewajiban moral dan membalas jasa adalah kehormatan. Habitus ini membentuk cara berpikir dan merasa, sehingga intervensi tante dalam pernikahan keponakan tidak dipandang sebagai dominasi, melainkan sebagai bentuk kepedulian. Akibatnya, keponakan tidak pernah benar-benar dipaksa, tetapi juga tidak memiliki ruang yang luas untuk menolak. Kuasa bekerja secara halus, melalui norma, rasa sungkan, dan ingatan kolektif tentang jasa. Dan Biba merasakan hal tersebut secara bertubi-tubi.
Melalui Uang Passolo’, kita diajak melihat bahwa pernikahan adalah titik temu antara cinta, solidaritas, dan politik keluarga. Tante muncul sebagai figur penting bukan karena ambisi semata, tetapi karena struktur sosial memberinya ruang dan legitimasi. Esai ini tidak bermaksud menghakimi praktik uang passolo’ atau peran tante sebagai sesuatu yang sepenuhnya problematis. Namun, refleksi kritis menjadi penting agar kita menyadari bahwa di balik niat baik dan solidaritas, sering tersembunyi relasi kuasa yang membentuk bahkan membatasi otonomi individu. Pernikahan, pada akhirnya, bukan hanya soal dua orang yang saling memilih, tetapi juga tentang bagaimana keluarga dan masyarakat ikut mengambil bagian dalam pilihan tersebut, dengan seluruh modal, ingatan, dan kepentingannya.
Namun, apakah ‘Biba-biba yang lain’ mampu keluar dari kuasa seperti yang dilakukan oleh Puang Ngugi? Bagi Bourdieu, habitus sebagai cara pandang yang ‘menguasai’ itu pada dasarnya struktur yang dibentuk juga. Dalam artian, seseorang dapat berubah sesuai dengan arena yang sedang ia hadapi dengan modal-modal yang dimiliki. Sehingga, seiring berjalannya waktu, seorang keponakan akan mampu mengakumulasi modalnya sendiri seperti yang diusahakan oleh Biba sebagai perempuan yang realistis dengan penuh pertimbangan di tengah perlakuan tantenya yang ‘mengekang’.
Kendati demikian, relasi kekuasaan yang dibangun oleh Puang Ngugi sebenarnya tidak cukup memberikan kungkungan literal dan bergerak monoton kepada Biba. Kelak, ketika seorang keponakan telah menampung modal yang mumpuni dan seorang tante telah terbatas dari segi fisik dan modal lainnya, sang Biba-biba yang lain mampu bergerak dengan nuansa kreativitas dalam mengakumulasi modal-modalnya secara ideal dan sistematis, sehingga relasi kuasa akan berbalik. Dalam buku Reka Sakti yang berjudul Njawani menegaskan bahwa dimensi waktu menjadi vital dalam pembalikan relasi itu. Waktu akan mengubah secara perlahan.
Pada akhirnya, di tengah kompleksitas tekanan batin dan keterbatasan finansial di kehidupan Biba dan Rizky, mereka secara tidak sadar mengajarkan akan kekuatan sebuah cinta. Karena cinta lah yang mereka bangun, pegang, hingga menjadi prinsip, keduanya menjadi bertahan sampai gelanggang pelaminan. Keduanya hadir sebagai tokoh yang menemukan caranya sendiri dalam menghormati nilai-nilai yang sedang mengelilinya, sehingga mereka mampu menciptakan pernikahan yang bermakna walaupun pada akhirnya, pestanya berujung kacau akibat kematian salah seorang warga saat senang berjoget bersama Puang Lallo. Akibatnya, banyak dari tamu undangan meninggalkan pesta dan tak sempat memberikan uang passolo’nya. Seketika Puang Ngugi dan Puang Lallo terpukul atas gagalnya misi politisnya itu.
Berbeda dengan kedua mempelai, Biba dan Rizky tetap melanjutkan sesi ‘tudang botting-nya’ dengan berdansa ria sambil berpesan satu sama lain, agar tetap merasakan atmosfer kebahagiaan di hari itu. Perjalanan hidup mereka penuh dengan kompleksitas perasaan saat-saat keduanya mencoba menavigasikan ekspektasi keluarga, tanggung jawab keuangan, dan arti kebahagiaan sejati.
Editor: Kamsah Hasan