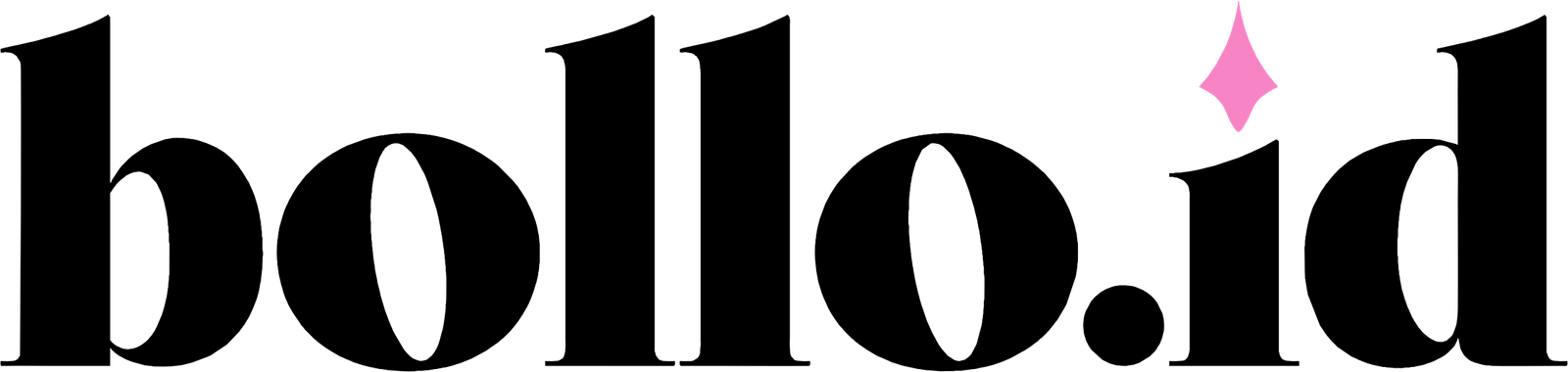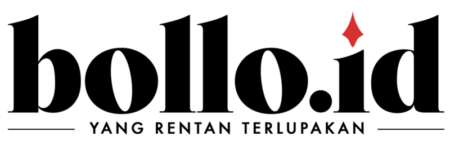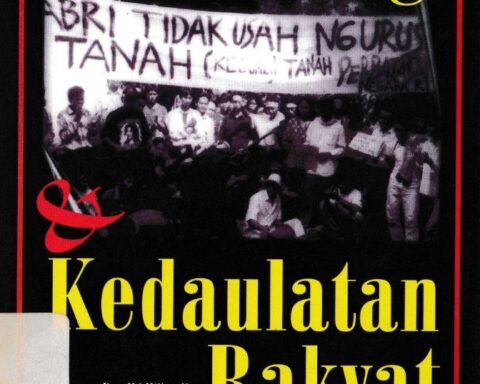Dua puluh tahun lalu, Indonesia dihadapkan pada sebuah ujian besar tentang bagaimana negara memaknai “kesehatan” dalam ranah politik. Pencalonan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada Pilpres 2004 dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum setelah Ikatan Dokter Indonesia memberi rekomendasi bahwa kondisi penglihatannya tidak memenuhi syarat “sehat jasmani dan rohani”.
Kala itu, belum ada Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, belum ada UU Disabilitas, dan kesadaran publik tentang perbedaan antara “sakit” dan “disabilitas” masih rendah. Kebutaan atau low vision digunakan sebagai indikator ketidakmampuan, seolah-olah tubuh yang berbeda otomatis berarti kapasitas mental dan kepemimpinan ikut berkurang.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Pelajaran itu penting kita ingat ketika menyimak apa yang terjadi di Parepare hari ini. Di Kelurahan Ujung Bulu, seorang calon Ketua RW bernama Sultan, atau Bang One, memenangkan suara terbanyak namun kemudian dicoret dari pencalonan karena ia dianggap tunanetra. Syarat Perwali tentang “sehat jasmani dan rohani” ditafsirkan sebagai alasan untuk membatalkannya. Sebagian warga menyuarakan keberatan, mengatakan tidak ingin dipimpin oleh seseorang yang dianggap “tidak sehat”, sementara kelompok warga lainnya—termasuk komunitas disabilitas—turun menolak keputusan tersebut.
Peristiwa ini menunjukkan bagaimana istilah yang tampaknya netral bisa berubah menjadi alat legitimasi untuk menyingkirkan seseorang dari ruang demokrasi. Padahal, Sultan adalah petahana dengan pengalaman sepuluh tahun memimpin RW; ia mengetahui dinamika warganya, memahami persoalan kampung, dan telah terbukti mampu. Ia juga mempertanyakan mengapa keberatan terhadap dirinya diproses setelah masa sanggah berlalu. Ketika standar fisik dijadikan alasan lebih kuat dibanding mandat warga, maka demokrasi di tingkat akar rumput sedang tersandung bias.
Dalam konteks hukum, arah kebijakan kita sejatinya sudah tegas. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meletakkan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan kesempatan, dan akomodasi yang layak sebagai fondasi perlindungan warga negara. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) melalui UU No. 19 Tahun 2011, di mana Pasal 29 CRPD menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak penuh untuk dipilih dan memegang jabatan publik, dengan kewajiban negara menyediakan aksesibilitas dan dukungan teknologi bila diperlukan.
Jika kerangka hukum ini dipatuhi, maka ketunanetraan tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk menganulir hak politik seseorang—terutama setelah ia memenangkan suara mayoritas.
Model sosial disabilitas, yang hari ini menjadi landasan banyak kebijakan inklusif, mengajarkan bahwa hambatan bukan pada tubuh individu, tetapi pada lingkungan yang tidak dirancang untuk merangkul keberagaman. Tugas Ketua RW dapat dijalankan dengan teknologi pembaca layar, pendamping administrasi, notulensi aksesibel, dan pola rapat yang inklusif. Dalam logika ini, persoalan bukan pada mata yang tidak melihat, tetapi pada sistem yang belum menyesuaikan cara kerjanya.
Di sisi lain, persoalan di Parepare juga menyinggung aspek tata kelola: keberatan yang diproses setelah hasil pemilihan keluar, musyawarah yang memutuskan diskualifikasi pasca-putusan, dan rekomendasi “kaji ulang” yang menunjukkan ada ketidakpastian prosedural. Demokrasi hanya bermakna ketika aturan main ditegakkan konsisten, bukan berubah mengikuti tekanan atau tafsir yang sempit.
Sebagai Kepala Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin, tahun lalu saya bertemu langsung dengan Wali Kota Parepare dalam acara Expo Pengabdian Masyarakat Unhas di Kota Parepare. Dalam pertemuan itu beliau menyampaikan komitmen kuat untuk memastikan warga disabilitas Parepare memperoleh kesempatan berkembang secara setara dan memperoleh hak-haknya dengan adil. Karena itu, saya percaya wali kota memiliki peran penting untuk menyelesaikan kasus ini dengan adil, selaras dengan semangat UU Disabilitas, CRPD, serta nilai inklusi yang sudah beliau tegaskan sendiri. Harapan saya, kepemimpinan daerah tidak hanya mengikuti huruf aturan, tetapi juga jiwa keadilannya.
Kita juga punya contoh konkret bagaimana ruang yang inklusif melahirkan pemimpin yang bermakna. Di Universitas Hasanuddin, kampus telah menerima mahasiswa dengan ragam disabilitas dan meningkatkan fasilitas aksesibilitas melalui Pusat Disabilitas dan banyak sumber daya di Unhas. Salah satu lulusannya, Nabila May Sweetha, alumni Ilmu Politik yang juga penyandang disabilitas penglihatan (selesai 2025), kini dipercaya sebagai Staf Ahli Wali Kota Makassar untuk isu disabilitas dan kepemudaan. Nabila adalah bukti bahwa ketika akses dibuka, kesempatan diberikan, dan stigma disingkirkan, maka kemampuan seseorang dapat berdiri tegak tanpa terhalang tubuhnya.
Contoh Nabila seharusnya menjadi inspirasi bagi Kota Parepare—baik bagi warganya maupun aparatur pemerintahnya—untuk melihat bahwa disabilitas tidak identik dengan ketidakmampuan. Perbedaan fisik tidak pernah menjadi ukuran moralitas, kecerdasan, atau kepemimpinan. Yang membedakan hanyalah apakah lingkungan memberi akses atau tidak.
Kasus Sultan kembali mengingatkan kita pada pertanyaan mendasar: apakah demokrasi kita cukup matang untuk menilai warga berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan berdasarkan fungsi inderanya? Apakah kita siap memaknai keberagaman sebagai nilai yang memperkaya kehidupan bersama, bukan sebagai alasan untuk menyingkirkan?
Sudah saatnya kita mengakui bahwa keberagaman manusia—termasuk keberagaman kemampuan fisik, sensorik, mental, atau intelektual—bukan ancaman, melainkan cara hidup terbaik. Cara hidup di mana kita saling mengenal, saling memahami, dan bekerja sama untuk kesejahteraan bersama. Dan jika demokrasi hendak bertahan, maka ia harus menjadi rumah bagi semua orang, termasuk mereka yang matanya tidak melihat, tetapi mampu menerangi ruang publik dengan kepemimpinannya.
Daftar Referensi
- Laporan pencoretan KH Abdurrahman Wahid dari pencalonan presiden tahun 2004 dan peran rekomendasi kesehatan (Kompas, Liputan6, The Jakarta Post/Jawawa, Hukumonline, Tribun Manado).
- Pemberitaan kasus Sultan, calon Ketua RW 8 Ujung Bulu Parepare, termasuk protes warga dan narasi pembatalan.
- Peraturan: UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD.
- Literasi model sosial disabilitas dan narasi anti‑ableisme.
- Dokumentasi program inklusi Universitas Hasanuddin, Pusat Disabilitas Unhas, serta profil Nabila May Sweetha.
Editor: Kamsah Hasan