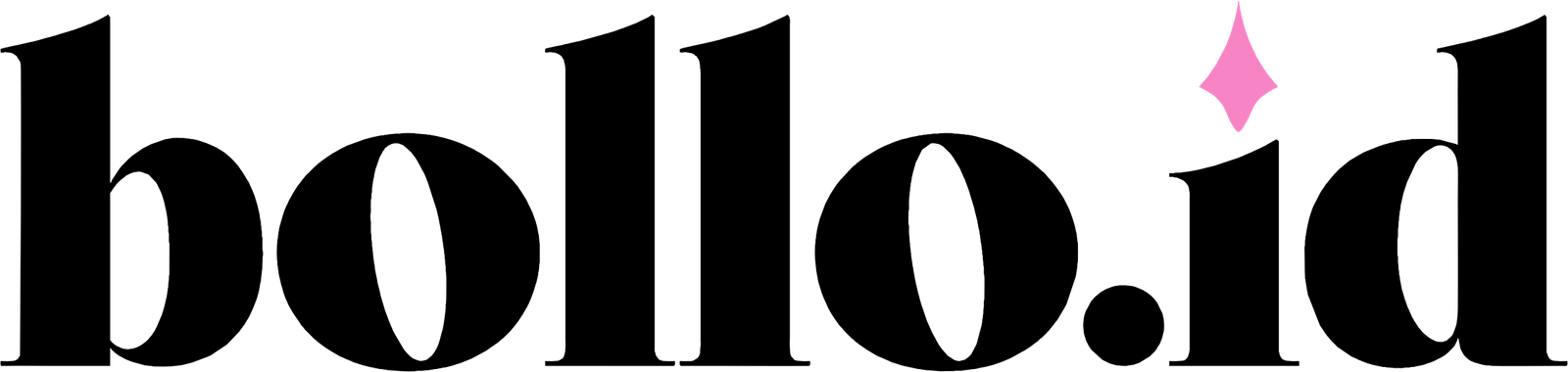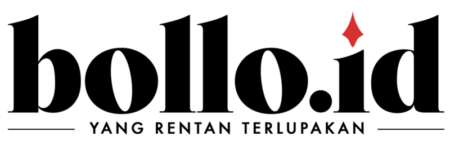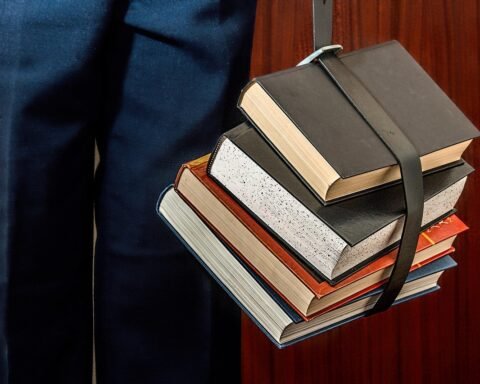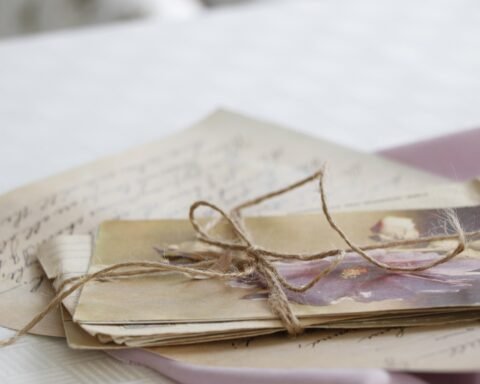Dalam sebuah tulisan di Rakyat Sulsel berjudul “SMSI Sulsel dan Pengurus PWI Sulsel Sesalkan Jurnalis Muda Mau Berdemo Bela Tempo yang Dinyatakan Bersalah Secara Etik,” Mappiar seolah memberi khotbah kilat. Para jurnalis muda, katanya, tak seharusnya membela Tempo—media yang telah dinyatakan melanggar etik oleh Dewan Pers.
Sekilas, pernyataan itu tampak seperti nasihat moral dari seorang yang lebih dulu menapaki jalan jurnalistik kepada generasi muda. Namun jika kita tengok lebih dalam, justru di sanalah letak persoalannya. Ia menegur tanpa sempat bertanya, misalnya, mengapa jurnalis muda di berbagai daerah merasa perlu turun ke jalan membela sebuah media yang dianggap bersalah?
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Akar Masalah
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggugat Tempo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara perdata sebesar Rp200 miliar. Gugatan itu didaftarkan pada 1 Juli 2025, dengan tuduhan Tempo melakukan perbuatan melawan hukum—padahal perkara ini telah diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers.
Sengketa bermula dari poster berita Tempo.co edisi 16 Mei 2025 berjudul “Poles-poles Beras Busuk”, pengantar dari artikel “Risiko Bulog Setelah Cetak Rekor Cadangan Beras Sepanjang Sejarah.” Artikel itu menyoroti kebijakan Bulog yang membeli gabah tanpa memilah kualitas (any quality) dengan harga tunggal Rp6.500 per kilogram.
Kebijakan ini membuat stok beras Bulog melonjak hingga 4,2 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah. Namun, di lapangan, petani justru mencampur gabah bagus dan buruk, bahkan ada yang menambah air agar beratnya meningkat. Akibatnya, beras di gudang Bulog banyak yang rusak.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Mustafa Layong, menyebut kata “busuk” dalam judul poster bukan penghinaan, melainkan penggunaan bahasa yang sah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti rusak dan berbau tidak sedap. Artikel itu pun mengutip langsung pernyataan Menteri Amran yang mengakui adanya beras rusak di gudang Bulog.
Dewan Pers kemudian menilai ada pelanggaran etik ringan dan memberi lima rekomendasi—empat di antaranya untuk Tempo: mengganti judul, memperbaiki poster, memoderasi konten, dan menyampaikan permintaan maaf. Semua rekomendasi itu dilaksanakan pada 19 Juni 2025, satu hari setelah Tempo menerima dokumen putusan. Poster di Instagram pun diubah menjadi “Main Serap Gabah Rusak.”
Artinya, secara etik dan administratif, kasus ini telah selesai di Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Namun, Amran tetap melayangkan gugatan Rp200 miliar ke pengadilan. Di sinilah persoalan mendasar muncul. Ketika mekanisme etik diabaikan dan sengketa pers dibawa ke ranah hukum perdata, maka kita sedang menyaksikan ancaman terhadap kemerdekaan pers yang dijamin konstitusi.

Pernyataan Mappiar di Rakyat Sulsel luput menyoroti konteks ini. Ia menegur para jurnalis muda karena dianggap tidak memahami etika, tapi diam terhadap fakta bahwa pers sedang dihadapkan pada upaya pembungkaman melalui jalur hukum yang justru bertentangan dengan UU Pers.
Padahal, UU Pers dengan tegas melarang kriminalisasi kerja jurnalistik. Sengketa pemberitaan harus diselesaikan melalui Dewan Pers, bukan pengadilan. Mekanisme ini dibuat agar pers bisa bekerja dengan ruang kritis—tanpa ancaman gugatan miliaran setiap kali menyentuh kepentingan pejabat.
Etika Diperalat Kekuasaan
Saya membaca keberanian para jurnalis yang berdemo bukan sebagai pembelaan buta terhadap Tempo, melainkan sebagai tanda bahwa nurani mereka masih hidup. Mereka bukan menolak etika, tetapi menolak cara kekuasaan memperalat etika untuk membungkam kritik.
Sebab, pers bukan lembaga suci, tapi juga bukan musuh negara. Ia adalah anjing penjaga (watchdog) demokrasi—yang menggonggong bukan karena benci, tapi karena mencium bahaya. Dan kita tahu, tak ada penguasa yang nyaman mendengar gonggongan itu.
“Kalau tidak tahan dikritik, silakan mundur,” ujar Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Nany Afrida.
Mappiar menyayangkan para jurnalis muda yang dianggap salah langkah. Namun sejarah pers Indonesia justru dibangun dari langkah-langkah yang “salah” menurut ukuran zamannya. Tempo pernah dibredel karena menulis tentang dugaan korupsi dalam pembelian kapal perang bekas dari Jerman Timur. Pemerintah Orde Baru beralasan pemberitaan tersebut dapat membahayakan stabilitas nasional.
Kini, tekanan datang bukan hanya dari kekuasaan, tapi juga dari sesama insan pers yang berbicara atas nama moral. Kita menyaksikan pergeseran yang lembut namun berbahaya.
Di banyak daerah, solidaritas antarjurnalis semakin pudar, tergantikan oleh relasi yang dekat dengan penguasa lokal dan pengusaha besar. Alih-alih berdiri di sisi publik, sebagian organisasi pers kini lebih sibuk mengamankan “hubungan baik” dengan pejabat yang mereka liput. Kritik terhadap kekuasaan menjadi sesuatu yang tabu, seolah keberanian bersuara adalah bentuk pengkhianatan terhadap “etika” korps.
Dalam suasana seperti itu, wajar jika jurnalis muda merasa terasing di rumahnya sendiri. Mereka tumbuh di tengah media yang gemar menulis rilis pemerintah, tapi ragu mengulik kebenaran yang menyakitkan. Mereka melihat senior-seniornya menandatangani kerja sama dengan pejabat yang seharusnya mereka awasi. Maka, ketika Tempo diserang dengan gugatan, mereka tahu bahwa yang sedang digugat bukan hanya satu media, melainkan semangat kritis yang tersisa.

Normalisasi Tekanan terhadap Pers
Mungkin kita sedang memasuki zaman ketika “nama baik” menjadi komoditas paling mahal di negeri ini. Harga satu nama—apalagi nama pejabat—bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Di atas meja pengadilan, reputasi dihitung seperti saham. Naik-turun nilainya tergantung siapa yang merasa dirugikan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggugat Tempo dua ratus miliar rupiah. Angka yang begitu besar, seolah-olah reputasi pejabat adalah perusahaan raksasa yang sahamnya terjun bebas hanya karena sebuah berita. Tapi bahaya terbesar bukan pada gugatan itu sendiri, melainkan pada rasa wajar yang pelan-pelan tumbuh di sekitar kita. Ketika gugatan sebesar itu tidak lagi membuat kita terkejut, maka yang rusak bukan hanya logika, tapi juga keberanian berbicara.
Sebelumnya, lima mantan staf khusus Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menuntut dua media daring—herald.id dan inikata.co.id—beserta wartawan dan narasumbernya. Tujuh ratus miliar rupiah. Angka yang bahkan tak masuk akal dalam neraca perusahaan media mana pun. Tapi mereka menuntut juga. Karena di negeri ini, rupanya kemarahan bisa dikonversi menjadi angka, dan rasa tersinggung bisa menjadi bisnis hukum.
Kasus itu kemudian kandas di Mahkamah Agung. Hakim menolak kasasi para penggugat, menegaskan bahwa rasa tersinggung tak bisa menjadi dasar untuk membungkam berita. Pelajaran itu tampaknya tak sampai ke meja kekuasaan.
Tak lama kemudian, Andi Nurlia Sulaiman—adik Menteri Pertanian—menggugat media lain, Legion News, senilai dua ratus miliar rupiah. Lagi-lagi, angka yang fantastis, untuk sebuah berita yang barangkali hanya dibaca beberapa ribu orang.
Ada pola yang mulai terlihat di sini. Mereka yang punya nama besar, punya jabatan, atau punya hubungan darah dengan kekuasaan, merasa berhak menggugat siapa pun yang mengusik kenyamanan mereka. Ini bukan lagi soal hukum, tapi soal psikologi kekuasaan. Tentang mereka yang menganggap publik tak pantas tahu, dan jurnalis tak layak bertanya.
Padahal Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan pemerintah tidak bisa menggugat atas nama pencemaran nama baik. Sebab, lembaga negara tidak punya “nama pribadi” yang bisa dicemarkan. Kekuasaan, dengan segala keagungannya, seharusnya tahan terhadap kritik, bukan alergi terhadapnya.
Namun, barangkali kita memang sedang hidup di masa ketika kuasa ingin memiliki semuanya—termasuk kata terakhir tentang dirinya sendiri. Dalam dunia seperti itu, jurnalisme yang kritis adalah musuh, bukan mitra. Dan ruang publik perlahan menjadi sunyi, dipenuhi gugatan, bukan percakapan.
Mungkin kelak kita perlu bertanya. Berapa sebenarnya harga kebebasan pers—jika setiap kalimat bisa ditagih dua ratus miliar rupiah?
Inilah ancaman baru bagi jurnalisme. Bukan lagi pembredelan fisik, tetapi pembungkaman yang legal, halus, dan tampak sah di mata hukum. Etika dijadikan tameng dan hukum dijadikan senjata. Sementara publik, yang seharusnya dilindungi oleh jurnalisme kritis, perlahan kehilangan suara yang membelanya.
Mungkin benar, Tempo keliru. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika etika dijadikan alat kekuasaan, dan pengadilan dijadikan jalan untuk memenjarakan kebebasan pers. Pers boleh salah, tapi haknya untuk menggigit ketidakbenaran tak boleh dicabut. Sebab begitu pers takut menggonggong, rakyat pun kehilangan penjaga pintu yang paling setia.
Dan jika suatu hari, anjing penjaga itu berhenti menggonggong, siapa lagi yang akan membangunkan kita dari tidur yang nyaman itu?