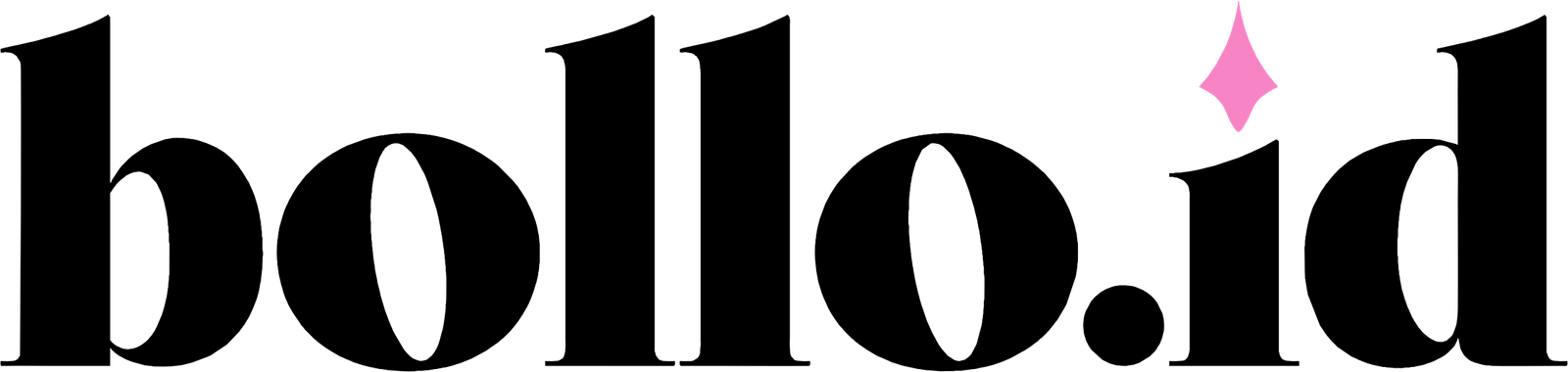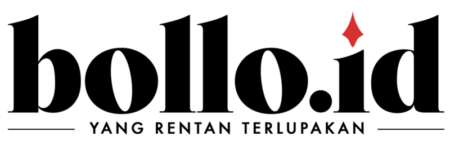Menjelang magrib, di pesisir Kendari, angin laut menyelinap ke ruang tamu tak berdinding. Di antara aroma garam dan debu timbunan, seorang perempuan paruh baya duduk bersila didampingi Jaringan Perempuan Pesisir Sulawesi Tenggara pada Ahad, 7 September 2025.
Matanya berkaca-kaca, sesekali menatap lantai yang retak. Suaranya lirih, terkadang meninggi, menahan beban yang terlalu berat untuk diungkapkan. Beberapa kali ia berhenti, menelan isak, sebelum melanjutkan cerita luka yang menghantuinya sehari-hari.
Ia menceritakan peristiwa pada Maret 2025 lalu, ketika dua anaknya yang masih berumur 6 dan 11 tahun menjadi korban kekerasan seksual. Kala itu, sepulangnya dari pasar, ia mendapati kiosnya sudah berantakan. Barang dagangan berserakan di lantai. Kedua anaknya tak terlihat. Tak lama kemudian, sang kakak pulang dengan wajah pucat dan bibir gemetar.
“Ibu, F (6) diganggu. R (11) juga dipegang-pegang,” kata anak itu dengan polos, yang menyisakan luka.
Esok harinya, tepat 25 Maret 2025, sang ibu melapor ke kantor polisi terdekat. Namun diarahkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kendari. Dengan harapan, anak-anaknya mendapatkan perlindungan visum segera dilakukan, dan pelaku diproses. Tetapi, jawaban polisi malah membuatnya semakin lemas.
“Ibu pulang dulu, nanti dihubungi,” ucap dia menirukan perkataan polisi.
Hari silih berganti, telepon tak kunjung datang. Ia pun meminta bantuan pendampingan dari JPP Sultra dan kasus ini diberitakan kompas.id, barulah polisi mulai bergerak.
Tetapi ibu korban justru dilaporkan balik dengan tuduhan penganiayaan. Alasannya telah menampar lelaki yang diduga telah mencabuli anak-anaknya. Tuduhan itu digunakan aparat sebagai alat untuk menekan.
“Terus pihak PPA menyarankan saya untuk atur damai,” ujarnya dengan suara serak. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada tamparan yang ia lakukan sendiri.
Praktik menormalisasi ‘atur damai’ dalam kasus kakerasan seksual bukanlah fenomena baru, kata Ketua JPP Sultra, Mutmainnah. Berdasarkan pengalamannya mendampingi korban, kasus F dan R hanyalah satu contoh dari pola penanganan yang berulang.
Dikasus F dan R ini, Mutmainnah bilang modus atur damai yang dilakukan pelaku dan aparat yakni dengan cara mengintimidasi keluarga korban. Bahkan polisi mengatakan kasus ini belum terlalu parah, baru sekedar dilecehkan.
“Tapi kan dalam UU TPKS, kita sebagai perempuan tidak terima dilecehkan dalam bentuk apapun, karena itu salah satu dari kekerasan seksual. Polisi selalu mengatakan bahwa itu belum, belum diperkosa dan bisa diatur damai begitu, supaya kasus tidak diperpanjang” ujar Mutamainnah.
Ia menyarankan, unit PPA seyogyanya memenuhi hak-hak korban. Tidak memberi opsi atur damai, mengintimidasi korban, dan memberikan dukungan kepada Ibu korban. Bahkan harus mempertimbangkan kondisi mental korban dan Ibunya.
“Tapi pihak polisi mengaitkan antara kasus kekerasan seksual dan kasus pemukulan. Ini kan bedah ranah. Disinilah celahnya pihak kepolisian mengintimidasi Ibu korban dan pada akhirnya kasus tersebut mandek,” tutur dia.
Mutmainnah menegaskan semua bentuk kekerasan seksual adalah tindak pidana, tanpa kompromi. “Tidak ada kategori ‘belum parah’. Semua bentuk kekerasan seksual adalah kejahatan,” tegasnya. Pasal 5 ayat (3) UU TPKS bahkan menyatakan, tidak boleh ada penyelesaian perkara di luar peradilan. Bahkan dalam pasal 10 Undang-undang saksi dan korban menyebutkan bahwa korban yang sedang melapor tidak dapat dilapor balik.
JPP Sultra mencatat, ada 100 kasus yang mereka dampingi di Tahun 2023-2025. Spektrum kasusnya beragam mulai dari hak perempuan-perempuan pesisir atas pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga perlindungan Kekerasan Didalam Rumah Tangga (KDRT).
“Dari dua kasus kekerasan seksual yang kami dampingi, satu ada upaya aparat untuk atur damai, satunya lagi berhasil diatur damai,” sebutnya.
Terpisah, Kepala Unit PPA Subdit IV Ditreskrimum, Polda Sulawesi Tenggara, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Pejjy Simon menjelaskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur kerja polisi dalam menangani kasus kekerasan seksual.
Pejjy berujar, tahapannya dimulai dari laporan polisi. Setelah masuk, polisi segera menindaklanjuti dengan melakukan visum. Rumah Sakit Bhayangkara menjadi rujukan utama Polda Sultra untuk memastikan kondisi korban tercatat secara hukum dan medis.
Namun, prosedur tidak berhenti di sana. Bagi korban anak, lanjut Pejjy, kepolisian menyiapkan pendampingan khusus. Unit PPA bekerja sama dengan UPTD PPA dan Dinas Sosial untuk memberikan dukungan psikologis serta distribusi layanan pendampingan yang lebih terarah.
“Begitu laporan diterima, kami langsung berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait. Kalau korbannya anak, maka pendampingan harus lebih intensif,” jelas Pejjy saat ditemui di Polda Sultra, Senin, 8 September 2025.
Meski begitu Pejjy mengakui bahwa laporan kerap kali terhenti di tengah jalan. Hambatannya adalah pelaku yang melarikan diri dan saksi enggan memberikan keterangan.
Alasannya beragam, mulai takut berurusan dengan polisi hingga tidak ingin membuang waktu dalam proses hukum. Situasi ini, menurut Pejjy, membuat upaya pembuktian menjadi lebih rumit.
“Kadang saksi kuat menolak hadir, padahal keterangan mereka penting. Tapi itu bukan hambatan bagi kami. Kalau saksi A tidak mau, kami cari saksi lain yang bisa mendekati,” katanya.
Pejjy menepis tudingan ada upaya polisi menawarkan ruang kompromi hukum serta atur damai pada kasus kekerasan seksual, seperti yang menimpa F dan R.
“Tidak ada sih yah. Apapun itu tidak, apalagi opsi atur damai,” ujarnya.
Kemudian jurnalis mencoba bertanya soal mitigasi pencegahan dan tindakan agar tak ada praktik atur damai lagi. Tetapi Pejjy tak menjawabnya.
Bahkan narasi resmi Pejjy tersebut bertolak belakang dengan pengalaman JPP saat mendampingi korban.
Kasus ini juga mendapat perhatian dari kuasa hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arif. Ia mengatakan pananganan kasus kekerasan seksual terhadap F dan R adalah sistemik, bukan sekadar teknis.
“Pasal 23 UU TPKS jelas melarang restorative justice dalam kasus kekerasan seksual. Perdamaian tidak diperbolehkan, kecuali untuk pelaku anak. Kalau pelaku dewasa, tidak dimungkinkan,” katanya.
Polisi, menurut Arif, sering menyalahgunakan konsep restorative justice atau umumnya disebut keadilan restoratif.
Keadilan restoratif yaitu sebuah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada perbaikan kerusakan akibat kejahatan, bukan hanya menghukum pelaku. Berfokus pada pemulihan dan penyembuhan, bukan sekadar hukuman, dan melihat keadilan sebagai upaya kolektif dari semua pihak yang terdampak.
Menurut Komnas HAM, keadilan restoratif ini punya banyak kelemahan misalnya bisa menjadi jalan pintas untuk kasus transaksional dan aturan teknisnya juga belum jelas. Yang lebih buruknya keadilan restoratif ini tidak bisa dijalankan bila ada relasi kuasa.
Dalam kasus F dan R, kata Arif, polisi menggunakan konsep tersebut untuk menghentikan kasus, bukan memulihkan korban. Praktik barter perkara, di mana laporan balik dari pelaku dipakai melemahkan korban, jelas mencederai hukum.
“Kekerasan seksual itu delik umum yang tidak bisa dicabut. Kalau polisi melakukan tukar guling, korban terluka dua kali,” tegasnya.
Arif menambahkan, akar masalahnya ada pada kapasitas dan budaya internal polisi. Banyak penyidik tidak memahami UU TPKS, perspektif gender, atau HAM. “Pertanyaannya, kenapa aparat tidak paham?. Apakah ada pelatihan khusus? Apakah ada pengawasan? Ini yang harus dievaluasi,” jelasnya.
Berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan, sepanjang Tahun 2024, Komnas Perempuan menerima total 15 kasus kekerasan seksual di Sulawesi Tenggara, dengan rincian delapan kasus kekerasan seksual; lima Kekerasan Seksual Berbasis Ekonomi (KSBE), satu perkosaan anak, satu pelecehan seksual non-fisik. Data tersebut memperlihatkan tren bahwa betapa rentannya perempuan, termasuk anak-anak, terhadap kekerasan yang sering tidak tertangani secara memadai.
Sementara, Ketua Resource Center Komnas Perempuan, Chatarina Pancer Istiyani, mengkritik praktik ‘atur damai’ yang disarankan pelaku dan polisi dalam kasus F dan R. Mekanisme terakhir, kata Komnas Perempuan tidak menjamin kedamaian bagi korban. Sebaliknya, ‘atur damai’ justru melindungi pelaku, memperkuat ketimpangan kuasa, dan menimbulkan reviktimisasi—trauma kedua akibat tindakan aparat yang seharusnya memberi perlindungan.
“Atur damai itu hanyalah kedamaian semu. Kami selalu membela hak-hak korban dan penegakan hukum yang berkeadilan gender,” ujar Chatarina. Negara, katanya, harus memastikan aparat menegakkan hukum adil, berpihak pada korban, dan menindak aparat yang melanggar.
Pelaksana tugas Direktur Eksekutif Yayasan Pulih, Livia Istania DF Iskandar, mengapresiasi tindakan F dan R yang mau bicara dan menyampaikan kepada ibunya terkait kekerasan seksual yang dialami. Sebab menurutnya, tidak banyak anak-anak yang mau bicara.
“Menurut saya kedua anak-anak ini luar biasa. Mereka kemudian menyampaikan kepada ibunya, dan itu bagus juga bahwa ada pendampingan dari JPP,” ucapnya.
Psikolog anak dan remaja dari Yayasan Pulih, Ika Putri Dewi. Ika mengatakan pemulihan anak korban tergantung pada kepastian bahwa pelaku dihukum. Jika pelaku bebas atau opsi atur damai, anak-anak mulai meragukan pengalaman mereka sendiri.
“Mereka berpikir, ‘Om itu salah atau tidak?. Saya yang salah?’ Nilai bahwa yang jahat harus dihukum jadi kabur. Ini berbahaya, karena menimbulkan rasa bersalah pada anak,” jelas Ika.
Kondisi tersebut kata Ika menjadi semakin kompleks karena ibu korban tertekan. Ibu korban bukan hanya menghadapi kenyataan anaknya disakiti, tetapi juga laporan balik dari terduga pelaku. Karena trauma, emosional ibu akan memengaruhi perilaku anak-anak.
“Relasi dengan anak terganggu. Padahal peran ibu krusial untuk pemulihan. Kalau ia tidak berfungsi dengan baik, anak-anak kehilangan dukungan utama,” ujarnya.
Ika juga menyayangkan situasi seperti ini sebab negara tidak hadir dan melindungi korban. Padahal UU Perlindungan Anak dan UU TPKS tegas melarang penyelesaian di luar jalur hukum. Karena menurutnya, atur damai bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga pelanggaran prinsip perlindungan korban.
“Kalau aparat benar-benar mau menjalankan undang-undang, kasus seperti ini tidak akan mengendap. Pelaku harus segera diamankan. Kalau pelaku minta damai, itu justru tanda ia (pelaku) tahu bersalah. Negara mestinya menolak, bukan melayani,” kata Ika.
Secara psikologis, ketegasan polisi merupakan bagian dari terapi psikologis bagi anak. Anak belajar; yang salah akan dihukum, dirinya tidak bersalah, negara melindungi. Sebaliknya, anak-anak dipaksa belajar bahwa kejahatan bisa ditawar dan keadilan dinegosiasikan.
Di akhir kisahnya, ibu korban tampak lelah, termenung, mentalnya terkuras. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, bahkan muncul pikiran gelap ingin minum racun.
“Seandainya kasus ini bisa langsung ke pengadilan, ke pengadilan mi saja lebih baik. Kita pergi mengadu ke polisi tidak ada gunanya. Mati rasa’mi sama polisi,” tutupnya dengan wajah menunduk yang terjebak di antara trauma dan atur damai dipaksakan.
Editor : Didit Hariyadi