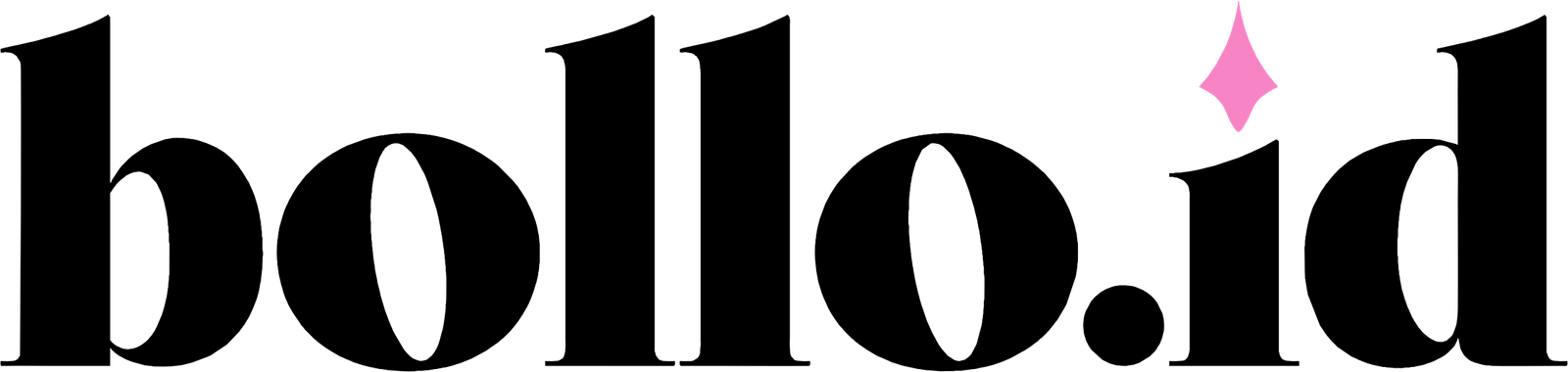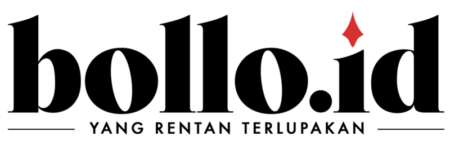Bollo.id – Pertengahan Desember 2025, sengketa tanah di Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, kembali menyita perhatian publik. Objek sengketa bukan sekadar sebidang tanah, melainkan tongkonan ka’pun—rumah adat yang dihormati dan menjadi pusat ikatan kekerabatan sebuah keluarga besar Toraja.
Eksekusi yang dilakukan pada Kamis, 5 Desember 2025, berujung ricuh. Sekitar pukul 14.00 WITA, aparat keamanan dan sebuah eskavator mendekati tongkonan yang hendak dieksekusi atas perintah Pengadilan Negeri Makale. Warga dan keluarga tergugat berdiri menghadang di depan rumah adat itu.
Benturan tak terhindarkan. Aparat melepaskan tembakan peluru dan gas air mata ke arah warga. Sejumlah orang terluka dan terpukul secara psikologis menyaksikan rumah adat yang selama ini menjadi penanda identitas keluarga dirubuhkan.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Carli, 23 tahun, berada di lokasi saat kejadian. Ia membantu sebagai tenaga medis darurat.
“Perasaanku campur aduk sekali waktu itu,” kata Carli, Senin, 22 Desember 2025.
Ia melihat orang-orang menangis, benda bermakna diratakan, dan ruang hidup yang selama ini mereka jaga dilenyapkan dalam hitungan jam. Bagi Carli, peristiwa itu memperlihatkan bagaimana hukum bekerja secara dingin di atas tubuh dan kehidupan warga.
Eksekusi itu tak hanya menyentuh bangunan yang disengketakan. Ruang hidup keluarga meluas di luar objek sengketa yang selama ini mereka pahami.
Seorang kakek berusia lebih dari 100 tahun terpaksa diangkat keluar dari tongkonan ka’pun saat eskavator mulai bergerak dan suara mesin memecah keheningan kampung.
Amakarelia, 30 tahun, anggota keluarga tergugat, mempertanyakan dasar eksekusi tersebut. Menurut dia, sejak awal sengketa hanya menyangkut tongkonan tanete yang berada di bagian belakang. Objek itu, kata dia, telah diserahkan dan dieksekusi secara sukarela pada 2024.
“Kenapa sekarang tongkonan ka’pun yang mau diambil?” kata Amakarelia, Sabtu, 20 Desember 2025.
Ia menilai pengadilan dan penggugat telah melampaui kesepakatan awal dengan mengambil rumah adat lain yang tidak pernah mereka lepaskan.
Selain soal objek, keluarga juga mempersoalkan waktu dan prosedur eksekusi. Amakarelia mengatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum lanjutan.
“Kami berusaha masukkan gugatan lagi. Sidangnya kemungkinan Januari (2026) nanti,” ujarnya.
Peristiwa eksekusi ini tak hanya dibaca sebagai konflik agraria atau sengketa perdata.
Di Toraja, tongkonan bukan sekadar rumah. Ia adalah simbol kekerabatan, pusat ritual, sekaligus penanda status dan sejarah keluarga.
Budayawan Sulawesi Selatan, Alwy Rachman, menilai eksekusi tongkonan ka’pun sebagai bentuk pengrusakan material kebudayaan. Kebudayaan bekerja bukan sekadar sebagai penanda fisik, melainkan sebagai ruang simbolik yang membangun jarak—jarak yang justru memungkinkan hadirnya empati dan penghormatan.
“Dalam konteks budaya, simbol mengajarkan manusia menghormati yang ‘lain’,” kata Alwy, Minggu, 21 Desember 2025.
Rumah adat, ritus, dan benda-benda budaya tidak pernah berdiri netral. Ia mengandung sejarah relasi, ingatan kolektif, serta lapisan makna yang hidup di tengah komunitas pendukungnya.
Karena itu, ketika simbol budaya direduksi menjadi objek sengketa, yang dipertaruhkan bukan hanya kepemilikan, melainkan juga martabat dan ikatan sosial.
“Tanpa jarak, tidak akan ada penghormatan, tidak akan ada empati,” tuturnya.
Dengan kata lain, menurut Alwy, simbol budaya mengajarkan manusia berempati dan menaruh hormat pada yang lain. Logika hukum yang kaku kerap gagal menangkap kompleksitas relasi sosial yang menyertai objek budaya.
Akibatnya, proses penyelesaian perkara justru berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat adat yang memandang kebudayaan sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari.
Ia pun menyayangkan penyelesaian sengketa yang semata bertumpu pada logika hukum formal semata.
“Penyelesaian sengketa semestinya memasukkan pertimbangan budaya, bukan hanya pertimbangan hukum saja,” kata Alwy.
Kasus di Kurra memperlihatkan ketegangan lama antara hukum negara dan ruang hidup masyarakat adat. Ketika putusan pengadilan dijalankan tanpa kepekaan terhadap konteks kebudayaan, hukum tak lagi hadir sebagai sarana keadilan, melainkan sebagai kekuasaan yang melukai.
Editor: Kamsah Hasan