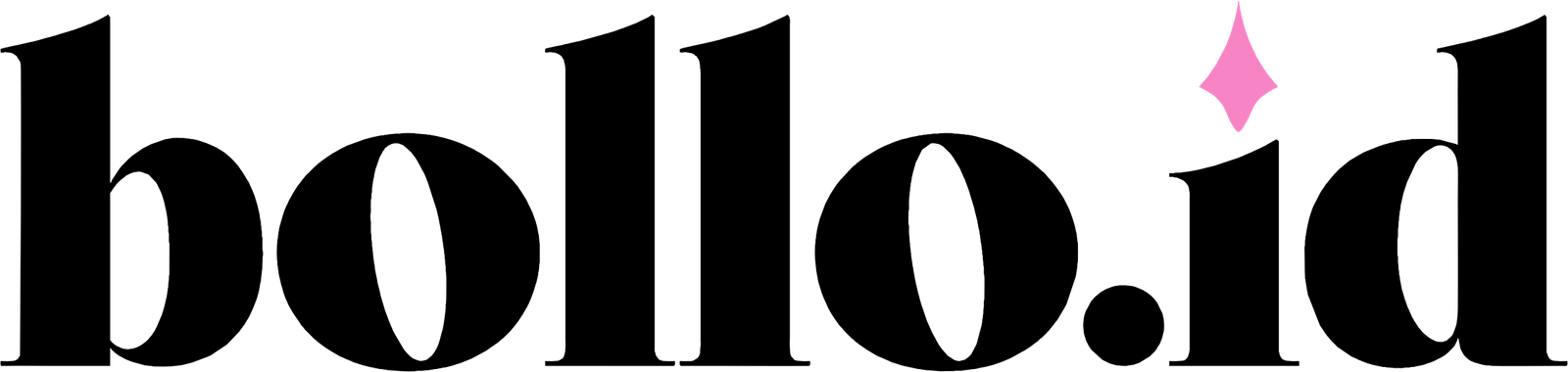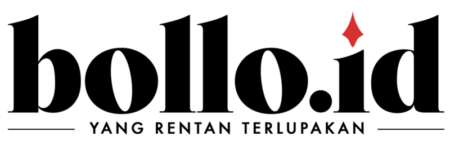Bollo.id — Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022 adalah undang-undang yang mengatur khusus tentang pencegahan, penanganan, dan penghukuman terhadap kekerasan seksual (KS) di Indonesia.
UU ini merupakan langkah penindakan kasus karena sebelumnya KS tidak memiliki landasan hukum yang spesifik. Di Makassar, UU TPKS ini telah menjadi landasan menindaki kasus KS seperti yang terjadi di ruang privat hingga akademik.
“Korban kekerasan seksual tidak lagi dibebani pembuktian dengan mencari saksi lain selain dirinya karena dalam UU TPKS keterangan saksi korban ditambah alat bukti lain dianggap cukup,” kata Wakil Kepala Divisi Advokasi LBH Makassar, Mirayati Amin, kepada Bollo.id, Senin, 7 Juli 2025.
“Jadi, untuk kasus KS yang notabenenya banyak terjadi dalam ruang privat yang minim saksi, UU ini sangat membantu,” lanjutnya.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Selain penanganan, UU TPKS juga memperhatikan pasca-penanganan kasus KS dengan pemulihan korban KS. Salah satu upaya pemulihan itu disebutkan dalam Pasal 70 yang meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan atau kompensasi, dan reintegrasi sosial.
“Selain itu, dalam UU TPKS juga terdapat kewajiban negara terkait pemulihan korban KS. Hal itu diatur secara jelas, termasuk tiap lembaga yang memiliki kewajiban penyedia layanan, seperti UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),” katanya.
YLBHI-LBH Makassar sejauh ini telah menangani tiga kasus dengan menggunakan UU TPKS yang berjalan sampai ke pengadilan negeri. Dua di antaranya sudah vonis dan satu sedang menunggu sidang putusan.
“Kasus A (korban kasus KS di UNM baru-baru ini) menjadi kasus ke-4 yang kami dampingi dengan merujuk pada UU TPKS,” ungkap Mirayanti Amin.
Menggunakan UU TPKS dalam laporan KS berarti mengadvokasi kasus dengan menyebut langsung pasal-pasal dalam UU TPKS saat membuat laporan polisi, dakwaan, atau permintaan perlindungan dari suatu organisasi/lembaga.
UU TPKS mendorong aparat hukum bertindak tidak melulu menggunakan KUHP hingga UU ITE. UU TPKS dinilai lebih komprehensif, spesifik, dan pro korban.
Ketua Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) Sulawesi Selatan, Aflina Mustafainah saat dihubungi Bollo.id juga berkomentar tentang kasus KS di UNM.
Baca juga: Dosen FIS-H UNM Jadi Tersangka Pelecehan Mahasiswa
Katanya, korban bingung mau melapor atau tidak karena memikirkan urusan perkuliahannya yang kemungkinan akan dipersulit dosennya. Itu karena pelaku adalah dosen pembimbingnya.
“Dia misalnya melakukan perlawanan, maka dia tidak selesai (kuliahnya). ‘Bagaimana ya kalau saya tidak selesai, berarti orang tua saya akan lebih lama membiayai atau kalau saya tidak selesai apa yang dicita-citakan (orang tua) itu tidak jadi’. Nah itu yang ambiguitas pada korban,” ujar Pino sapaan akrab Aflina.
Pihaknya sebagai pendamping korban KS menyoroti identitas inisial yang diterbitkan sejumlah media. Menurutnya, penyebutan identitas seperti penamaan (naming) malah menyudutkan korban pada masa pasca-pelaporan KS ke pihak berwenang.
“Korban itu kan seharusnya tidak di-naming. Ketakutan korban sebenarnya yang membuat dia kadang-kadang tidak mau melapor itu karena dia di-naming yang disebut baik inisial maupun nama,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Pino menerangkan perbedaan pendampingan korban perempuan dan laki-laki dalam kasus KS. Meskipun perempuan lebih rentan sebagai korban KS berdasarkan relasi sosialnya secara gender di lingkungan rumah atau sekolahnya, laki-laki juga rentan sebagai korban KS.
“Laki-laki secara umum, dia mungkin masih dapat privilege karena kultur patriarki. Mungkin dia enggak kerja di rumah, ada yang bekerja, porsi pekerjaan (rumah) itu bukan anak laki-laki, dan bisa meningkatkan keterampilannya di sekolah atau kampus, artinya dia tidak rentan,” katanya.
“Tapi bagaimana laki-laki yang rentan? Mungkin anak laki-laki yang sakit-sakitan di lingkungan rumahnya atau mungkin karena dia etnis tertentu, jadi ada kerentanannya ya interseksional, rentan karena minoritasnya, baik gender atau karena dia disabilitas,” Pino menyudahi.
Editor: Sahrul Ramadan