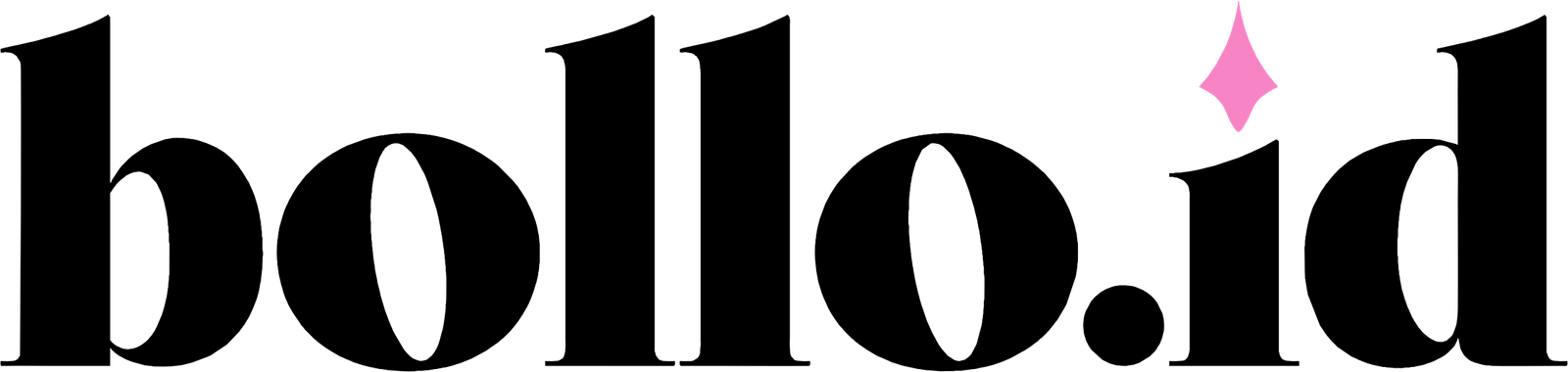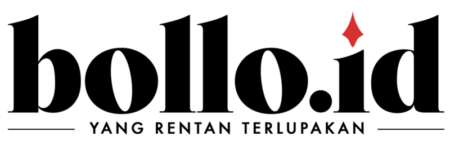Bollo.id – Pada siang hari, layar gawai kita sering menampilkan angka suhu 28 hingga 30 derajat Celsius. Tapi entah mengapa, tubuh terasa seperti dibakar. Keringat menetes di pelipis, kipas tangan bergerak tanpa henti, dan keluhan yang sama terdengar di mana-mana: “Satu orang, tujuh matahari.”
Keluhan itu sudah seperti lelucon kolektif warga kota—cara sederhana untuk menggambarkan teriknya hari-hari di bawah langit beton. Tapi di balik keluhan itu, ada realitas ilmiah yang perlahan membentuk wajah kota kita hari ini.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Ketika Panas Tak Sekadar Terasa
Coba tengok jalanan tengah kota. Di atas aspal yang memantulkan cahaya, tampak garis-garis transparan seperti gelombang hawa panas. Suhu udara naik, bangunan memantulkan panas ke udara, dan kendaraan menambahnya dengan knalpot yang tak berhenti berasap.
Panas itu tak muncul tiba-tiba. Ia lahir dari cara kita membangun kota—menyusun jalan, gedung, dan pemukiman tanpa jeda ruang hijau. Beton dan aspal yang menutup permukaan tanah membuat panas terperangkap lebih lama. Ketika malam datang, panas itu dilepaskan perlahan ke udara. Maka kota tak pernah benar-benar dingin, bahkan selepas senja.
Fenomena ini oleh ilmuwan disebut urban heat island (UHI) – pulau panas perkotaan. Menurut Dabbage dan Shepherd (2015), jika bangunan dan jalan dibangun berkesinambungan tanpa ruang jeda, panas akan semakin terjebak dan memperkuat efek UHI.
Solusinya? Menyisipkan ruang hijau, taman, dan pepohonan di antara bangunan. Tapi seberapa banyak ruang itu tersisa di kota kita?
Makassar Panas
Makassar hari ini menampung 1.477.861 jiwa dengan luas wilayah 175,8 km². Artinya, setiap kilometer persegi dihuni sekitar 8.406 orang—angka yang membuat kota ini terasa sesak di jam siang dan malam.
Kalau lebar bahu seseorang 50 sentimeter, maka dalam satu kilometer bisa berdiri 2.000 orang rapat-rapat. Dengan kepadatan Makassar, sepanjang jalan Benteng Rotterdam ke Museum Kota (1,1 km) bisa diisi empat baris orang berdiri dari ujung ke ujung. Bayangkan panasnya kalau semua berjalan di bawah matahari.
Ruang terbuka hijau seharusnya menjadi peredam panas alami. Namun, menurut data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar tahun 2023, total RTH (publik dan privat) baru mencapai 2.027 hektare—sekitar 11,5 persen dari luas kota. Padahal, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menegaskan minimal 30 persen luas kota harus berupa RTH. Makassar baru sepertiganya.
“(Jika jumlah RTH yang sedikit) dikalkulasi dengan seberapa banyak penciptaan emisi karbon per hari, maka tentu saja tidak bisa menyerapnya,” kata Fatwa Faturachmat, peneliti Forest and Society Research Group Universitas Hasanuddin, Selasa, 2 September 2025.
Belum lagi 885.377 unit kendaraan bermotor yang beroperasi di Makassar (BPS, 2024). Bayangkan 800 ribu mesin yang setiap hari menyalakan api kecil di bawah langit yang sama.
Ketika Kota Jadi Tungku
“Banyak kota di dunia menderita polusi udara karena perencanaan dan desain yang buruk serta lalu lintas padat,” tulis Piracha dan Chaudhary (2022). Pernyataan itu seperti cermin bagi kota-kota Indonesia yang tumbuh lebih cepat daripada pikirannya sendiri.
Menurut Katzschner (2009) dalam penelitian Ibrahim dkk (2018), fenomena UHI sebenarnya adalah “penyimpanan energi matahari di siang hari yang dilepaskan ke atmosfer pada malam hari.” Itulah mengapa malam di kota tetap gerah, bahkan tanpa sinar matahari.
Saat suhu naik, pendingin ruangan menyala di setiap rumah dan kantor—ironisnya, emisi dari listrik dan pendingin itu justru memperparah panas yang sama ingin dihindari.
Panas di Belahan Dunia Lain
Juli lalu, kota Medan mencatat suhu 36 derajat Celsius. “Lemaslah karena kepanasan. Jadi lebih sering minum gitu,” kata Niki, seorang kuli bangunan, dikutip dari Kumparan News. Tak hanya Indonesia. Di Filipina, suhu 38 derajat Celsius membuat pemerintah meniadakan kelas tatap muka hampir setiap hari.
“Gelombang panas pada April dan Mei tahun lalu berdampak pada jutaan siswa,” tulis VOA Indonesia.
Sementara di Amerika Serikat, warga Boston dan Washington harus berjalan di bawah suhu 38 derajat Celsius. Payung, handuk, dan tumbler empat liter menjadi perlengkapan wajib, menurut laporan CNBC Indonesia.
Dunia memanas. Kota-kota makin sesak. Dan kita—manusia di antara beton dan aspal—mulai merasa bahwa “satu orang tujuh matahari” bukan lagi keluhan, melainkan kenyataan.
Menanam Teduh
Kita mungkin tak bisa menyingkirkan panas dari kota. Tapi kita bisa menanam teduh di tengahnya. Menambah pohon, memperluas taman, menyeimbangkan beton dengan tanah. Sebab tanpa ruang hijau, kota hanya akan menjadi tungku yang memanggang warganya perlahan.
Dan keluhan “satu orang tujuh matahari” akan terus terdengar—bukan lagi metafora, melainkan peringatan.
Editor: Kamsah Hasan